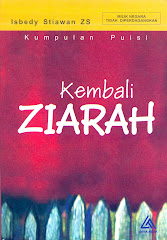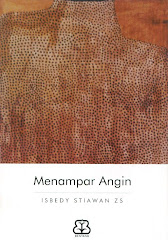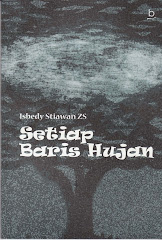Catatan Dari Amzuch ke Fitri Yani*)
Oleh Isbedy Stiawan ZS
PETA sastra Indonesia tidak lengkap, sekiranya ada upaya untuk menghilangkan Lampung. Terutama beberapa tahun terakhir ini. Pasalnya provinsi bagian selatan pulau Sumatera ini cukup besar perannya bagi kesemarakkan sastra di Indonesia, hampir mendekati peran yang pernah disumbangkan, misalnya Sumatera Barat dan Riau pada masanya.
Sejak 1978-an, sebagai awal “melek” sastra di Lampung, ranah sastra Indonesia mulai memperhitungkan daerah ini sebagai lumbung kesusastraan. Dimulai oleh Assaroeddin Malik Zulqornain Ch.(kelahiran 1956), dinamika sastra di Lampung menjadi bagian dari perpetaan kesusastraan Indonesia. Meskipun, boleh jadi, AMZ dianggap bukan pioner kesastrawanan Lampung, karena Motinggo Busye, A.A. Sarmani Adil, ataupun Andi Wasis yang kelahiran atau pernah mencecap tanah Lampung lebih dulu berkiprah. Tetapi kiprah ketiga sastrawan tersebut dilakukan di luar daerah ini.
Amzuch (A.M.Zulqornain Ch) seperti “memelekkan” orang Lampung tentang sastra Indonesia, betapapun Lampung memunyai sastra tradisional (tutur) yang cukup kuat sebagai kekayaan budaya. Karya-karya Amzuch berupa cerpen, puisi, dan esai mewarnai media masa nasional sekaligus menciptakan peta sastra Indonesia tertuju ke Lampung. Sebagai pioner memang Amzuch kemudian seperti menghilang, tapi sejarah kesusatraan (di) Lampung tidak bisa begitu saja meniadakan perannya.
Perkembangan berikut, “pulangnya” para perantau: Iwan Nurdaya-Djafar, Sugandhi Putra, Hendra Z., Djuhardi Basri, dan “masuknya” Naim Emel Prahana karena menyunting gadis Metro berdarah Jawa. Bersamaan “kepulangan” para perantau itu, dinamika sastra di Lampung kian bergolak dengan munculnya Syaiful Irba Tanpaka, Achmad Rich, serta yang berkiprah kemudian yaitu Panji Utama, A.J. Erwin, Iswadi Pratama, Ivan Sumantri Bonang, D.Pramudia Muchtar, Eddy Samudra Kertagama, dan lain-lain—untuk sekadar menyebut beberapa nama.
Forum Puisi Indonesia 87 yang digagas Dewan Kesenian Jakarta di TIM, 3-5 September 1987 adalah tonggak dan bukti bahwa Lampung sedang memasuki peta sastra di Indonesia. Sejumlah sastrawan Lampung (Iwan Nurdaya-Djafar, Syaiful Irba Tanpaka, Sugandhi Putra, Naim Emel Prahana, Achmad Rich) mewakili Lampung di forum yang dihadiri sekitar 87 penyair se-Indonesia tersebut. Selepas Forum Puisi Indonesia 87, media masa bergengsi kala itu—Berita Buana dengan penjaga gawangnya Abdul Hadi W.M., Pelita dengan redaktur tamu Sutardji Calzoum Bachri di samping media lain yakni Merdeka Minggu, Horison, Berita Yudha—banyak memberi peluang bagi publikasi karya para sastrawan Lampung. Bahkan sumbang pemikiran sastrawan Lampung pada saat polemik sastra kontekstual versus sastra transendental yang menyita halaman budaya media masa saat itu.
Pertemuan-pertemuan sastra, yang juga menghadirkan para sastrawan Jakarta dan daerah lain di Lampung. punya peran cukup besar menstimulus generasi sastra berikutnya. Ditambah lagi workshop maupun penerbitan antologi sastra secara berkala dan didanai swadaya telah pula menularkan semangat menulis karya sastra pada generasi muda.
Dan, tak bisa diabaikan dalam membantu perkembangan sastra di Lampung adalah peran media radio—dalam hal ini RRI Cabang Tanjungkarang dan Radio Suara Bhakti (Rasubha)—yang peduli pada dunia sastra dengan menyediakan acara puisi. Bahkan Rasubha menerbitkan antologi puisi bertajuk Memetik Puisi dari Udara (1987). Itu semua sebagai sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan sastra (Indonesia) di Lampung.
Kemudian peran kampus juga cukup besar. Adalah IAIN Radin Intan pernah menoreh sejarah sastra di Lampung ketika mengundang Hamid Jabbar ke kampusnya. Namun sumbangsih terbesar bagi munculnya sastrawan Lampung di kalangan kampus, tentulah Universitas Lampung. Baik kegiatan sastra yang digagas FKIP Jurusan Bahasa dan Seni Unila, apatah lagi yang dilakukan UKMBS Unila melalui gelar pembacaan puisi maupun workshop.
Dari kawah UKMBS Unila muncul sastrawan seperti Ari Pahala Hutabarat, Jimmy Maruli Alfian, Inggit Putria Marga, Diah Indra Mertawirana (kini Diah Merta), Lupita Lukman, dan Elya Harda. Sementara itu, tampilnya Dina Oktaviani yang kala itu berstatus sisiw SMAN 9 Bandarlampung kuga menghentakkan jagat sastra Indonesia. Karya-karya puisi Dina yang masih belia telah bermunculan di Republika, Kompas, dan Media Indonesia. Sayang usia Dina menaburkan keharuman bagi sastra di Lampung tak lama: ia hijrah ke Jakarta dan kini menetap di Yogyakarta.
Sebelumnya, Iswadi Pratama, A.J. Erwin, Panji Utama, Rivian A.Chevy, dan Ivan Sumantri Bonang juga lahir dari UKMBS Unila, namun untuk tiga serangkai Panji-Iswadi-Erwin kemudian lebih dikenal jebolan Forum Semesta (?). Sementara dari FKIP liwat komunitas KSS tercatat Aris Hadiyanto dan Anton Kurniawan. Dari Unila juga lahir penyair Alex R.Nainggolan yang kini kembali ke Jakarta, dua cerpenis: M. Arman AZ dan Ardiansyah. Dinamika dan semaraknya kesastraan di Lampung kian terasa dengan hadirnya Oyos Saroso H.N., Budi P. Hutasuhut, “pulang”nya Y. Wibowo, dan munculnya nama-nama baru yang sekejap lalu menghilang dalam kancah sastra Lampung. Ataupun kehadiran penyair Fitri Yani, seperti “mendadak”, namun mampu menghentak kancah perpuisian di Lampung—juga Tanah Air.
Fitri Yani, kelahiran Liwa 28 Februari 1986 dan mahasiswi FKIP Unila jurusan Bahasa dan Seni, pertama kali saya jumpai puisi-puisinya dimuat majalah budaya GONG, kemudian Kompas, dan Lampung Post. Setelah saya membaca puisi-puisinya, Fitri Yani adalah penyair muda Lampung potensial dan menjanjikan. Ia bisa seiring jalan dengan para sastrawan terdahulu dari daerah ini.
Bersamaan dengan Fitri Yani, saya juga mencatat kehadiran F.Moses. dengan puisi dan cerpennya di Lampung Post dan Suara Pembaruan. Moses, alumnus Sanata Dharma Jogjakarta yang kini bekerja di Kantor Bahasa, sekiranya ia tekuni untuk menulis cerpen, bukan tidak mungkin ia potensial sebagai kreator prosa ketimbang “pengrajin” puisi.
Tetapi, di tengah semaraknya sastra Lampung tampaknya kepenyairan memegang kunci dalam peta sastra di Indonesia. Hal itulah yang menggelitik Nirwan Dewanto lalu menyebut daerah ini sebagai Negeri Penyair, setelah itu F. Rahardi yang mengatakan yang dapat menyamai suburnya kepenyairan Lampung hanyalah Bali, Jatim, dan Yogyakarta.
Lalu, di mana posisi cerpenis dalam konstelasi sastra di Lampung? Minimnya cerpenis Lampung, rasanya hanya diwakili M. Arman AZ, Ida Refliana, F.Moses, dan satu dua nama lainnya, belum mampu menyamai prestasi penyair dalam mengharumkan Lampung di kancah sastra nasional. Tadinya saya berharap pada Diah Merta, namun ia hijrah ke Yogyakarta dan kemudian melahirkan beberapa buku kumpulan cerpen, novel anak, dan novel Peri Kecil di Sungai Nipah.
Untuk memarakkan ranah prosa, berbagai workshop penulisan cerpen pernah dilaksanakan baiki oleh Dewan Kesenian Lampung, Taman Budaya, Kantor Bahasa, serta UMBS Unila dan Kober. Tetap saja penulis prosa langka dari daerah. Kelangkaan ini bukan disebabkan benih ditanam di ladang tak subur. Bukan pula ranah prosa kurang menjanjikan dibandingkan puisi. Oleh sebab itu, saya pikir “kebuntuan” semacam ini mesti dicari solusinyanya. Termasuk pula Lampung, smapai kini, tidak (pernah) lahir novelis. Hal inilah yang pernah “digelitik” kritikus yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UI Maman S. Mahayana di Lampung Post. Maman mengaku sebenarnya sastrawan Lampung potensi menggarap novel, hanya yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketekunan, Di samping peran pemerintah daerah memberi peluang lahirnya novelis, misalnya dengan cara mendanai sastrawan untuk menulis novel ataupun cara-cara lain yang sah.
Namun, di sini saya masih tetap berharap banyak dari dunia kepenyairan. Setidaknya penyair Lampung terus bertambah, sementara yang lebih dulu berkiprah masih tetap “bersaing”.
Dan, bersaing itu wajar. Penyair termuda semacam Fitri Yani sah-sah saja bersaing dengan para pendahulunya. Karena di dunia kreatif seperti kesenian ini, yang diutamakan ialah kreativitas, inovasi, dan terobosan-terobosan. Kita tunggu saja Fitri Yani yang makin “menjadi” sebagai penyair Lampung—yang tentu saja Indonesia.
Selain itu, para penyair di antaranya Inggit Putria Marga, Jimmy Maruli Alfian, Ari Pahala Hutabarat, tetap terdepan dalam sastra di Lampung. Sementara Amzuch yang kini nampak seperti “pemencet pasta gigi kosong”—saya meminjam pendapat Amzuch, cukuplah menikmati hari-hari bersejarah sebagai pembuka jalan bagi sastra di Lampung menuju Indonesia. Sedangkan cerpenis M. Arman AZ—rasanya satu-satunya cerpenis Lampung yang setia dengan dunia prosa—perlu menajamkan kreativitasnya mencapai media bergengsi semacam Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara Merdeka.
Itu semua kendala, namun juga tantangan yang harus dilampaui oleh para sastrawan. Sebab pertaruhan paling hakiki di dalam dunia sastra adalah karya itu sendiri. Bukan wilayah geografis antara pusat dan daerah, nasional atau lokal, Jakarta dan seberang, dan seterusnya. Apatah lagi masuknya isu soal pengkotakan alias kubu: kubu TUK, Horison, DKJ, KSI, Rumah Dunia, sampai Boemi Poetra dan Memo Indonesia.
Sebagai kreator mestinya abaikan persoalan yang menggganggu kreativitas tersebut, apalagi sampai “selalu menuding” ketidak becusan redatur dan kanon sastra semacam itu karena menganggap hanya nama-nama tertentu dan itu-itu saja, sehingga melampiaskan kekecewaannya dengan menyatakan tak pernah mengirim karya ke media massa mana pun lagi. Atau memutuskan diam dan menunggu sambil terus berkarya dan menyimpannya.
Saya tidak mengerti apakah ini masuk wilayah kreativitas (penciptaan) ataukah wilayah propaganda marketing yang sejatinya mereka berharap juga diperhatikan. Propaganda yang hampir sejenis ini—kalau boleh dibilang propaganda—sebenarnya pernah dilakukan kelompok Revitalisasi Sastra Pedalaman (RSP) yang dimainkan Kusprihyanto Namma, Beno Siang Pamungkas, Widjang Wareh, dll. yang menyatakan penolakan terhadap pusat (dalam hal ini Jakarta). Mereka menolak TIM/DKJ dan seluruh media massa terbitan Jakarta, dengan membuat tandingan melakukan pertemuan sastra di Jatim dan Jateng serta membuat buletin untuk menampung karya kreatif ataupun campakan ludah tertuju Jakarta (baca: kanon sastra). Akan tetapi, ketika karya dari penggagas RSP muncul di media Jakarta dan selanjutnya diundang DKJ tampil di TIM, luntur seluruh cacimaki pada Jakarta.
Sikap seperti ini bukan tak ada pada sastrawan Lampung. Kekecewaan yang semula karena tak dimuatnya karya-karyanya di media Jakarta, lalu membikin gerakan menyurut ke belakang atau bersembunyi di balik “moralitas” sastra. Misalnya membentuk kelompok kecil, sekolah kecil-kecilan yang juga untuk kelompoknya, atau sama sekali ambil jarak dengan dunia sastra yang sayangnya tak pernah (mau) menyatakan “selamat tinggal dunia sastra” karena menganggap sastrawan adalah “profesi sampai mati”.
Ketika gugatan terhadap KUK/TUK yang dinilai sebagai “penentu” percaturan sastra di Indonesia, Lampung juga memeroleh imbas “cacimaki” dari kelompok penggugat TUK. Imbas itu terasa, misalnya, menyebut sastrawan Lampung sebagai TUKisme dan “dibesarkan” oleh TUK karena kerap karyanya dimunculkan di Kompas (redakturnya Hasif Amini dari TUK) dan Koran Tempo (Nirwan Dewanto yang juga orang TUK), sambil mengabaikan bahwa karya-karya sastrawan Lampung juga dimuat Media Indonesia, Republika, Horison, Jawa Pos, Suara Merdeka, Suara Pembaruan, Suara Karya yang notabene tak tersangkutpaut dalam “gurita” TUK—jika dianggap TUK bergurita
Isu kubu-kubu yang terjadi di Jakarta memang telah meracuni sebagian sastrawan beli di beberapa daerah. Ada semacam kebimbangan untuk menentukan media bagi sosialisasi karya-karyanya. Ada pula yang sekadar ingin tahu kebenaran ihwal kubu-kubu itu. Tetapi, tak sedikit ada pula yang merasa takut karena dihantui bahwa rimba sastra begitu pekat dan menakutkan!
Ujaran ataupun hujatan seperti itu anggap saja bagian dari dinamika kehidupan. Tak perlu dihirau atau dirisaukan, apatah sampai mematikan kreativitas maupun mundur dari gelanggang. Pendekar sejati mesti berani masuk ke gelanggang dan mempertaruhkan seluruh kemampuannya. Kalau tidak, ya menarik diri dari garis pertarungan secara legawa tanpa meninggalkan sumpahseranah.
Demikian konstelasi sastra Lampung, dari Amzuch ke Fitri Yani. Dari uraian serbaringkas dan cenderung menatah sejarah kesastrawanan di Lampung, kita bisa menyerpihi satu persatu para sastrawan. Kemudian menunjuk mana sastrawan yang tetap berkarya di tengah persaingan “merebut hati” redaktur (media masa) nasional maupun lokal dan dinamika seakan setiap hari lahir sastrawan di Tanah Air.
Berapa banyak sastrawan Lampung—baik dari generasi awal sampai teranyar—yang masih setia menekuni dunia kesunyian ini? Memang, agaknya, dunia sastra di Indonesia belum menjanjikan apatah lagi berpeluang menunjang strata sosial si sastrawan. Itu sebabnya, wajar kalau terjadi pasang-surut-pasang bagi dunia sastra. Seperti pula penerbitan buku-buku sastra yang kadang booming dan lain hari para penerbit enggan menerbitkan buku sastra lantaran takut rugi.
Ada yang menarik dari dinamika sastra di Lampung, yakni ketika munculnya (latah?) keinginan beberapa sastrawannya kembali ke lokalitas keLampungan. Sayangnya lokalitas (localgenius) itu cuma terkesan lipstick—hanya tempelan dan pemanis—karena tidak menukik ke kedalaman. Yang hadir di dalam karya-karya para sastrawan Lampung cuma kosakata semisal “adin, atu, kiyai” ataupun nama-nama tempat/singgahan. Padahal, lokalitas bukan sebatas penamaan dan penandaan, tapi bagaimana usaha sastrawan menafsir ulang ihwal kelokalitasan yang ada dan berlangsung di suatu tempat ia berpijak. Sebagaimana dilakukan Azgari (Aceh) melalui cerpen-cerpennya yang kemudian terhimpun dalam bukunya Perempuan Pala, Sutardji Calzoum Bachri yang “memperbarui” mantra di dalam puisi-puisinya, sampai kepada Taufik Ikram Jamil, Fakhrunnas MA Jabbar, Marhalim Zaini (Riau), serta Gus tf (Sumatera Barat).
Akhirnya untuk menutup uraian ini, sambil lalu saya ingin menggubris peran media di Lampung. Terus terang hanya Lampung Post yang masih mempertahankan ruang bagi karya sastra dengan honor cukup berarti, yang lain: Radar Lampung, Lampung Ekspres Plus, serta media-media yang lain seakan “menutup” ruang-ruangnya. Saya kurang dapat memahami, kendala apa bagi media-media lokal tersebut sehingga tak berperhatian pada karya-karya sastra.
Dan, bagi Lampung Post sendiri tentu saja mesti harus terus berbenah: membenahi bagi penjaga gawang halaman sastra. Tugas sebagai redaktur sastra, sebenarnya tak segampang menggawangi halaman-halaman lainnya. Haruslah dipilih orang yang setia, memunyai apresiasi yang baik terhadap sastra, dan jeli melihat karya yang baik walaupun datang dari penulis pemula, serta netral. Saya yakin ini bisa dilakukan Lampung Post. Siapa takut?
Bandarlampung, 4-8 Desember 2007
*) mengutip judul
Dari Fansuri ke Handayani, terbitan
Horison-Ford Foundation
-----------------
karena tulisan ini sbagai kertas kerja pada pertemuan sastra se-Sumatera di Medan--yang telah dimuat
Lampung Post edisi khusus Akhir Tahun (2007)--, telah mendapat tanggapan melalui SMS dengan nomor kontak 0815409660209, isinya:
"
malam bang is, selamat idul adha. malam ini saya baca blok abang. ada esai berjudul 'kontemplasi (seharusnya konstelasi, isb)
sastrawan lampung. mulai motinggo busye sampai fitri disebut. namun tak sepotong nama pun nama saya di situ. saya dianggap tak pernah ada.
tak apalah. bagi saya isbedy juga bukan apa-apa. puisinya tipis cerpennya dangkal. tapi pede banget nerbitin buku. entah siapa yang beli!! suka dipuji juga suka berkonprontasi.
budi dan edi ia benci. terutama karena budi penyair yang menulis puisi paling kuat di lampung selain iswadi. oke deh, saya akan junjung nilai perkenalan kita selama ini. semoga anda sukses dan terus menerbitkan buku-buku. siapa tahu dapat khatulistiwa. salam hangat!!
un
tuk pesan tak bernama itu, saya balas
:
"maaf, saya tak bermaksud meniadakan nama seseorang. tapi karena terlupa saja sebab banyak nama yang mesti diingat. soal puisi atau cerpen saya tipis dan dangkal, pembaca yang menilai."