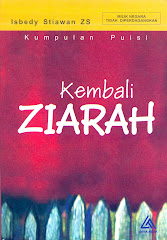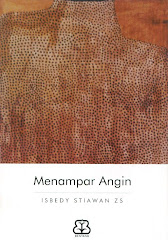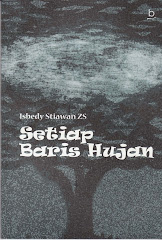Seandainya Komisioner KPU Dibekukan?
Oleh Isbedy Stiawan ZS
Komisioner KPU Kota Bandar Lampung didesak organisasi massa (LSM) agar segera segara dibekukan. Desakan menonaktifkan itu disebabkan kelebihan pencetakan surat suara hingga 116.583 lembar bagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung Juni depan.
Desakan beberapa lembaga ormas itu, boleh jadi, akumulasi dari berbagai pelanggaran yang selama ini dianggap telah dilakukan pengurus KPU, terkait penyelenggaraan Pilkada Kota Bandar Lampung 2010. Bahkan ada tengarai komisioner tidak netral lagi, cenderung berpihak kepada satu kontestan.
Oleh karena itu, desakan komisioner KPU Kota Bandar Lampung dibekukan seperti jadi alternatif. Setelah dinonaktifkan, ‘kekuasaan’ KPU kota itu diambilalih oleh KPU Provinsi Lampung, tentu dengan pengawalan dari lembaga indevendent. Tawaran yang sebut terakhir ini, dari pernyataan seorang teman melalui jejaring sosial dunia maya (facebook). Meski hal itu sangat tidak mungkin, mengingat perhelatan Pilkada 2010 tinggal hitungan hari. Selain itu pula, akan menambah anggaran yang dikelujarkan untuk membayar ‘lembaga baru’ tersebut.
Sulit memang siapa yang benar dan siapa pula yang telah melakukan kecurangan, terkait pencetakan suarat suara yang berlebih itu. Pasalnya, pihak komisioner KPU mengakui bukan disengara. Sementara pihak kontestan, berasumsi ada kesengajaan yang dilakukan KPU untuk memenangkan salah satu kandidat.
Dalam peta politik, memang seakan ‘dihalalkan’ untuk menuding ataupun berkelit. Bahkan, jelas-jelas telah melakukan kesalahan pun menganggap bahwa pihaknya benar. Pernyataan dalam dunia politik menjadi abu-abu. Klaim-klaim bahwa satu pihak paling benar ataupun paling peduli bagi kesejahteraan rakyat, dianggap hal biasa untuk menarik simpati masyarakat. Jargon dan kebohongan sudah sulit ditemukan pembedaannya.
Media masssa telah dijadikan arena yang tepat untuk menampung jargon-jargon politik. Pihak KPU, kontestan, dan lembaga ormas (dan LSM) berlomba untuk saling melempar klaim tentang kebenaran itu. Masyarakat dipaksa untuk meyakini bahwa para pemain di panggung politik itu adalah benar, kebenaran, dan satu-satunya yang berhak memegang jargon tersebut.
Alangkah malangnya dunia politik kita. Setiap politisi berhak mengumbar janji, dan media menampungnya untuk dilemparkan ke publik. Sementara masyarakat terpaksa dijejali dengan berbagai pernyataan, yang cenderung sampah itu. Begitu pula, KPU bersikap layaknya ‘malaikat’ yang bisa semena-mena menentukan (menetapkan) sesuatu atau perhelatan pilkada. Komisioner KPU menjadi ‘kebal hukum’ bahkan tatkala dia dianggap melakukan kesalahan. Contoh ihwal ini sudah cukup banyak. Kegagalan KPU menggelar pemilu dan pilkada, hampir kebanyakan tidak sampai ke penjara. Para pengurus KPU boleh untuk tak menjawab—dengan mematikan alat kontaknya—setiap pihak meminta pertanggungjawaban. Setelah dinilai aman, mereka kembali ke publik dengan persoalan selesai begitu saja.
Kalau kebiasaan-kebiasaan serupa ini, terus dipelihara akan ke mana arah akhir politik di tanah air? Masyarakat menjadi semakin tidak peduli dengan hasil pemilu/pilkada. Siapa pun yang duduk di legislatif maupun yang menjadi kepala daerah, tidak akan memengaruhi tingkat sosial massa. Kecuali orang-orang yang dekat dan bersentuhan secara akrab dengan mereka. Alangkah malangnya hasil dari arena politik di tanah air ini?
Tampaknya sistem perpolitikan di sini yang mesti dibenahi., dan bukan soal lembaganya. Apa pun lembaganya—legislatif maupun KPU—kalau sistemnya memang mudah dicurangi, akan dilakukan juga. Betapapun individu komisioner KPU awalnya dinilai baik dan bersih, begitu memasuki sistem yang karutmarut dan terbuka dicurangi itu maka akan larut pula.
Saya amat menyayangkan, orang-orang baik dan jujur namun karena memasuki sistem politik yang masih karutmarut itu akhirnya luntur. Bahkan, kalaupun masih konsisten tetap saja dicurigai keindependenannya. Seperti buah simalakama.
Menjaga eksistensi
Memasuki bulan terakhir akan dihelatnya Pilkada Kota Bandar Lampung, elok sekali kalau semua pihak sama-sama menjaga eksistensi pesata demokrasi ini. Pihak-pihak—seperti KPU, partai, ormas dan LSM, kandidat, media massa, serta publik—bertanggungjawab bagi lancarnya keberlangsungan pilkada. Menahan diri dari berbagai emosi dan kepentingan pribadi, snagatlah diharapkan.
Terutama pihak KPU yang bagaimanapun sebagai ‘kekuasan tertinggi’ bagi hitam-putihnya pilkada/pemilu, dituntut sebenar-benarnya netral. Tanamkan dalam iktikad, bahwa siapapun pilihan masyarakat itulah yang di kedepankan. KPU hanya menghitung atau mencatat perolehan suara bagi kontentan, tanpa dicampuri oleh kepeningan demi keuntungan pribadi lalu mencurangi hitungan suara.
Lalu para kandidat, masukilah arena pilkada dengan sikap menerima kemenangan atau kekalahan. Jangan menjadikan kekalahan sebagai senjata untuk menggagalkan hasil pemeilihan suara dari masyarakat. Betapa pun, ‘suara rakyat’ pada saat ini sulit disebandingkan dengan ‘suara Tuhan” sebab sudah bisa dibeli. Apabila kecuarangan tidak siginifikan, dapatlah diterima dengan lapang dada.
Dalam perpolitikan, seperti juga di meja perjudian, kekalahan dan kemenangan adalah hal biasa dan sesaat. Karena yang lebih besar, ialah bagaimana membangun darerah ini agar lebih maju dan bisa mensejahterahkan masyarakat. Saya masih optimistis, iktikad kandidat Wali kota/Wakil Wali kota Bandar Lampung semata untuk memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan. Bukan untuk satu-satunya kemenangan, demi kekuasaan.
Sementara ormas atau LSM yang seakan dinisbahkan punya hak turun ke jalan, setidaknya sebelum berdomentrasi dipikir secara matang: apakah yang diperjuangkan itu akan bermanfaat bagi banyak masyarakat? Atau hanya segelintir dari pihak-pihak tertentu yang akan mencecapnya. Di sini, bukan maksud saya, hendak mencurigai integritas dan independensi semua ormas dan LSM yang kerap turun ke jalan. Tetapi kembali mengingatkan saja, ada banyak pihak yang kadang ikut bermain untuk mneikmati hasil perjuangan dan pengorbanan eleman masyarakat yang kritis itu. Jangan sampai elemen masyarakat yang seyogyanya perjuangan demi rakyat kecil, namun yang memetik keuntungannya adalah elit-elit politik.
Dan, kita masyarakat biasa, yang hanya membaca dan menyaksikan gonjang-ganjing perpolitikan—terutama jelang Pilkada Kota Bandar Lampung—tidak harus semakin ora mudeng karena polah para pemain politik tersebut. Masyarakat yang berada di luar garis lapangan, tak mesti terseret sebagai korban. Jangan sampai dunia sepakbola dimana penonton terlalu kerap jadi korban, berimbas memasuki arena pilkada. Jangan. Jangan... *