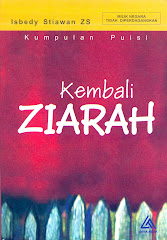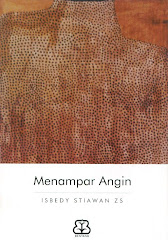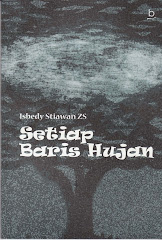15 November 2008
Catatan buat Festival Krakatau XVIII:
Oleh Isbedy Stiawan ZS
SABTU 23 Agustus 2008, Festival Krakatau (FK) dibuka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, FK akan berlangsung selama sepekan. Dan tahun 2008 ini digelar hingga Minggu (31/8) depan.
Meskipun rencananya pembukaan FK XVIII akan dihadiri para duta besar asing, hajat senibudaya Lampung dalam rangka menarik minat wisatawan mengunjungi objek-objek wisata di daerah ini, tetap menyimpan pesimistis. Akankah FK yang telah berlangsung 18 tahun ini mampu “menyihir” wisatawan asing berkunjung ke Sang Bumi Ruwa Jurai?
Menilik jadwal acara FK XVIII, tampaknya cuma mengulang tahun-tahun sebelumnya: seremoni yang seakan “wajib” sambil “mendatangkan” para duta besar asing, gelar seni budaya, midnight krakatau, tur ke krakatau, festival layang, dan seterusnya.
Sementara, ini yang sering saya pertanyakan, objek-objek wisata yang tersebar di daerah ini tetap tak terkunjungi. Padaha, FK ini dihajatkan sejatinya untuk menarik minat wisman berkunjung sehingga mampu menghidupkan objek-objek wisata. Para duta besar hanya untuk menyaksikan seremoni pembukaan FK, lalu—barangkali—mereka kembali ke Jakarta usai kegiatan seremoni tersebut. Sedangkan tamu asing yang notabene wisatawan hanya berapa orang, itu pun tidak menetap beberapa hari di sini.
FK XVIII ini sekaitan memromosikan Visit Lampung Year 2009, hanya semangat untuk menyukseskannya tidak—atau belum—tercium. Asumsi saya ini bisa dibuktikan melalui polling ke masyarakat Lampung: tahukah dengan FK XVIII, sejauh mana pengetahuan warga terhadap Visit Lampung Year 2009, adakah keterlibatan masyarakat bagi hajat FK?
Apabila FK yang saat ini masuki tahun 18 diklaim sukses oleh pemda, kita bisa buktikan dengan jumlah hunian hotel-hotel di Bandar Lampung. Misalnya berapa persen kenaikan jumlah hunian hotel dari wisatawan (lokal dan internasional) karena ingin menyaksikan FK dan mengunjungi objek-objek wisata? Betapa pun spanduk dalam berbagai ukuran sudah terpajang di sejumlah hotel, bahkan mungkin brosur ihwal FK juga disediakan di setiap resepsionis dan loby hotel.
Meskipun tulisan ini tanpa survei, saya pesimistis kalau masyarakat Lampung tahu persis tentang FK, Visit Lampung Year 2009, merasa terlibat; atau hunian hotel-hotel tidak akan naik persentasenya secara signifikan. Beberapa hari lalum di bulan Agustus ini, saya menyempatkan mengobrol dengan salah seorang petugas resepsionis hotel, ihwal dampak penyelenggaraan FK. Dengan sangat hati-hati, ia mengaku, kalau FK memilik dampak bagi kunjungan wisatawan otomatis hunian kamar hotel akan bertambah. “Nyatanya sampai hari ini belum ada tamu luar kota (Lampung) yang memesan kamar?” ia balik tanya.
Ini hanya satu contoh, walau belum dapat dianggap akurat, tapi setidaknya sebagai gambaran bahwa FK masih belum menarik minat para wisatawan berkunjung ke Lampung. Lalu, apakah gaung FK tidak dikenal oleh masyarakat di luar Lampung (luar negeri)? Saya tetap yakin bahwa FK telah diketahui oleh masyarakat di luar Lampung.
Sebagai contoh, pada Kamis (21/8) saya mendapat pesan singkat (short masage system) dari seorang teman, Suryadi. Pengajar di Universitas Leiden itu mengetahui nomor kontak saya dari jurnalis Kompas Yurnaldi yang sama-sama berada di Kualalumpur. Dalam pesan pendeknya yang saya terima, ia menanyakan jadwal FK 2008. Dengan semangat mempromosi saya balas bahwa FK akan digelar 23 s.d. 31 Agustus 2008, ditambah acara-acara pendukung: Lampung Expo dan Panggung Apresiasi Senibudaya di Graha Wangsa, 26-31 Agustus 2008. Pada akhir SMS saya itu, harapan saya agar ia mau berkunjung. Sayang rekan Suryadi—sungguh sampai kini saya belum kenal wajahnya, kecuali ia mengatakan tulisannya kerap dipublikasikan Kompas—sedang siap bertolak ke Amsterdam.
Kekecewaan saya tak mampu “menyihir” seorang Suryadi bertandang ke Lampung di saat FK XVIII ini sedikit terobati, manakala ia mengatakan kalau saat ini tengah melakukan penelitian terhadap Syair Karam—sebuah karya sastra berusia berabad-abad yang ditulis oleh pribumi (putra daerah) Lampung bernama Muhammad Saleh—yang merekam bencana Krakatau pada 1883. “Teks syair tersebut tersimpan di Kualulumpur, Leiden, Cambridge, Frankfurt, dan Moscow,” katanya.
Masih kata ahli filologi yang juga pernah meneliti adanya Dinasti Kerjaan Gowa di Sulsel yang tak tersentuh sejarah Indonesia itu, Syair Karam itu ditulis dalam bahasa Arab-Melayu. Ia berniat akan menerbitkan transliterasi Latin teks syair tersebut disertai pengantar teks.
Informasi mengenai Syair Karam membikin hati saya berbunga sehingga melenyapkan kekecewaan saya tentang halangannya untuk hadir pada FK ini. Selain itu, keingintahuannya jadwal FK sudah membuktikan sekiranya kegiatan pendukung dikemas lebih baik dan promosi makin ditingkatkan, tak perlu lagi pesimis FK tidak dikunjungi wisawatan (lokal dan mancanegara).
Hanya pada kesempatan ini, pesimistis itu masih bersemayam. Pasalnya, dari agenda yang disodorkan FK XVIII masih itu-itu saja. Pengemasannya pun tidak ada yang mampu membuat orang tersihir. Begitu pula promosi yang jauh dari “menghebohkan”, membikin hajatan FK seakan tak memiliki magnit.
Sesungguhnya dalam dunia pariwisata, diperlukan penghebohan. Dengan “siasat menghebohkan” tersebut, wisatawan akan tertarik. Kalau sudah tertarik, ia akan berminat. Setelah timbul niat, ia berupaya untuk dapat bertandang.
Terlepas tetap mengutuk dan tak sulit dilupakan tentang kekejian pengebom Bali, namun tak bisa dipungkiri bahwa “tragedi bom Bali” itu melecut keinginan wisatawan luar negeri berkunjung ke Pulau Dewata apapun motivasinya. Buktinya, Bali tetap menjadi nomor wahid di pertiwi ini dalam soal kepariwisataan.
Persoalannya pada FK dan juga institusi terkait pada kesuksesan pariwisata di Lampung, sepertinya tak pernah berpikir melakukan “penghebohan” selain hanya mengikuti desain yang sudah ada dari tahun ke tahun. Akibatnya, berkali-kali FK—tahun ini ke 18—dihelat, kunjungan wisatawan ke Lampung tidak meningkat-ningkat. Sejumlah objek wisawa yang ada, semisal Kalianda Resort, Pantai Marina, Pusat Latihan Gajah di Waykambas, Taman Wisata Bumi Kedatun Batuputu, Danau Ranau di Lampung Barat, pesisir pantai Krui, dan berbagai objek wisata lainnya, bagai kedinginan tanpa pengunjung.
Itu sebabnya, saya tak punya cara lain kecuali mengkritisi FK sebagai hajat yang hanya menjalankan agenda tahunan yang dananya dikucurkan APBD. Hal ini sudah pula saya utarakan manakala jurnalis Kompas berkesempatan mewawancarai saya beberapa hari lalu. Saya masih belum punya bahasa lain, kecuali hajat Pemda Provinsi Lampung di ranah pariwisata ini masih dalam tataran permukaan.
Analoginya bahwa pemda telah menciptakan pasar yakni Festival Krakatau, tetapi yang akan dijual belum tahu (dan tak ada) barangnya. Kalianda Resort dan Pantai Marina (Lamsel) belum mampu kita banggakan, karena kalah jauh menarik dengan Pantai Kuta dan Sanur (Bali), Taman Kedatun Batuputu belum dapat diandalkan, sebab ia kalah hebatnya dengan Sangeh (Bali) atau yang lainnya, PLG Waykambas (Lamtim) makin sepi dikunjungi sebab selain jauh dari pusat kota maka kawasan itu juga (konon) tidak terurus dengan baik. Apatah lagi kalau kita ingin mengandalkan pantai yang menyisir teluk Lampung akan kalah jual dengan pantai yang ada di Bali, Lombok, Bengkulu, Sumbar, Sulsel, dan daerah-daerah tujuan wisata (DTW) lain di Tanah Air.
Lantas, apa lagikah eksotisme Lampung yang akan kita jual di hadapan para wisatawan? Untuk itu, perlu didiskusikan—diseminarkan, didialogkan dan kalau mungkin diperdebatkan—dengan mengundang para pakar dan ahli berbagai bidang ilmu kemudian merumuskan “kue” apa yang hendak dihidang di pasar pariwisata? Akankah kita lakukan seperti apa adanya dan yang sudah berlangsung selama ini, yang cenderung monoton dan tidak punya daya tarik itu?
Mestinya Pemprov Lampung belajar banyak dari perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB), Festival Kesenian Yogya (FKY), Festival Danau Toba, dan banyak lagi festival ataupun pesta kesenian yang muaranya untuk mendongkrak dunia pariwisata. Bagaimana PKB mampu menghadirkan tidak saja Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melainkan presiden. Namun kemampuan menghadirkan menteri dan presiden memang belum cukup untuk mengatakan perhelatan tersebut berhasil, sejatinya PKB, FKY, atau Festival Danau Toba terbukti sukses baik acara maupun wisatawannya yang mau bertandang.
Eksotisisme
Menyadari wisatawan asing—terutama berkulit bule—sangat berminat hal-hal eksotis (exotic), kenapa penyelenggara FK tidak berpikir menggali eksotisisme ke-Lampung-an. Dan Lampung, jangan khawatir, akan kehabisan nilai-nilai eksotis itu. Dengan alam berbukitan (pegunungan), belantara nan hijau, beberapa hewan yang dianggap langka di dunia masih berkeliaran di Lampung, ditambah pula kekayaan senibudaya yang masih mencirikan kekhasan seperti dadi, muayak, wawancan dan lain-lain; sungguh bisa jadi andalan untuk menyelematkan kepariwisataan di sini.
Contoh yang tak bisa diabaikan, penemuan ahli filologi dari Universitas Leiden itu tentang Syair Karam ternyata ditulis oleh pribumi (putra daerah) Muhammad Saleh. Mengapa kita tidak berminat menjemput Suryadi ke Lampung untuk mempresentasikan “penemuan” Sayir Karam Muhammad Saleh, sebab syair tersebut jelas merupakan aset dan kekayaan khasanah sastra Lampung. Sementara soal “adanya” makam Patih Gajah Mada di Pugungtampak (Lambar), pemda tak sungkan mengucurkan dana dari APBD hanya untuk mendapatkan kebenarannya.
Bukan slogan lagi—walau dianggap penting—yang digelontorkan berton-ton bagi suksesnya FK, melainkan objek apa yang akan diperdagangkan di pasar pariwisata. Ibarat berdagang, produk apa yang dijual. Setelah ada produk, bagaimana mengemasnya akan menarik minat pembeli. Untuk “menyihir” pembeli, produk yang dijaja bukan sembarang atau barangnya bisa didapat di tempat (pasar) lain. Belajarlah pada Jepang, meski yang dijaja hanya sepeda motor—misalnya Honda—akan tetapi setiap tahunnya dilounching kemasan baru dan menarik. Begitu pula pasar pariwisata.
Jika tidak pernah mau berpikir baru lalu mengandalkan yang sudah ditampilkan tahun-tahun sebelumnya, alamat “rumah keduamu” (your scond home) akan tetap tak disinggahi. Kalau Lampung tak ada lagi yang (bisa) menarik, wisatawan lebih baik memilih Yogya, Bandung, atau sekalian ke Bali, Lombok, Sumut, Sumbar, bahkan Sumsel. Bukankah dana transportasi yang mesti dikeluarkan hampir sama besarnya ke Bali atau ke daerah lain? Sebab biarpun Lampung sangat dekat dengan Jakarta, namun tiket pesawat tak jauh berbeda apabila memilih tujuan ke daerah lain. Sedangkan bila menggunakan transportasi laut dan darat, waktu 6 jam atau lebih bagi wisawatan asing sangatlah menyita dus tidak efektif.
Akhirnya, memang tak ada gading yang tak retak, cuma soalnya (dapat pula dibaca: sialnya) gelaran FK selalu dari tahun ke tahun melulu retak di gading yang sudah retak itu. Mau apa lagi dan apa mau dikata? FK tak mungkin ditiadakan, Visit Lampung Year 2009 telah dicanangkan….
Dimuat Radar Lampung, Senin, 25 Agustus 2008
(Kebudayaan) Lampung di Mata Pendatang
Oleh Isbedy Stiawan ZS
SEBENARNYA kekhawatiran seperti ini sehingga berulang dilaksanakan seminar sudah lama muncul. Dalam berbagai diskusi tentang kebudayan Lampung yang seakan tidak menjadi tuan di rumah sendiri sering dilontarkan. Tetapi selalu saja, (kebudayaan) Lampung tetap “tersisih” dan seperti (di)marginal(kan) di antara kebudayaan-kebudayaan lain di daerah ini: Minang, Batak, Bali, Banten, dan belakangan marak dari komunitas Tionghoa (Cina).
Kalau ada kebudayaan yang kurang menonjol—bahkan nyaris tenggelam oleh kebudayaan yang datang—di rumahnya sendiri, mungkin adalah (hanya) Lampung. Orang Betawi yang ditengarai hanya menempati pinggiran Jakarta, namun laku dan bahasa Betawi tetap hidup bahkan mewarnai penduduk Jakarta. Terlebih pendatang, merasa belum menginjak Jakarta dan menetap, jika tidak berlaku dan berbahasa Betawi. Bahasa (logat) dan laku Betawi yang terbuka merembes hampir ke daerah-daerah di Tanah Air.
Anehnya, bahasa (dielek) dan laku dari kebudayaan Lampung justru hanya berlangsung di komunitas orang Lampung. Karena itu pula, tamu yang berkunjung ke Lampung seperti kehilangan untuk menandai kebudayaan Lampung. Sebaliknya yang dijumpai ialah kebudayaan di luar etnis Lampung.
Sejak Bakauheni pendatang tidak disuguhi kekhasan nuansa kebudayaan Lampung. Di Terminal Rajabasa, kecuali kecemasan, tak ada penanda bahwa pendatang sudah tiba di sini. Bahkan di pasar-pasar—terutama Bambukuning—yang sampai di telinga adalah dialek dan kekhasan orang Minang, begitu pula di stasiun kereta api. Belum lagi apabila pendatang menginap di hotel-hotel yang tersebar di Bandar Lampung, betapa tak dijumpai penanda bahwa ia sedang berada di Bumi Ruwa Jurai.
Dari fenomena di atas, wajar jika warga Lampung beretnis Lampung menjadi cemas. Mungkin tak lama lagi, seperti diasumsikan para pakar, bahasa Lampung akan punah karena ditinggalkan penggunanya. Sebenarnya, catatan para pengamat bahasa daerah pada Seminar Bahasa-Bahasa Daerah di Hotel Marcopolo tahun lalu, ada banyak bahasa daerah dikhawatirkan tidak (lagi) digunakan sehingga hilang.
Ini dari soal bahasa. Lampung yang punya 2 dialek bahasa yang sangat berbeda dan sulit dicari persamaan, tampaknya cuma dipakai oleh komunitas masing-masing. Dialek nyow dipakai komunitas pepadun dan api hidup di masyarakat saibatin sulit diapresiasi masyarakat di luar Lampung, meskipun lahir dan besar di Bumi Ruwa Jurai. Jika hal ini kita tanyakan kepada masyarakat etnis Lampung, jawaban yang didapat karena “keterbukaan” orang Lampung kepada pendatang (tamu). Persoalan yang sama berbeda pada daerah-daerah lain, semisal Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa, Bali, maupun Makasar serta Papua.
Muatan lokal sudah dilaksanakan di sekolah, dari jenjang SD hingga SMA, tapi kenyataan di masyarakat berapa banyak yang mampu menggunakan bahasa Lampung secara mahir—baik berdialek api maupun nyow. Generasi muda, terutama remaja, dalam percakapan sehari-hari lebih suka dan merasa bangga memakai bahasa gaul (Jakarta/Betawi?) dan atau dialek yang “diviruskan” buku-buku teenlit dan chicklit ketimbang bahasa Lampung.
Muatan lokal di sekolah-sekolah sebenarnya bisa dijadikan basis pengembangan dan pemanfaatan bahasa Lampung secara luas. Sayangnya, belum adanya kesepakatan tentang dialek yang akan dipakai. Apakah dialek nyow ataukah api. Bayangkan jika anak-anak SD, kelas 1, harus “dipaksa” memahami dua dielak pada saat bersamaan.
Kurikulum di sekolah juga mengajarkan bagaimana anak didik hanya bisa menulis ke dalam bahasa Lampung. Dan, bukan menulis percakapan dengan bahasa Lampung dalam bahasa dan aksara Lampung. Sehingga anak didik tidak mahir bercakap-cakap dalam bahasa Lampung. Aksara Lampung, sejatinya dibanggakan karena hanya sedikit aksara dimiliki di Indonesia, hanya dikenalkan dan bukan dipakai.
Entah disebabkan etnis Lampung yang minoritas membuat penggunaan bahasa sulit disosialisasikan atau karena “keterbukaan” masyarakat etnis Lampung yang pada tataran tertentu kerap berbahasa Indonesia jika berkomunikasi dengan masyarakat nonetnis Lampung. Selain itu kurangnya kesadaran dari masyarakat Lampung—beretnis Lampung dan etnis lain—menjadikan bahasa Lampung sebagai bahasa komunikasi. Asumsi lain, bahwa Lampung mempunyai 2 dialek bahasa yang amat berbeda membuat keduanya sulit bertransformasi secara luas.
Saya tidak sepakat kalau Lampung sebagai Indonesia mini hanya disebabkan beragam etnis ada di daerah ini. Saya juga menolak jika Lampung sebagai bagian barat dari Jakarta, sebab di sini tumplek berbagai suku dari banyak etnis. Cara pandang seperti itu menunjukkan pesimistis yang membuat kita enggan melakukan perubahan.
Kita maklumi kebudayaan adalah penanda, karena itu harus ada kesadaran untuk menjaga supaya penanda itu tidak lenyap. Apakah masih disebut Lampung jika aksara (dan bahasa), adat, dan budaya tidak lagi dikenali? Tantangan ke depan, saat ini saja ketika arus globalisasi sudah memasuki hingga ke ruang-ruang paling privasi, arus budaya asing dan budaya-budaya dari etnis nonLampung semakin mewarnai, maka yang harus dilakukan ialah merumuskan strategi pelestarian seluruh aset kebudayaan Lampung. Adapun maksud strategi pelestarian, menurut Dr. Khaidarmansyah, pelestarian ialah perlindungan (melindungan), pengembangan (mengembangkan), dan pemanfaatan (memanfaatkan). Sehingga pelestarian kebudayaan berarti (1) mempertahankan bentuk-bentuk lama yang sudah pernah ada, (2) menjadikan kebudayaan yang bersangkutan tetap ada dan tetap hidup dengan peluang perubahannya sesuai dengan perkembangan zaman.
Sejatinya masyarakat Lampung—terutama etnis Lampung—menyadari segera sebelum benar-benar punah seperti yang diperkirakan para pakar tentang kekayaan budaya yang dimiliki Lampung. Banyak yang bisa digali dan dilestarikan, misalnya dadi (sastra tutur) untuk sekadar menyebut yang kini hanya seorang Masnuna yang nyatanya sudah pula uzur kalau tidak ada dan menyiapkan penerus penuturnya, akan punah pula. Sayangnya Masnuna sudah tidak bisa bepergian jauh untuk “ditanggapi”, sedangkan penerusnya belum lagi lahir dan semahir Masnuna.
Masnuna jelas punya “nilai jual” dan dadinya mampu memikat orang di luar etnis Lampung. Meskipun boleh jadi mereka tidak bisa mengerti dan memahami syair-syair dalam bahasa Lampung sangat puitik dan bernilai sastra tinggi. Tetapi, menyedihkan (kalau) ternyata ada (lembaga) yang hendak “menjual” dan mengeruk keuntungan dari Masnuna. Sebab, sampai kini—semoga masih hidup—Masnuna hidup dalam kemelaratan di pedalaman Lampung Tengah.
Tetapi kita kerap lalai. Kita latah pada pemerintah yang tidak menempatkan kebudayaan sebagai bagian integritas pembangunan, bersanding dengan program-program pembangunan yang ada. Masalah kebudayaan, sejak pemerintah Orde Lama yang dilakukan setengah-setengah, sampai puncaknya pada rezim Soeharto dengan politik “penyeragaman”nya. Tetapi yang ditonjolkan adalah (kebudayaan) Jawa sehingga jawanisasi makin kental. Akibatnya menenggelamkan keberagaman etnis dan budaya hanya oleh “persatuan dan kesatuan” yang telah menjadi jargon berpuluh tahun, paling parah dirasakan budaya-budaya dari etnis minoritas.
Dengan pemahaman seperti itu, kebudayaan akan mudah digerakkan dan dibentuk yang datang dari (pemerintah) pusat. Segala bentuk kebudayaan, seakan tergantung “paket” dari pusat. Jangan heran ketika Depdiknas memangkas Direktorat Kesenian kemudian dimarger ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, daerah (Pemprov Lampung) latah menghapus Subdin Kebudayaan dari Dinas Pendidikan. Sasaran pengajaran kebudayaan di jenjang SMA menjadi terputus. Bisa dibayangkan 5 atau 10 tahun mendatang, anak-anak didik jenjang SMA yang dianggap potensial untuk dibentuk menjadi manusia berbudaya akan makin asing dan tak mengenal sama sekali kebudayaan sendiri.
Sayangnya, baik kalangan budayawan, seniman, dan masyarajakat adat di Lampung, seperti tidak keberatan dihilangkannya Subdin Kebudayaan dari tubuh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Padahal, saya bisa pastikan, kebijakan Pemrov Lampung tidak dirahasiakan. Menyadari sifat kebudayaan tidak diwariskan secara genetika melainkan melalui proses belajar, baik secara formal maupun tidak formal; bukan milik individu; dan bersifat tradisional. Maka apakah kita menganggap tak ada masalah dengan hilangnya Subdin Kebudayaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung?
Menyatukan kebudayan dengan pariwisata, membuat kebudayaan dianggap sebagai benda, dan dihitung secara materi. Kebudayaan dipandang bagaimana bisa menjual dan dijual di pasar pariwisata. Dan jika kebudayaan tak bisa dijual dan menjual sebagai devisa negara (daerah), kalau tidak ditinggalkan maka bagaimana caranya direvitalisasi dan pelestarian demi pemuasan para pelancong (wisman-wisdom).
Persoalan dan nasib kebudayaan Lampung tidak bisa sepenuhnya berharap campurtangan terlalu jauh dari (pemerintah) pusat. Apalagi kabinet SBY yang juga tidak terlihat sense of culture dengan tidak membuat Departemen Kebudayaan tersendiri. Semampangnya, otonomi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh daerah beserta kebudayaan daerah masing-masing. Oleh karena itu, (kebudayaan) Lampung dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri: Lampung. Ini dengan catatan masyarakat Lampung, apakah ia dari etnis Lampung ataukah etnis nonLampung, sama-sama sepakat untuk memajukan kebudayaan Lampung.
Masyarakat mendorong pemerintah daerah membuat Perda Kebudayaan sebagai political will untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Lampung. Kenapa pemerintah Jawa Barat mampu menelurkan perda tentang kebudayaan, di Lampung sampai kini baru sebatas rancangan di meja legislatif? Mungkin rancangan perda kebudayaan itu masih lama, namun diperparah perilaku legislatif yang hanya mengenakan pakaian adat pada saat-saat tertentu enggan sementara pembuatannya telah mengeluarkan anggaran tidak kecil.
Di sinilah saatnya masyarakat mendesak pemerintah (daerah) membuka simpul-simpul tak berkembangnya kebudayaan Lampung. Ke depan, kita letakkan harapan sekaligus mendesak kepada calon gubernur/wakil gubernur serta wajah baru di legislatif hasil Pemiu 2009 untuk kehidupan (ber)kebudayaan Lampung. Harus ada strategi kebudayaan dalam pemerintahan yang baru di Lampung, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di segala lini tetap bermatra kebudayaan. Artinya, merenovasi dan merevitalisasi kota melalui pembangunannya, tidak menghancurkan (meruislag) bangunan-bangunan yang sudah menjadi ikon (penanda), bangunan atau gedung berciri budaya Lampung tidak dipunahkan demi kota bernuansa modern.
●sudut bandar lampung, 23 juni 2008 ◘
*) disampaikan pada Seminar Kebudayaan Lampung bertema Marginalisasi Mayarakat Adat Lampung di Tengah Arus Globalisasi, Lembaga Peduli Budaya Lampung, Bandar Lampung, 29 Juni 2008.
Kebudayaan Hilang
Oleh Isbedy Stiawan ZS
Sastrawan, pemerhati seni dan budaya
MEMASUKI tahun 2008, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung “semakin langsing”. Selain Subdin Pemuda dan Olahraga yang menjadi instansi tersendiri, ternyata Subdin Kebudayaan di instansi tersebut telah marger ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
Ternyata “hilangnya” Subdin Kebudayaan di Dinas Pendidikan, tidak menimbulkan reaksi dari kalangan seniman (apatah lagi budayawan) Lampung. Seakan kebudayaan tidak begitu penting di dalam pendidikan sekolah.
Lalu dengan cara apa siswa (generasi muda) dapat mengenal dan mengapresiasi kebudayaan (dan kesenian), jika instansi yang bertanggung jawab pada pendidikan telah meniadakan subdin kebudayaan? Apakah para siswa (SMP dan SMA) diharap mencari dan meraba sendiri dalam rangka mengapresiasi kebudayaan yang ada dan berkembang di Tanah Air? Apakah pengenalan kebudayaan diserahkan masing-masing siswa, keluarga, dan lingkungan di mana ia dibentuk?
Persoalan yang seharusnya disikapi dengan prihatin ini, layaknya tidak “berbunyi”. Berbeda ketika rencana Pemprov Lampung ingin meruislag GOR Saburai, reaksi penolakan sangat gencar. Akan tetapi, ketika kebudayaan ditiadakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, tak ada satu pun reaksi penolakan yang datang dari seniman, budayawan, lembaga kesenian, dan lembaga kebudayaan (termasuk lembaga adat dan penyimbang adat).
Adakah itu semua indikasi bahwa masalah kebudayaan (budaya/adat) hanyalah “manis di bibir, tapi tak berakar di hati?” sebagaimana kebiasaan kita yang kerap menggembor-gemborkan jargon tanpa realisasi dalam kehidupan nyata. Provinsi Lampung memiliki jargon yang rancak: “mak ikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi” untuk membangkitkan semangat membangun dan memajukan senibudaya di daerah ini.
Akan tetapi, sayang seribu sayang, jargon yang pernah muncul di banyak spanduk di jalan-jalan—bahkan dibentang di depan Sekretariat Dewan Kesenian Lampung (DKL)—tidak pula menggetarkan untuk kemudian peduli bagi pengembangan dan kemajuan senibudaya di daerah tercinta ini.
Buktinya jelas: (sekali lagi) tak ada satu pun suara keprihatinan dari kalangan budayawan dan seniman ketika pemerintah meniadakan Subdin Kebudayaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Tak ada seorang pun dari lembaga adat maupun penyimbang adat dan lembaga kesenian) yang memberi saran kepada pemerintah, bahwa kebudayaan di instansi tersebut masih sangat penting dan diperlukan. Mengingat penanaman nilai-nilai budaya (di dalamnya kesenian) akan sangat tampak manfaatnya jika dilakukan sejak generasi muda di bangku sekolah (SMP dan SMA). Sedangkan di perguruan tinggi, mereka tinggal pendalaman.
Pengenalan, pengajaran, dan cara mengapresiasi kebudayaan sangat tepat dilakukan di usia sekolah. Karena itu, peran tersebut hanya bisa dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan. Sementara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak mungkin melakukannya. Pasalnya instansi tersebut tidak beurusan pada pendidikan/pengajaran, melainkan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai performa dan bisa “dijual” dalam pasar pariwisata.
Oleh karena itu, bisa dibayangkan bagaimana anak didik kita mendatang sekiranya mereka tak pernah dikenalkan sekaligus dibiasakan mengapresiasi kebudayaan yang berkembang banyak di Tanah Air. Suatu masa nanti, dengan “kebutaan”nya terhadap senibudaya milik etnis yang ada, akan sulit membangun rasa menghormati kebudayaan (adat) yang ada.
Padahal kita selalu mengkhawatirkan betapa arus globalisasi sangat mengancam generasi muda. Nilai-nilai budaya yang dimiliki generasi muda akan tergerus oleh kebudayaan yang datang dari luar. Bahkan, ancaman globalisasi dengan berbagai kebudayaan yang tak selaras dengan adatistiadat keIndoneasian, sudah sangat cepat sekali masuk hingga ke bilik-bilik privasi. Ancaman sekaligus tantangan itu, seharusnya dieliminir dengan mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia di dalam diri generasi muda.
Dan, saya kira hanya melalui dunia pendidikan itu semua bisa dilakukan. Sepertti yang saya ketahui selama ini ketika Subdin Kebudayaan masih ada di Dinas Pendidikan, para siswa diperkenalkan dan diberi workshop tentang berbagai kesenian dari berbagai budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Paling utama adalah pengenalan dan pengapresiasian kesenian dan kebudayaan Lampung.
Saya sering mengamati program-program apresiasi dan workshop yang dilakukan Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan. Dari pengalaman siswa, saya menyimpulkan bahwa mereka terbantu dengan program di luar sekolah. Seperti untuk pengenalan situs dan kebudayaan, Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan menyelenggarakan Kemah Budaya di Pugungraharjo. Di tempat itu, siswa di samping mengenathui langsung situs purbakala juga mendapat wawasan seni dan budaya dari narasumber.
Begitu pula pelatihan tari, musik pengiring tari, sastra tutur (tradisional) Lampung seperti wawancan, ringget, dadi, dan banyak lagi. Termasuk pengenalan tehadap karya sastra modern dan tradisi seperti “Pertemuan Dua Arus”. Bahkan bantuan berupa alat-alat musik tradisional bagi sekolah yang memiliki sanggar seni.
Akhirnya, sebagai bangsa, kita tak ingin mengulangi kesalahan yang harus dibayar dengan ongkos besar. Yakni ketika pertikaian antaretnis jelang dan selepas reformasi. Padahal, jika saja apresiasi kebudayaan diperkenalkan sejak dini, kita akan tahu adat dan perilaku budaya orang lain.
Tetapi ini yang dilupakan tatkala rezim Orba berkuasa. Soeharto yang memiliki program transmigrasi, namun para transmigran yang dipindahkan dari Pulau Jawa ke daerah-daerah lain tak pernah dikenalkan budaya setempat. Kecuali para transmigran itu hanya dibekali parang, cangkul, uang, dan iming-iming hidup sejahtera di tempat baru. Akibatnya, pepatah yang manis dan sudah sangat kita hafal (“di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”) kerap diabaikan.
Marilah kita renung lagi: apakah keputusan menghilangkan Subdin Kebudayaan di Dinas Pendidikan sudah final dan akan banyak manfaatnya bagi generasi muda? Saya tak mau “bertanya pada rumput yang bergoyang…” (*)
14 November 2008
Pulang ke Kampung Ibu,
Oleh Isbedy Stiawan ZS
TAK dinyana dan tanpa diniatkan sebelumnya, setelah 28 tahun kembali kususuri akar ibu. Cirebon—tepatnya Desa Winduhaji, Kecamatan Sindanglaut—adalah kampung kelahiran ibu yang pernah aku kunjungi terakhir pada 1980. Kunjungan pertama saat aku berusia 5 tahun, lalu ketika kelas 1 SLTA bertandang sendiri, dan terakhir bersama dua adikku.
Kali ketiga pada 7 November 2008. Inilah saat kerinduanku amatlah memuncak pada kampung (kelahiran) ibu. Tanpa diniatkan sebelumnya, seusai acara Temu Sastra III Mitra Praja Utama (MPU) di Lembang yang berlangsung 3 hari(4-6/11), aku menyusuri kembali akar ibu: suatu budaya yang juga mengalir dalam darahku.
Ahmad Subanuddin Alwy, “raja” penyair dan pemikir budaya Cirebon yang setia menjaga independensi Dewan Kesenian Cirebon (DKC) dalam arti tak pernah meminta kucuran dana APBD Pemkot Cirebon, tulus sekali siap mengantarku ke kampung kelahiran ibu jika ingin. Kusambut berkecambah riang tawaran Alwy, panggilan akrabnya.
Tiba di Bandung dari Lembang pukul 17.00 pada Jumat (6/11) dan belum ada tanda kepastian ke Cirebon, bahkan jam keberangkatan. Alwy cuma bilang, ia sedang menunggu seorang teman untuk bertemu seseorang di Kafe Halaman. Siapa yang ditunggu dan siapa pula yang hendak ditemui, tak pernah dijelaskan. Aku menunggu sabar.
Beberapa jam kemudian, seseorang—berambut gondrong dan berjengeot serta mengenakan topi lingkar—turun dari mobil VW merah. Karena bergaya seniman, aku yang berada di depan Kafe Ampera di Jalan RE Martadinata, Bandung, langsung bersuara: menemui Alwy ya? Ia mengangguk, aku pun menyalami. Alwy keluar dari kafe. Kami pun menuju Kafe Halaman.
Pengendara mobil VW berambut panjang itu, ternyata pelukis yang kini sedang naik daun: Dirot Kadirah. Pelukis kelahiran Indramayu, Jabar, itu pernah magang dengan pelukis Sudarso di Bali beberapa tahun (1991-1995). Setelah cukup bekal ia kembali ke Indramayu, dan pada 2000 ia hijrah ke Jakarta dan kini menetap sekaligus studionya di Jalan Kayu Putih 04/01 No. 6 Pondok Cabek Udik, Pamulang Tangerang.
Sementara orang yang akan ditemui di Kafe Halaman, Bandung, tak lain Aminudin TH Siregar—kritikus senirupa, pemilik Galeri Sumardja dan dosen senirupa ITB. Awalnya aku tak tahu pemilik nama Ucok, demikian Alwy dan Dirot menyebut Aminudin, adalah kritikus senirupa yang cukup kritis dan acap kubaca ulasan-ulasannya di sejumlah media massa.
Tersebab sesama seniman—walau aku bukan dari senirupa—percakapan malam itu tetap berlangsung hidup. Pertemuan mereka ternyata hendak merancang pameran tunggal Dirot Kadirah di Galeri Sumardja ITB. Kalau pameran yang direncanakan Mei 2009 itu terealisasi, berarti itu kali kedua setelah Dirot berpameran tunggal di Galeri Nasional, Jakarta, 7-11 Oktober 2008 yang mengusung tema “Negeri Para Pejuang”.
Pertemuan di Kafe Halaman itu berakhir pukul 22.00. Entah bagaimana cara “sihir” Alwy, Dirot memacu mobil kodoknya ke luar kota Bandung menuju Cirebon. Mobil buatan Eropa tahun 1964 itu amat perkasa, dan 5 jam kemudian kami tiba di kediaman Alwy. Sedangkan kami benar-benar lelah, sehingga tak ada percakapan lanjutan. Kami lelap, saling berpacu mendengkur.
Kampung sudah berubah dan bertambah
Jalan menuju kampung ibu sudah berubah, begitu pula dengan kampungnya. Jalan sudah beraspal dan banyak cabang. Menandakan bahwa perkampungan (desa) bertambah seiring kota kian gemerlap. Aku benar-benar terkesima, bahkan pangling. Persawahan, hutan bambu, dan belukar sebagai ciri pedesaan nyaris tak lagi kerap dilihat.
Pada 28 tahun lalu, seingatku Terminal Cilimus terletak sebelah kanan jika dari Cirebon menuju Kuningan. Tetapi bekas terminal itu kini berdiri mesjid agung. Sedangkan terminal pengganti, di sebelah kiri atau behadapan dengan masjid (terminal dulu). Barangkali istilah “tukar guling” juga terjadi di sini.
Indomaret sudah ada di Cilimus. Agar tidak tersesat jangan malu bertanya. Kepada pelayan pasar mini itu Edeng—seniman, voluntir DKC, dan teman setia perjalanan kami—bertanya ihwal kampung bernama Winduhaji. Memang pelayan toko itu tak tahu, untunglah seorang pembeli menjelaskan. Kami pun memasuki Jalan Kanauman di sebelah kiri jika hendak ke Kuningan.
Sepanjang jalan sudah dipenuhi rumah-rumah penduduk, juga ada bangunan besar yang kuduga adalah gudang, dan selebihnya sawah atau pun kebun bermacam tumbuhan. Beberpa kali kami mengulang bertanya, dan selalu dijawab beragam: ada yang tahu kampung ibu, ada yang tak tahu, dan lainnya cuma menduga-duga.
Tetapi, aku tetap optimistis. Pasti kutemui kampung ibu. Aku yakin akan bertemu saudara-saudara sekandung ataupun tidak di sana. Ya! Ibuku tak mungkin lagi akan pulang ke kampung kelahiran. Sebab ia sudah uzur. Cukuplah aku yang mengikat tali silaturahim ini.
Pertama kali kujumpai rumah adik sepupu ibu. Ia, Partanda, adalah mantan kuwu (kuwu hormat). Kuwu berarti kepala desa/dusun. Sejak awal aku hanya menyebut nama dia pada tiap orang yang kutanya, sebab manalah mungkin ibuku akan dikenal lagi?
Dan, rumah ibuku semasa kecil persis di sebelah kanan rumah kuwu. Segera kujumpai dan kupeluk adik perempuan ibuku. Aku banyak mengobrol dengan mantan kuwu Partanda, juga saudara-saudara ibu lainnya. Mereka heran, tak menyangka putra Ratminah, ibuku (di kampungnya ia hanya disapa Teh Ratmi), berambut panjang dan diantar oleh tiga temannya yang juga berambut sama dan nganeh.
Cuma 3 jam aku di rumah ibuku, sudah cukup meresapi dan merapatkan kembali jarak kultur dan akar ibu. Alwy adalah orang yang sangat bebahagia ketika aku bisa sampai ke akar. Edeng, dengan mata bebrinar-binar dan berair, berkali-kali mencuri adegan-adegan harubiru antara aku dan keluarga ibu. Dan, Dirot Kadirah seperti merekam dalam benaknya ihwal yang terjadi di kampung ibu. Ya, tanpa Dirot sulit rasanya aku bisa dengan mudah sampai ke kampung ibu. Ia sangat sabar dan berkali-kali mengucap “santai saja” tiap aku meminta kesabarannya.
Selesai makan siang pukul 13.30 kami kembali ke Cirebon. Malamnya aku harus membayar kebaikan Alwy dan Edeng dengan membaca puisi dan diskusi di sekretariat DKC. Dirot juga siap berdiskusi karena ia ingin pulang ke Jakarta bersamaku, Sabtu (8/11) pagi.
Debar “Kerakyatan” Dirot
Setiap orang menyimpan kampung kelahiran atau kampung ibu di dalam dirinya. Dan, tiap urban akan selalu merindukan kampung halaman, tempatnya lahir, dibesarkan, atau setidaknya akar ibu.
Sepanjang perjalanan pulang ke kampung ibu, aku benar-benar meresapi debar “kerakyatan” yang terekam dalam sejumlah karya lukisannya. Debar dari pekikan rakyat yang diwakilkan para nelayan, sungguh suara yang tak bisa dipungkiri: ia meniscaya. Itulah juga yang saya tangkap dari wajah-wajah manusia yang hidup di Winduhaji—sebuah desa yang nyaris terisolir kalau saja transportasi (jalan dan kendaraan) tak pernah dipedulikan—yang lugu namun perkasa.
Demikianlah, misalnya, aku dan Dirot Kadirah. Aku dilahirkan di Tanjungkarang (Lampung) tentu menyimpan kenangan pada akar dan atau kampung kelahiran ibu. Begitu pula Dirot yang lahir dan berdarah Indramayu (Jabar), namun pernah urban di Bali dan kini di Jakarta. Ia punya kenangan dan kerinduan pada tanah pesisir Indramayu. Kehidupan orang-orang Indramayu yang nelayan. Kehidupan sehari-hari dari hasil kekayaan laut.
Itulah mengapa Dirot sangat kental pada kehidupan nelayan Indramayu. Itu terekam di dalam karya-karya lukisnya (lihat “Dirot Evolution in first Vibration”, 2008) atau sejumlah karyanya yang telah dipamerkan di Galeri Nasional bertajuk “Negeri Para Pejuang” (7-11 Oktober 2008).
Jean Couteau memandang bahwa Dirot adalah “seniman nelayan”. Istilah yang digunakan Couteau ini, menurut Aminudin TH Siregar sangat menarik sebab selain tidak lazim digunakan, juga menunjukkan dua profesi yang berperan sekaligus secara bersamaan.
Istilah tersebut tampaknya diberikan Couteau sebagai prediket yang menerangkan identitas lain dalam diri Dirot (nelayan) serta—tentu saja—menunjuk pula pada bagaimana pelukis ini mengolah pengalaman estetisnya dari menjadi “nelayan” ke “seniman”.
Lebih jauh, Couteau mengatakan, sasaran Dirot mungkin masyarakat sosial, tetapi pelrakuannya adalah apa saja tetapi nyata. Daya tarik dari karya Dirot adalah simbolik dan realitas, sosial dan spiritual yang di dalamnya tak mungkin keluar satu sama lain.
Menikmati karya-karya Dirot seperti membawa kita pulang ke kampung ibu. Sebab kampung ibu, bagi Dirot, adalah pesisir dan para nelayan, maka rekaman ihwal laut, ikan, nelayan ataupun penjala dengan berbagai perspektif.
Ikan di tangan Dirot acap lebih besar bentuknya dibanding manusia. Sementara para manusia ditegasi dengan otot besar dan jelas. Lihatlah “Tangkapan Besar” yang menegaskan betapa kehidupan para nelayan semata bermodal fisik yang tak saja kuat melainkan harus perkasa.
Hal itu juga berarti Dirot hendak memberi gambaran perjuangan para nelayan yang notabene rakyat dari manusia Indonesia, berjuang habis-habisan dari hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Buah dari perjuangan para nelayan menundukkan gelombang besar dan kadang harus melawan badai, setelah berhasil dengan ikan tangkapan ia pulang dengan wajah semringah. Dirot melukis kegembiran “para pejuang” itu liwat karyanya “Ingin Seperti Bapak”.
Dirot sebagaimana dikatakan Aminudin TH Siregar memang berbeda dengan Hendra Gunawan. Jika Hendra lebih dekoratif ketika mewarnai kulit, maka Dirot tidak demikian. Apabila Hendra Gunawan lebih menonjolkan sosok perempua, dalam mayoritas karya-karya Dirot tampak jelas dia cenderung memunculkan sosok laki-laki.
Dan, Dirot Kadirah memang tengah memotret dunia nelayan sebagai “para pejuang” yang tak pernah mendapat pengakuan, apatah lagi penghargaan. Sebab, mereka berjuang untuk keluarganya, untuk dirinya sediri. Hidup itu sendiri adalah perjuangan.
Menyimak karya-karya Dirot Kadirah sama artinya menyelam ke dalam intelektualitas “anak nelayan” yang datang dari laut dan berbicara tentang laut. Sekitar 1986-an aku menulis baris demikian: “karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar” (puisi “Perjalanan Pelaut”) untuk menegaskan bahwa pelaut tentu tahu kapan badai datang namun mereka tetap melaut untuk menangkap kan. Maka Dirot melalui “Membaca Alam” (Dirot: The Evolution of Fish Vibration, 2008) ingin mengatakan orang-orang pantai (nelayan dalam konteks Dirot) selalu faham membaca alam. Karena alam yang mengajarkan mereka untuk berjuang, tabah, dan mencari kehidupan. Pada alam juga mereka kembali (lihat “Back to Basic, 2008: katalog, 29).
Jadi sejalan yang dikatakan Couteau, Dirot menjadikan laut, ikan dan lingkungannya sebagai penanda manusia berhadapan dengan kebsaran alam: antara nyata dan simbolik, andara sosial dan spiritual.
Hidup memang seakan selalu mengulang dan atau mengalir. Apa yang dilakukan orang tua seolah (pasti) turun kepada sang anak. Mengapakah anak nelayan ingin meneruskan tradisi sang bapak? Itulah yang ingin dikatakan Dirot melalui karyanya “Ingin Seperti Bapak”.
Bagi nelayan atau rakyat kecil, mimpi adalah harapan paling akhir tatkala kenyataan hidup menuntunnya menyimpang dari harapan/cita-cita. Harapan-harapan dan attau mimpi-mimpi itu digambarkan Dirot, misalnya liwat “Tertidur”, “Menjemput Fajar”, “Tertidur”, dan “Menggapai Bulan dan Bintang”.
Sedangkan “Honey Moon” bagi seorang nelayan (anak nelayan) tidaklah menjadi prioritas sebagaimana dilakukan pasangan pengantin dari keluarga kaya atau di perkotaan. Karena bulan madu bagi sepasang pengantin dari masyarakat nelayan, tak akan jauh dari laut. itulah yang ingin dibicarakan Dirot dalam “Honey Moon”. Atau imajinasi seorang nelayan bagi pasangannya, layaknya pelaut yang menggamit putri duyung (lihat “Imagination”, 2008: katalog, 46).
Tampaknya karya-karya Dirot dalam “Negeri Para Pejuang” merupakan personifikasi potret dirinya yang nelayan. Bagi Aminudin, kehadian sosok-sosok di dalam kanvasnya itu tak terlepas dari hal ihwal tentang dirinya, sebab Dirot memang tengah membangun narasi tentang apa yang terjadi di sekitarnya.
Kalau Dirot terlahir sebagai anak nelayan dan atau anak laut (“Diri ini Laut”, 2008: 39, “Aku ini Laut”, 2008: 50) ia tak akan melepas diri, bahkan ia menyelami setiap ihwal yang berlangsung di sana. Maka aku tak dapat menghindar dari sergapan kerinduan pada kampung ibu.
Dalam arti lain, kampung dan alam sekitarnya bagi kami sesuatu yang selalu melambai dan ingin sekali digapai…
Lampung, 11 November 2008
16 Mei 2008
Persaudaraan Cirebon-Banten-Lampung sudah berlangsung 450 Tahun
Persaudaraan Cirebon-Banten-Lampung sudah berlangsung 450 Tahun
Oleh Isbedy Stiawan ZS
MAJELIS Penyimbang Adat Lampung (MPAL) yang langsung dipimpin Gubernur Lampung Drs. Sjahroedin Z.P., S.H., berkunjung ke Keraton Kanoman dan Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Kesultanan Banten dan Desa Cikoneng Banten, 8-10 Februari 2007 lalu, berlangsung sukses. Kunjungan tersebut juga disertakan 10 seniman dari Dewan Kesenian Lampung, tim ahli Gubernur, dan birokrat.
Gubernur Lampung saat diterima Pangeran Mohammad Emiruddin dari Keraton Kanoman mengatakan, Cirebon adalah saudara tertua bagi Lampung. Oleh karena itu, ikatan persaudaraan ini harus lebih ditingkatkan lagi pada masa-masa sekarang hingga mendatang. “Artinya, jika Cirebon ‘diserang’ maka Cirebon berada di depan dan Lampung di belakang. Begitu sebaliknya, jika Lampung diserang, Cirebon di belakang dan Lampung berada di depan,” ujar Sjahroedin dalam sambutannya.
Ia punya alasan mengapa Cirebon dan Lampung memiliki pertalian saudara. Dijelaskan, ketika Sultan Syarif Hidayatullah melakukan penyebaran Islam di Banten lalu sempat singgah di Lampung dan menikahi muli (perempuan) Lampung bernama Ratu Sinar Alam. Setelah itu, sultan kembali ke Banten dan membawa masyarakar Lampung dari 40 pekon (desa) untuk membantu penyebaran agama dan melawan penjajah. Warga Lampung yang selamat mencapai Banten kemudian berjuang habis-habisan membantu sultan. Karena kegigihan orang Lampung, yang masih hidup kemudian dihadiahi sepertiga Banten.
Sebagaimana dijelaskan M. Furqon, orang Lampung beberapa generasi dari Cikoneng Banten, surat wasiat sultan kini berada di Belanda. “Saat kini, orang Banten asal Lampung hanya menempati 4 desa di kawasan Anyer Banten, yaitu Cikoneng, Tegal, Bojong, dan Duhur,” jelas Gubernur Lampung Sjahroedin ZP. Oleh karena itu, merujuk Sultan Syarif Hidayatullah, Gubernur Lampung menyimpulkan antara Lampung dan Cirebon sesungguhnya bersaudara. Itu sebabnya, melalui kunjungan tersebut, ibarat pepatah: ingin mempersatukan kembali balung pisah (tulang yang berserakan, persaudaraan yang terpisah jarak), hendak mengikat tali yang sempat putus.
“Hubungan kekerabatan ini, sebaiknya tak hanya adat atau budaya yang kembali diikat. Melainkan dalam hal lain, misalnya pembangunan, kalau mungkin dapat bekerja sama,” kata Sjachroedin.
Dalam kesempatan di Kesultanan Kanoman dan Kasepuhan, Gubernur Lampung memberikan bantuan dan bawa-tangan lainnya. Misalnya, di Kesultanan Kasepuhan—pusat penyebaran agama pertama di Cirebon—Gubernur Lampung menyerahkan bantuan 3 ekor kerbau. Dalam kesempatan itu juga, Sjahroedin berulang menyebutkan bahwa kunjungan “budaya” itu dimaksudkan untuk membuka wawasan orang Lampung, terutama para penyimbang adat. Sehingga, setelah kembali ke Lampung tidak lagi ibarat katak di dalam tempurung, pikiran picik, dan berjuang untuk kembali menyusuri berbagai peninggalan leluhur yang mungkin masih terpondam. Ia menyebut, jika memang di Lampung pernah ada Kerajaan Tulangbawang atau Skalaberak, maka mesti dicari bukti-bukti tentang itu semua. “Sebab beruntung Cirebon dan Banten yang masih memiliki bukti-bukti,” katanya.
Gubernur juga berharap ke depan, tidak ada lagi ritual pemberian gelar bagi seseorang dengan sangat mudah seperti selama ini terjadi. “Harus ada kriteria mengapa seseorang diberi gelar adat, bukan karena ia memiliki banyak uang.”
Majelis Penyimbang Adat yang seharusnya menyeleksi dan menentukan kriteria tentang pemberian gelar. Selain itu, penyimbang adat juga bekerja untuk menjaga nilai-nilai adat, tradisi, dan peninggalan sejarah yang masih ada di daerah Lampung. Dengan demikian, sejarah masa Lampung dapat ditelusuri. Syahroedin yakin bahwa Lampung masih memiliki sejarah budaya yang tak kalah dengan daerah-daerah lain di Tanah Air. Hanya saja, jika di daerah lain sejarah itu masih meninggalkan bukti seperti keraton, makam, ataupun berupa aksara.
Ia mencontohkan Kerajaan Tulangbawang di Menggala, sampai kini masih diragukan kebenarannya karena tidak adanya bukti. Begitu pula di Skalabrak, situs di Pugungraharjo, dan sebagainya.
450 Tahun Cikoneng
Kunjungan terakhir MPAL dan DKL berakhir di pekon (desa) Bojong, Cokoneng, Kec. Anyer Banten. Di tempat ini, rombongan Gubernur Lampung membagikan bingkisan sembako untuk 250 keluarga. Selain itu membantu uang tunai Rp10 juta untuk pembangunan mesjid di Bojong dan Rp15 juta bagi pembangunan masjid di Tegal. Gubernur juga berjanji akan membantu perahu motor bagi warga Banten asal Lampung, setelah dibicarakan lebih dulu.
Mayoritas warga asal Lampung di empat pekon di Banten bermata pencarian sebagai nelayan. Kehidupan mereka juga banyak yang kurang beruntung. Berbeda dengan orang lampung berasal dari Banten di Provinsi Lampung; banyak yang bernasib baik di eksekutif, legislatif, dan swasta.
“Karena itu, saya berharap orang Banten asal lampung di sini juga mendapat hak yang sama dengan warga banten lainnya. Namun demikian, kesamaan hak itu harus diimbangi dengan tingkat pendidikan dan profesional yang baik pula,” katanya.
Untuk ke depan, orang Lampung di empat desa Cikoneng diberi kesempatan belajar, bahkan kalau mungkin menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi di Lampung. Gubernur Lampung juga siap membantu pengadaan perahu motor bagi nelayan Banten asal Lampung tersebut.
Menurut M. Furqon, keturunan Lampung di Desa Bojong, Cikoneng, Banten yang juga pengurus DPP Lampung Sai, warga Cikoneng asal Lampung (ada empat desa: Cikoneng, Bojong, Tegal, dan Duhur) sudah hidup turun-temurun selama kurang lebih 450 tahun. Kedatangan orang Lampung ke Banten karena diajak Sultan Syarif Hidayatullah setelah mempersunting Ratu Sinar Alam, gadis Lampung. Dipekirakan 40 pekon membedol lalu menyeberangi Selat Sunda dan menepi di Anyer.
Dari sinilah para pemuda Lampung yang amat gigih bahu-membahu memperkuat Sultan Syarif Hidayatullah melawan penjajah, mempertahankan tanah Banten, dan membantu sultan dalam penyebaran Islam di Banten. Sejak itu orang Lampung menetap di empat desa di tepian pantai Anyer, setelah surat pembagian wilayah yang diberikan Sultan Syarif Hidayatullah dibawa ke Belanda. “Padahal dalam surat wasiat itu, orang Lampung yang membantu sultan diberi wilayah sepertiga dari tanah Banten. Kini kami hanya menempati empat desa,” tutur Furqon.
Akulturasi
Orang Lampung di Cikoneng memang telah terjadi akulturasi. Hal ini dimaklumi karena sudah 450 tahun turun-temuruh mereka menempati empat desa di Anyer, Banten. Mungkin kalau tak ada kepedulian Sjahroedin ZP—jauh sebelum ia menjabat Gubernur Lampung—sebagai Ketua DPP Lampung Sai berkunjung ke Cikoneng untuk menyalurkan bantuan sembako, uang, pakaian adat, dan penjelasan perkawinan adat. Meskipun pakaian adat sudah kerap dipakai pada saat-saat tertentu—misalnya menyambut kunjungan rombongan Gubernur, MPAL, dan DKL, para gadis (muli) berpakaian adat, namun bahasa sehari-hari mereka adalah percampuran bahasa Lampung dan Banten. Misalnya, ketika meminta tamu asal Lampung agar menempati kursi yang telah disediakan karena acara segera dimulai, salah seorang panitia berujar: “puari kabeh, mejong diji.” Puari adalah basa Lampung yang berarti saudara, sedangkan kabeh berasal dari Banten yang maksudnya semua atau sekalian.
Akulturasi itu, menurut Furqon, terjadi pula pada pergaulan sehari-hari. Selain itu, perkawinan campur yang juga berlangsung cukup lama, di samping hadirnya suku-suku lain ke desa tersebut. Akulturasi ini akhirnya memperkaya citarasa budaya masyarakat asal Lampung di Cikoneng.
Namun demikian, masyarakat asal Lampung di sana mulai menyadari “tanah asal” dan merindukan kembali kepada akar tradisi dan budaya Lampung. Itu sebabnya, kunjungan MPAL, DKL, dan Gubernur Lampung disambut antusias dan keterharuan seluruh warga asal Lampung di Cikoneng. “Kami memang warga Banten, tapi kami orang (ulun) Lampung. Bahasa dan adat istiadat kami memang bercampur (Lampung dan Banten, red.), tetapi akar kami adalah Lampung.” Maka benar adanya pepatah: “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Masyarakat Cikoneng sudah membuktikan itu…