Kumpulan Cerpen
ISBEDY STIAWAN ZS
hanya untuk
satu nama
Daftar Isi
Kata Pembuka ….. v
1. Pertempuran hingga Pagi …..
2. Kupu-Kupu di Jendela….
3. Ibu Berperahu Sajadah….
4. Perempuan yang Berenang saat Bah….
5. Sarmi Hamil…..
6. Lelaki Asing di Gedung Pertunjukan….
7. Pintu Vila itu Dibiarkan Terbuka…..
8. Hanya untuk Satu Nama …
9. Batas Rencana ….
10. Pasien Terakhir …..
11. Batu Itu Tak Terbang ke Langit…
12. Perempuan di Ladang Tebu ……..
13. Ruang Asap ……..
14. Hikayat Wajah ……..
15.
16. Sonar
Kata Penutup …….
Tentang Penulis
(Catatan: Kumpulan cepen ini sudah diterbitkan C/Publishing Bentang Yogyakarta)
KATA PEMBUKA
PRODUKTIF. Itulah komentar teman-teman—baik diucapkan sungguh-sungguh, separuh serius, atau basa-basi—kepada saya (ada yang melalui short massage service atau langsung saat berjumpa). Memang dalam dua tahun terakhir ini, saya begitu “gila” menekuni profesi yang dianggap pula sebagian orang “gila” ini.
Maaf, jika saya telah menetapkan dunia sastra menjadi profesi. Saya dengan begitu beraninya (semoga bukan sekadar kesombongan) untuk “menumpang hidup” dari karya sastra. Memang belum sampai menjanjikan. Tetapi, dari terlalu kerapnya karya-karya sastra (terutama puisi dan cerpen) saya yang dimuat di berbagai media
Karya-karya saya mengalir, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Selain dua kumpulan puisi yang terbit pada 2003, kiranya enam buku lainnya justru menghimpun certa-cerita saya. Setelah Ziarah Ayah (2003), mengalir kumpulan cerpen saya berikutnya yakni Bulan Rebah di Meja Diggers, Badai Kembali Berdenting, Perempuan Sunyi (2004), Selembut Angin Setajam Ranting, Seandainya Kau Jadi Ikan (2005), dan buku yang ada di tangan pembaca ini: Hanya untuk Satu Nama.
Saya tak pernah membedakan—untuk soal keseriusan—saat menulis puisi ataupun cerita. Bagi saya kedua bidang garapan itu sama-sama mementingkan kesungguhan. Saya tak (akan) bermain-main dalam berkarya, meski urusan kualitas kemudian saya serahkan sepenuhnya pada redaktur, editor, kritikus, dan pembaca. Soal mutu bukan lagi urusan penulis, sebab adanya ukuran-ukuran lain di luar proses kreatif (: kreativitas).
Maafkan, saya telah “menumpang hidup” dan menjadikan sastra (writing) sebagai profesi, sebagai kerja (juga ibadah?) saya menyelesaikan umur ini. Tetapi, saya tak pernah akan terperangkap ke dalam jaring rutinitas semata untuk profesi saya ini. Artinya, saya tetap menumpukan kerja saya dari inspirasi, imajinasi, dan atau perburuan-penjelahan imajinasi (-inspirasi). Dengan begitu, saya menghendaki tidak terjebak pada stagnasi. Kreativitas saya pacu agar terus berubah; adanya perubahan dan perbedaan dari satu karya ke karya yang lain.
Bukan maksud saya memanfaatkan booming penerbitan buku cerita pendek, sehingga saya lebih banyak bergiat dalam kubangan yang satu ini. Tetapi memang, harus diakui, banyak penerbit di Tanah Air yang sigap menyambut kiriman naskah cerita ketimbang kumpulan puisi.
Sebagai juru cerita, saya sadari sangat tertarik mengeksplorasi persoalan manusia. Di dalamnya tentu ada mahluk berkelamin perempuan dan lelaki, berkelindan masalah-masalah sosial dan seterusnya. Jika terlihat banyak pendekatan saya ke mahluk perempuan, bukan karena ingin mengeksploitasi kelamin ini. Disebabkan masalah di dalamnya yang saya anggap (masih) seksi (baca: menarik), sekaligus penuh misteri. Sebagaimana pernah saya ungkapkan dalam salah satu puisi saya: aku dapati kematian/
tiap gali rahasia perempuan// engkau, perempuan, rahasia/yang sulit diselami/seperti kematian/yang kurasakan/setiap petang…(“Seperti Kematian”, 2004; Kompas, 20 Februari 2005)
Yang jelas, pada kesempatan yang amat rugi saya alpakan ini, sepantasnya saya berterima kasih pada Ita Dian Novita yang memperkenalkan kumpulan cerpen ini pada PT Bentang Pustaka, sekaligus terima kasih saya pula pada Penerbit Bentang dan Suhindrati Shinta yang amat kooperatif sebagai editor. Lalu teman-teman dekat saya yang banyak mendukung dan membantu, seperti Martin Aleida, M. Arman AZ, Hary Jayaningrat, Hamsad Rangkuti, Syahnagra Ismaill, Ch. Heru Cahyo Saputro, Daniel HG, Syaiful Irba Tanpaka, Maman S. Mahayana, Ibnu Khalid, Firman Seponada, Oyos Saroso HN, Budisantoso Budiman, Radhar Panca Dahana, Zen Hae, Jauhari Zailani, Jamal D. Rahman, Edy A. Effendi, Satmoko Budisantoso, Raudal Tanjung Banua, Moch. Wan Anwar, Taufik Ikram Jamil, Hary B. Koriun, Asma Nadia, Hudan Hidayat, Iswadi Pratama, R. Krisman, A.J. Erwin, dan banyak lagi yang sulit disebutkan di sini. Karena perhatian merekalah, saya masih ada di ranah sastra ini. Setelah itu, adalah pembaca sebab tanpa Anda maka cerita-cerita dalam buku ini akan selamanya membisu…
Perumahan Beringinraya--
Bandar Lampung, 21 Februari 2005
Isbedy Stiawan ZS
1. Pertempuran hingga Pagi
TIBA-TIBA ia menjauh dan lesap di rimbun semak. Terdengar suara gemuruh kelimunan orang. Memburu. Pentungan dan parang mengacung-ancam…
“Dia lari ke arah itu,” terdengar suara menujah dari salah seorang pengejar.
“Masuk ke semak!” buru suara lain.
“Kejar!”
“Tangkap!”
Jika tertangkap mau diapakan?
“Bakar hidup-hidup!”
“Tapi, dia sembunyi di mana?”
Malam pekat. Rimbunan pohon, tanah luas berawa, dan rimbunan semak. Serbahitam tempat itu. Yang diburu, entah sengaja atau tidak, berpakaian gelap. Ia tak mendengus. Diam. Membisu. Mencermati tombakan orang-orang menyumpah, dengan perasaan gemetar dan cemas.
Mungkinkah ini hari terakhirku di dunia? Barangkalikah ini akhir aku menghirup napas sebagai manusia?
Terbayang tubuhnya diseret orang. Bertubi-tubi pentungan dan kayu atau besi—juga tinju—mendarat. Tak terhingga parang pun menguliti tubuhnya. Lalu cairan merah mengalir dari tubuhnya. Kemudian cairan minyak membasahi badannya, dan sekejap kemudian sepercik api pun dilempar. Menyulut…
Beberapa jam sebelumnya, ia duduk di kedai kopi ujung jalan itu. Ia menyeruput segelas kopi yang masih mengepulkan asap, dua pisang goreng dan tiga gorengan lain di piring lain di depannya. Matanya nanar meski masih tampak sangar. Tak banyak cakap. Selalu menunduk atau membuang pandang ke sembarang.
“Dia tadi kulihat di kedai tak mau bersitatap wajah. Rupanya ia tak ingin dikenali,” kata lelaki yang membawa kayu kasau. “kalau kutahu dia, sudah saya hajar waktu minum kopi tadi!” lanjutnya. Lelaki itu tampak geram.
“Kalau tertangkap, kita hajar saja!” sambut yang lain.
Yang lain seperti koor menyatakan “Setujuuuu….”
Lalu sekelimunan orang itu kembali merangsek ke semak-semak, seperti mendapatkan kembali semangat setelah beberapa waktu tadi merasa sia-sia mengubek tempat itu.
Hanya sampai sejauh itu, ia masih aman dari amukan
Tidak! Ia membatin. Mereka, para warga yang makin beringas itu, tak boleh menyentuhku. Apalagi sampai melukai tubuhku. Mereka tak kuizinkan dapat mengendus persembunyianku ini. Aku tak hendak mati di tangan orang-orang kampung itu. Ia kembali menggumam.
Binatang malam mulai usi; Terutama sekali nyamuk hutan dan semut sudah menggerayang dan menggigiti kulitnya. Nyaris ia memukul seekor nyamuk yang tengah menghisap darahnya.
Desah napasnya bercampur ketakutan. Barangkali inilah akhir petualangannya sebagai penjahat. Sebagai maling.Inilah pertempuran habis-habisan melawan maut. Orang bilang, sepandai-pandai tupai melompat suatu ketika akan jatuh. Boleh jadi inilah kejatuhan baginya. Akhir dari sebuah pertempuran? Entahlah.
Namun hatinya berkeras. Semangatnya untuk melawan selalu dinyalakan. Aku tak hendak mati konyol di tangan mereka. Ia mendesis. Kasihan Minem, kalau kumati ia tak lagi bersuami.
Maka ia tahan desah agar tak terdengar para pencari itu. Ia tutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Sementara puluhan nyamuk yang menggerayang dan menghisap kulitnya, ia biarkan.
“Hisaplah darahku, minumlah sepuasmu kawan. Kita sama-sama penjahat, peminum darah…” menggumam seperti berbiacara dengan puluhan nyamuk. “Tapi mereka sekarang juga sedang haus darah, lapar ingin membunuhku! Hanya, mereka tak akan bisa menghabisi nyawaku, tak akan kurelakan seinci pun tubuhku dirajam!” kembali ia membatin.
Ia bayangkan Minem, terbujur di ranjang. Menahan sakitnya dengan sabar. Pasrah. Wajahnya selalu tersenyum. Seperti setiap waktu Minem tunjukkan padanya. Dan Manto dengan setia menemani dan mengurusi ibunya. Mengambil air minum jika Minem haus. Menyuapkan nasi apabila saatnya makan. Manto anak yang baik, selalu berbakti. Batinnya.
Pikirannya menerawang ke masa silam. Saat ia menyunting Minem. Tiada halangan apapun sebab Minem memang mencintainya. Meski beberapa lelaki lain juga ada yang mengincar. Ia menang tanpa pertarungan hebat-hebatan. Dengan sangat gampang ia lamar Minem. Waktu ia masih bekerja di sebuah pabrik susu di
Setelah punya Manto, kehidupannya mulai terombang-ambing. Pabrik susu tempatnya bekerja pelan-pelan susut produknya. Banyak saingan pabrik serupa. Ketika Manto berusia 8 tahun, pabrik susu itu tutup.
Seorang teman lama semasa SMP mengajaknya membobol sebuah kantor. Berhasil. Inilah awal ia masuki belantara hitam. Pekat. Penuh dosa. Berjuta ancaman dan risiko menghadang. Cuma semua itu ia harus jalani. Sebab ia tak hendak istri dan tiga anaknya mati karena lapar.
Bertahun-tahun. Ia selalu sukses selama ini. Tak pernah tertangkap. Karena itu ia masih asing dengan bui. Namun bukan karena ia lihai atau memiliki ilmu maka selalu luput. Tidak tertangkap. Disebabkan nasib baik saja. Tuhan belum menghendaki ia ditangkap dan masuk penjara. Bahkan ketika temannya tertangkap lalu dijebloskan ke penjara selama 5 tahun, ia tak pernah disebut-sebut ikut terlibat. Sampai disiksa habis-habisan, temannya tetap menjawab, “Saya bekerja sendiri. Tak punya kawan…”
Kini ia masih sendiri di dalam semak itu. Temannya yang lain, pendatang baru di dunia maling, tadi selamat dari kejaran. Barangkali temannya itu sekarang sudah terlelap di rumah. Boleh jadi sedang bercinta dengan istrinya.
Kalau saja ia tertangkap kelak, ia akan lakukan seperti temannya dulu. Tak akan melibatkan yang lolos. Biarlah temannya menikmati kebebasan…
MATAHARI kemerah-merahan mulai menyembul di Timur. Menyinar di antara rerimbun pohon. Sebentar lagi siang menjelang. Ia berharap orang-orang kampung itu tak sabar menanti ia keluar dari persembunyian, lalu pulang ke rumah masing-masing. Saat itu ia akan keluar dari belukar itu.
Cuma harapan itu sia-sia. Warga kampung malah makin ramai. Mereka yang hendak ke kantor ikut menimbrung. Anak-anak yang seharusnya pergi ke sekolah, berhenti pula di situ. Membentuk rombongan baru. Dari semak-semak, ia mengintip orang-orang itu. Tubuhnya kembali gigil. Makin menggeremang. Keringat dingin mengucur.
“Ya Tuhan, tolonglah…”
Lantas matanya terpejam. Ia seperti melangkah dari dalam semak itu. Tak seorang pun tahu atau melihatnya. Pulang. Minem yang masih terbaring menyambutnya riang. Manto ternganga memandangi kedua orang tuanya yang berpelukan.
“Ayah enggak apa-apa?”
“Kau tak apa-apa, Mas?” Minem menyambung.
Ia mengangguk.
Tersenyum.
Menatapi Minem dan Manto.
“Sampai kapan Mas seperti ini. Diburu-buru…” lanjut Minem. Suaranya pelan dan nyaris berbisik. Khawatir terdengar. Dia tatap suaminya yang tampak sekali kelelahan. Napasnya masih terengah-engah.
“Entahlah…” Cuma itu yang meluncur dari bibir lelaki itu. Lalu…
“Itu dia orangnya!” terdengar dari salah seorang sambil menunjuk persembunyiannya di balik semak. Teriakan itu membuyarkan angannya.
Matahari sudah tampak penuh.
“Mana??” tanya yang lain.
“Itu… Di semak yang bergerak itu!”
“Jangan lari!”
“Tangkap…”
“Hajar!”
“Habisi!”
“Bakar….”
Setelah itu suara langkah orang-orang kampung yang lari membelah semak semakin riuh. Gaduh. Menuju persembunyiannya. Kali ini ia tak lagi dapat menghindar, apalagi lari menyelamatkan diri. Sudah terkepung. Tak dapat kabur.
Setelah itu berulang benda tumpul bersarang ke tubuhnya. Menghantam dirinya. Teriakan minta tolong sudah tak lagi terdengar. Kecuali aduh dan rintihan. Makin lama semakin pelan.
Matahari sudah tampak penuh…
2004-2005
2. Kupu-kupu di Jendela
--empatiku untuk cerpenis azhari--
KUPU-KUPU itu, dulu, selalu singgah di jendela kamarku. Setiap pagi. Kala embun belum pula kering. Matahari lamban bersijingkat. Jendela baru mengembang. Menanti siang menjemput. Bunga-bunga membuka kelopaknya.
Dan, pada saat itu aku akan memandang ke taman. Alangkah indah: penuh warna hijau dan merah. Kupu-kupu bersayap warna-warni. Binar. Cahaya. Pandanglah selalu ke taman. Angin tenang. Belai. Aku melihatmu di kejauhan. Seperti tertelan semak.
Kutarik tubuhku ke paling tepi jendela. Matahari masih seperti pagi kemarin. Tiada berubah. Aku mendesah. Kau makin lari ke dalam semak. Ingin menghindar dari terik matahari.
Tapi aku tahu pagi ini ada yang sangat lain. Kau menjelma kupu-kupu. Bukan singgah di jendela itu. Sebab tiada lagi jendela di rumahku. Aku, maksudku kami di rumah ini, tak perlu membuka terlebih dulu jendela jika ingin memandang ke taman. Rumahku sudah terbuka. Dari mana pun kami dapat jika ingin melihat ke luar (ke taman). Karena itu, setiap waktu kami bisa melihat ke luar, menikmati sesuatu yang lain dari biasanya. Di luar
Kini taman telah berwarna coklat. Daun-daun kehilangan hijaunya. Pohon tumbang di sembarang tempat. Awan menyemburat merah. Bau amis ribuan jasad menyengat. Aku memandang, memandangnya dengan penuh cemas.
Di sini tak kulihat lagi kupu-kupu itu. Tiada taman hijau tempat biasa kupu-kupu itu hinggap, juga jendela telah tenggelam oleh gelombang besar itu. Sesungguhnya, hari ini dunia seperti mati. Ditinggal penghuninya—ratusan ribu, bahkan masih banyak lagi yang masih berserak di setiap sudut
Ladang-ladang larangan telah tumbang, bahkan tertimbun lumpur. Lumpur dari laut. Hitam. Dan, ah, orang-orang menjadi kaku. Di balik bangunan. Di dalam kubangan air menghitam. Atau hanyut entah ke mana.
“Di
Sayang, kuingin sekali melihat kupu-kupu bersayap warna-warni itu. Cuma di
Lalu berhari-hari, bahkan berganti tahun, aku tak lagi melihat kupu-kupu yang terbang. Sebab tak ada taman untuknya hinggap. Begitu pula jendela biasa ia hinggap, sejak hancur bersama ratusan ribu rumah, membuat kupu-kupu terbang entah ke mana.
HANYA awan memutih. Bagai wajahmu yang pasi. Bertumpuk antara serakan tubuh kaku. Aku masih mencari kupu-kupu itu. Kini. Kupu-kupu yang pernah hinggap di bibir jendela kamarku. Dulu sekali.
Di sini, seperti tak lagi kutemukan kupu-kupu yang entah sudah terbang ke mana. Tak akan mungkin. Juga wajah cantikmu, sayangku, meruang di dalam serakan awan itu. Antara yang masih kukenal atau asing. Inginku menyudahi pencarian ini. Aku sudah jenuh. Tetapi, mayat-mayat itu wajiblah dimakamkan, meski tak perlu kain kafan dan disembahyangkan.
Ah, aku tak berani mengenangmu kembali. Di angkasa ini aku hanya menyaksikan serakan awan; diam. Atau berjalan pelan. Bagai timbunan tanah yang mengubur tubuhku, juga tubuhmu sayang.
Sebuah kecemasan datang.
Sebuah kesedihan harus dikatup.
Enyahlah segala lara, tangis berkepanjangan, kesedihan yang melebar, putus asa yang hendak berpinak. Aku tak akan lagi memburu kupu-kupu itu. Biarlah ia tak akan pernah hinggap di jendela kamarku. Warnanya telah berganti putih, sebagaimana awan yang kulirik dari jendela pesawat ini. Tanpa terlihat kota-kota itu. Seakan mengajakku ingin bermain dalam kelembutannya.
Kau memang lembut, sayangku. Cuma jangan sekarang mengajakku bermain. Beri aku sekejap saja melupakan kematian dari ketinggian angkasa ini. Juga mengingat tubuh-tubuh kaku tertimbun lumpur atau sampah itu.
Lalu kau merajuk. Seperti seorang kekasih yang tidak mendapatkan ciuman. Diam. Ingin berlari dan memasuki awan putih itu. Dan, itu malah akan membuatku kesepian. Dari jendela pesawat yang amat kecil ini, aku cuma menunggu bakal datang kesepian yang lain. Kesepian tanpa ayah dan bunda, juga adik-adikku yang mati ditelan bah maha besar itu. Bahkan, seluruh album keluarga lenyap. Seakan ingin mengubur kenangan dan silsilah.
Aku tak punya lagi kenangan di
Ya! Kalau kutahu akan begini nasib keluargaku, tiada mungkin kutinggalkan mereka berlama-lama di tempat lain. Aku akan memilih mati bersama mereka. Biar segala silsilah tak lagi koyak seperti ini. Kini aku menjadi sebatangkara. Sendiri di kampung kelahiran. Ataukah aku harus melunta di lain
Biar pun beratus ribu kilogram senyuman yang kaukirim ke mari, tetap akan sulit menghapus lukaku. Meskipun aku bangun kembali rumah di tanah bekas rumahku yang kini telah menjadi puing, tak akan dapat mengganti kenangan lama yang telah hancur. Tersebab tak selembar album pun bersisa.
“Bukankah kau telah temukan kain Ibu, meski cabik? Maka jadikan cabikan itu sebagai kenanganmu?” bisikmu pelan. Memandang puing-puing rumahku, lumpur hitam, amis mayat, bangkai binatang penuh lalat…
“Seperti cabikan masa laluku,” sergahku. Masa lalu kami, di
“Jangan putus asa seperti itu. Masih ada masa depan bagimu. Bagi kalian…”
Tak menyahut. Kupungut cabikan kain Ibu. Kurapatkan muka telapak tanganku ke lantai bekas rumahku. Kuusap seluruh wajahku. Barangkali hanya inilah yang dapat kulakukan. Membasuh wajahku dari lumpur di bekas lantai rumahku. Lumpur yang telah menghanyutkan dan menenggelam ibu, ayah, dan adik-adikku. Mungkin juga keluarga yang lain, yang sampai waktu ini belum kutemukan.
Gelombang pasang yang diempas laut ke kampung kelahiranku, menyisakan keperihan. Pedih yang mungkin tak pernah terhapuskan. Bah yang datang di pagi ahad itu, telah meluluhkan harapanku. Ya! Aku pulang tanpa melihat lagi ibu, ayah, dan adik-adikku. Tiada lagi rumah yang dulu telah setia menerima tumpahan darah dan tuba bunda sewaktu melahirkanku. Rumah yang pertama mendengar tangisku yang awal.
“Jangan larut bersedih. Ambillah cabikan kain Bunda, dan simpanlah dalam benakmu. Jadikan kenangan, jika itu sebagai kenangan dan ingin kau jadikan kenangan. Setelah itu kau boleh tinggalkan bekas rumahmu…”
Ya! Aku akan pergi. Tetapi, ke mana aku bawa duka ini? Aku ingin melunta, sebatang kara di
AH! Aku tak lagi menyaksikan indahnya warna kupu-kupu. Kupu-kupu yang dulu kerap hinggap di jendela kamarku. Setiap pagi atau senja. Meski jinak namun tak pernah tertangkap. Kukejar kupu-kupu itu yang terbang ke taman, ladang, kebun, dan menghilang di hutan. Tersaput pekat.
Aku merajuk. Menemui Bunda. Kataku, “Tangkap kupu-kupu itu untukku, Bunda. Aku suka warnanya. Indah sekali. Aku ingin memasukkannya ke dalam toples kaca ini. Akan kupelihara hingga besar…”
“Bagaimana Ibu menangkapnya? Kupu-kupu itu telah terbang ke dalam hutan…”
“Kejar ke
Hustst! Bunda mendelikkan mata beloknya. Aku mengerti ia marah sekali. Ujar Bunda, “Itu hutan larangan. Selain rimbunan pohon ganja, hutan itu adalah tempat pelarian orang-orang yang diburu tentara. Kita bisa mati ditembak. Disangka pengacau…”
“Bukankah mati bisa di mana saja, Bunda?”
“Jangan omong begitu. Kata-kata adalah doa,” Bunda mengerem ucapanku. Kataku tersekat. Kupandangi wajahnya. Lalu menunduk. Ketika Bunda tersenyum, barulah aku mengangkat tatapanku.
“Tapi Bunda, aku ingin kupu-kupu itu…”
“Ia telah pergi jauh. Mungkin tak akan kembali,” ujar Bunda kemudian. Lalu ia kembali ke dapur, meninggalkan aku seorang di depan pintu rumah.
“Jangan omong begitu. Itu doa, Bunda. Apakah Bunda tak menginginkan kupu-kupu itu datang lagi dan hinggap di jendela kamarku?”
“Oh, maaf, anak lelakiku…” Bunda meralat. “Suatu hari kelak, kupu-kupu itu akan kembali. Ia akan hinggap lagi di jendela kamarmu. Saat itulah Bunda akan menangkapnya dan memberikan kepadamu,” ucap Bunda kemudian.
Kata Bunda lagi, “Sekarang kau mandilah. Hari sudah petang. Sebentar lagi ayahmu akan melaut…”
Aku pun ke kamar mandi. Ayah pamit hendak ke laut. Seperti hari-hari sebelumnya, ia akan menangkap ikan. Dari hasil melaut itulah kami hidup. Dan kepergian ayah itu yang terakhir. Seperti kupu-kupu yang pergi. Tak kembali. Tak akan ada lagi jendela yang terbuka menghadap laut. Tiada lagi kupu-kupu yang hinggap di
Mungkin kau tak percaya, siapa pun tak akan percaya, air pasang yang datang tiba-tiba dan hanya sekejap itu telah menghapus segala kenangan. Kini menyisakan duka…
Lampung 26/11, 30/12-2004, dan dirampungkan dalam pesawat perjalanan Pekanbaru—Jakarta 30 Januari 2005 pkl 11.20 dengan comunicator Nokia 9210i.
3. Ibu Berperahu Sajadah
SUNGGUH! Ibu cuma dapat melambai. Dibawa arus gelombang mahabesar. Tangannya yang satu lagi mendekap kitab suci, seperti menjaga nyawanya sendiri. Ibu terus menjauh, akan tetapi ia tetap melambai. Sedari tadi Ibu hendak menggamit dan menarikku—tepatnya menyelamatkan aku—dari arus air yang datang tiba-tiba. Ahad pagi yang damai berubah menjadi gaduh. Terdengar di mana-mana suara minta tolong, dan nama Tuhan dipanggil berulang-ulang.
Ibu belum mencopot mukena. Sajadah terbentang. Kitab suci di tangan. Ibu usai salat dhuha pagi itu langsung menyambar kitab suci dan membacanya. Pelan kudengar suara ibu mengaji. Di kamar sebelah. Kamar biasa Ibu meleburkan seluruh dirinya beribadah. Ah! Ibu akan selalu begitu. Akan selalu mengambil mukena, sajadah, dan mendekap Alquran. Setelah semua pekerjaan untuk mengantar Ayah ke tempat bekerja, Ibu pun akan berwudhu.
Kebiasaan itu ditambah lagi oleh Ibu dengan bercerita tentang sejarah para nabi. Tetapi, itu dulu—ya dulu sekali, sewaktu kami masih kecil. Ibu tak pernah alpa bercerita, dan kami—anak-anakknya—akan senang mendengarnya. Bahkan kami merasa ketagihan mendengar cerita ibu, setiap pagi usai ibu melaksanakan salat dhuna. Ibu amat hapal pada cerita-cerita tentang para nabi. Misalnya, cerita nabi Yunus yang selamat meski berada di dalam lambung ikan hiu. Doa nabi Yunus di dalam perut ikan yang sampai kini masih kuingat (terima kasih Ibu yang telah menugaskan kami untuk menghapal agar kami mendapat cerita lain keesokan harinya): “laa ila ha illa anta wa subhannaka inni kuntu minadzalimin…”
“Doa itu dapat kita ucapkan setiiap usai salat,” kata Ibu waktu itu mengakhiri kisah nabi Yunus. “Amat baik karena selalu berlindung dari sikap zalim,” ibu menambahkan. Lalu, Ibu menekankan bahwa dengan doa itu maka Yunus terselamatkan, dan dapat keluar dari perut ikan.
Pada kesempatan lain, usai dhuha di hari lainnya lagi, kami mendengarkan kisah Ibu tentang nabi Luth. Demikian Ibu bercerita yang dipetik dari sejarah (kaum) Luth. Pada saat itu hanya sedikit kaum Luth yang menerima kebenaran yang dibawa nabinya. Selebihnya ingkar, bahkan keluarga Luth. Lalu Allah menimpakan bencana pada kaum itu, dengan membalikkan bumi beserta isinya. Kiranya Allah hendak menghabisi kaum yang ingkar dengan menggantikan kaum yang tunduk.
“Dalam kisah lain, bahkan istri nabi Luth menjadi patung di antara dua
Ketika kami mulai remaja, Ibu pun mulai jarang memberi petuah dan anak-anaknya dibiarkan mengambil hikmah masing-masing dari cerita dan sejarah para nabi itu. Maka dari
Kata Ibu, “Pendidikan tinggi sering membuat orang menjauh dari Tuhan. Sedang kekayaan kerap membuat kita lupa pada yang memberi rezeki. Kau, anak Ibu satu-satunya yang tidak meninggalkan rumah ini, jangan bersikap seperti itu.”
Aku tersenyum. Mengangguk. Mencium punggung tangan Ibu. Saat mencium tangan itu, aku seperti merasakan kesejukan. Mungkinkah itu hawa dari surga? Aku membatin. Entahlah. Tetapi aku amat percaya di tubuh seorang ibu memancar aura surgawi. Ah. Jika itu benar betapa sejatinya akan banyak anak yang tak hendak lepas dari dekapan ibu. Ingin meriangkan hati ibu. Dan, aku amat beruntung. Tak juga mau pergi dari rumah ini, meski ada yang pernah hendak meminangku. Sampai usiaku 23 tahun ini aku masih perawan. Tubuhku belum tersentuh lelaki. Belum ada suami yang membuka hijabku dan membelai apa yang selama ini kututup rapat. Dan aku tetap bahagia.
AYAH sudah lama tiada. Ia hilang ditelan badai sewaktu melaut. Malam yang pekat. Badai turun tiba-tiba, dan Ayah tak mampu mengendalikan perahunya agar tak diterjang badai. Menurut teman-teman Ayah mengapa ia tak dapat selamat, tersebab Ayah tak mau berpisah dari ikan hasil tangkapannya. Ayah bertekad harus selamat dengan seluruh hasil melautnya. “Ayahmu sangat mencintai keluarganya. Itu sebabnya ia tak mau pulang dengan tangan hampa, dan akhirnya ia terlempar bersama perahu dan ikan tangkapannya,” kata Teuku Rafli, pamanku, yang ikut melaut bersama Ayah. Teuku Rafli selamat karena melompat dari perahu kemudian menangkap sebatang pohon yang terapung. “Paman terapung sehari semalam, sampai ditolong kapal yang liwat. Dan ayahmu entah terdampar di pasir mana, entah pula tenggelam di laut mana…” Teuku Rafli berkisah begitu tiba di rumah.
Ayah memang nelayan ulung. Bukan setahun atau dua tahun ia kenal rahasia lautan, tetapi sejak kanak-kanak ia sudah akrab dengan laut. Tersebab ia dilahirkan dan dibesarkan oleh darah pelaut. Tetapi seperkasanya seorang pelaut, kalau sudah takdir tak akan mampu mengelak dari badai. Seorang penyair pernah berujar, “karena laut mengajarkan rahasia badai, maka aku pun setia berlayar”1) demikian pula ayahku yang selalu setia melaut, meski boleh jadi ia tahu kapan musim badai: sebagaimana para nelayan tahu bila ada banyak ikan, arah perahu dituju untuk berangkat dan ke pantai. Seorang pelaut akan tahu Timur atau Barat, Selatan atau Utara, hanya dengan melihat bintang.
Tetapi, kenapa Ayah mati? Mengapa laut menggulung tubuh Ayah beserta perahunya? Mengapa Ayah tak dapat menjinakkan badai? Maaf, yang lebih tepat, mengapa badai tak bersahabat pada pelaut yang telah bertahun-tahun mengakrabinya? Pertanyaan-pertanyaan itu beberapa hari lamanya menggoda benakku. Sampai aku membuat kesimpulan: laut demikian kejam! Apa artinya persahabatan antara Ayah dan laut selama ini, kalau ayahku tak mampu menemukan rahasia badai?
Ketika kekecewaan ini kuutarakan pada Ibu, ia berujar: “Ayahmu tentu sudah memikirkan semua itu, mungkin sejak ia masih kanak-kanak dulu. Mereka yang terbiasa hidup di lautan, mungkin tak pernah terbayang matinya di ranjang. Meskipun soal kematian adalah rahasia Tuhan...”
“Tapi Ibu…”
“Allah lebih tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Rahasia kehidupan dan kematian, seluas dari misteri alam semesta ini,” Ibu memotong. “Apakah Ibu pernah mengangankan menjadi istri seorang pelaut, seorang nelayan seperti ayahmu? Tidak. Ibu malah bercita menjadi istri orang
“Ah, Ibu…” Cuma itu yang terlontar dari bibirku. Sungguh, aku enggan berdebat dengan Ibu, apalagi akhirnya membuat hatinya terluka.
“Kau pun nanti, siapa bisa tahu akan dibawa lelakimu ke mana dan dari mana asalnya…”
“Ah, Ibu…” aku merajuk. “Cut belum berpikir soal itu. Cut masih ingin bersama Ibu, selamanya…”
“Husst!” sergah Ibu. “Mustahil itu. Tak mungkin kau akan menemani Ibu selamanya. Kau akan kawin, berumah tangga, dan punya anak. Kau akan menjadi milik suami dan anak-anakmu. Dan Ibu, sejak ayahmu tiada, Ibu akan kembali sendiri. Mengurus diri sendiri…”
“Lalu, apa gunanya Cut, kalau Ibu mengurus diri sendiri. Apa gunanya anak kalau tidak mengurus orang tuanya?”
“Tetapi, sang anak akan tetap terbagi perhatiannya pada keluarganya…”
Lalu kami terdiam. Hanya saling bersitatap. Setelah itu, tersenyum.
SUNGGUH! Ibu cuma dapat melambai. Gelombang mahabesar membawanya. Kitab suci yang erat dalam dekapan tangannya yang satu lagi, kulihat Ibu seperti berperahu sajadah. Berkali-kali ibu hendak menggamit dan menarikku agar menaikki sajadah itu. Tetapi berkali itu pula sia-sia. Seperti ada yang menarik pakaianku dari belakang agar aku menjauh dari Ibu. Ahad pagi yang damai berubah menjadi gaduh. Terdengar di mana-mana suara minta tolong, dan nama Tuhan dipanggil berulang-ulang.
Kupanggil Ibu. Berulang-ulang. Kulapalkan doa yang masih kuingat, terutama doa nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan. Sekhusyuk kulisankan doa itu. “Laa ila ha illa anta wa subhannaka inni kuntu-minadzalimin…” Berulang-ulang. Terus kuucapkan. Bersama airmata yang juga terus mengalir.
Aku juga hanyut. Orang-orang juga terbawa arus. Hanyut. Rumah-rumah hanyut. Pohon-pohon tumbang. Tiang listrik ditelan air bah. Mobil-mobil terombang-ambing, menghantam apa saja yang menghadang. Jeritan di mana-mana.
Entah dari mana, tiba-tiba air amat besar menerjang desaku. Air juga memasuki
Liatlah! Ibuku berperahu sajadah. Berkendera iman, ia susuri gelombang besar di tanah ini. Ia kembangkan kain layar yang dijahitnya bertahun-tahun dengan benang takwa. Barangkali kalian tak pernah mengira, kalau Ibuku kini berperahu sajadah. Ketika
Dalam bayanganku tak akan ada lagi rumah yang masih kokoh. Bangunan itu pastilah telah porakporanda, karena beberapa kejap sebelum banjir besar datang kami rasakan bumi seperti dibalikkan. Sebagaimana bumi yang pernah dihuni oleh umatnya Luth, juga dibalikkan oleh Tuhan. Hanya apa yang kami terima kini, layaknya kami berada dalam dua peristiwa besar semasa Luth dan Nuh.
“Jangan sampai Allah menimpakan cobaan seperti kepada kaum Luth dan Nuh. Tak bisa kita bayangkan…” kata Ibu semacam berharap, usai ia mengisahkan cerita tentang musibah pada kaum Nuh dan Luth. Lalu, kami—anak-anaknya waktu itu masih kanak-kanak—mengaminkan. “Tetapi, Allah akan selalu memberi peringatan dan cobaan pada manusia, demi menguji keimanan kita. Bukankah Tuhan telah berfirman bahwa setiap orang yang mengaku beriman pasti diberikan cobaan. Oleh karena itu, janganlah kalian berprasangka buruk pada Allah kalau cobaan yang datang itu sangat berat diterima. Sebab yakinlah di balik itu ada hikmah…”
Entah mengapa (pasti waktu itu pikiran kanak-kanak kami tak akan sampai), kami mengangguk tanda setuju pada ucapan Ibu. Sesungguhnya, kami selalu membenarkan apa yang dikatakan Ibu. Ucapan apa pun yang keluar dari bibir Ibu, pada waktu kanak-kanak dulu, kami terima sebagai kebenaran. Apalagi Ibu, di mata anak-anaknya, adalah orang saleh. Itu sebabnya, kami seperti membenarkan kata-kata Ibu, “Kalau Allah tak lagi menghendaki suatu kaum dan ingin menggantinya dengan umat yang baru, tidak sulit bagi-Nya menimpakan musibah sebagaimana terjadi pada kaum Nuh dan Luth dan umat nabi-nabi lainnya.”
Namun, adakah Tuhan hendak mengganti kaum yang baru ketika bah itu menghantam
Ibu entah terseret ke mana bersama perahu sajadahnya. Aku pun tak ingat lagi tadi di mana aku terdampar. Hanya ratusan ribu orang kini kaku: “hampir di setiap sudut tanah
SUNGGUH! Ibu yang berperahu sajadah tak henti melaju. Membelah gelombang, menggunting penghalang. Meski tanpa angin, kain layar ibu tetap melambai. Bagai layang-layang. Hanya, begitu jauh. Semakin jauh dan amat jauh. Aku tak dapat menangkap Ibu, dan ia tak kuasa mendekap tubuhku. Kami pun berpisah tersebab air bah maha dahysat ini. Karena takdir pula. Sebab ketentuan-Nya. Oleh kun fayakun-Nya. Barangkali kami akan berjumpa di suatu tempat pada suatu masa. Bila. Ya!
(teringat oleh email Asmanadia yang mengabarkan bahwa penulis dan anggota FLP Banda Aceh Diana Roswita yang meninggal akibat musibah gempa dan tusnami di Aceh 26 Desember 2004 sambil mendekap satu anak kembarnya. Karena email ini, menginspirasi lahirnya cerita ini).
Posko Lampung Ikhlas, Januari 2005
4. Perempuan yang Berenang saat Bah
ENTAH dari mana ia tahu kalau aku berada di
“Nta selamat. Juga anak kembarku,” lanjutnya dengan tetap menyebut dirinya Nta sebagai sapaan dari namanya. “Meski si kembar masih harus dirawat. Ia banyak meminum air…”
“Suamimu?” segera kutanya nasib suaminya, Teuku Nurgani, orang Aceh. Dan karena Nurgani, dia dibawa ke
“Abang tak bisa diselematkan. Ia digulung gelombang besar, dan sampai kini Nta belum menemukannya. Tapi Nta yakin, abang sudah meninggal…” jelasnya beberapa kejap kemudian. Terdengar isaknya.
“Lalu, kau di mana sekarang?” secepatnya kutanyakan posisinya. Aku tak lagi berpikir apalagi bertanya dari mana ia dapat informasi kalau aku ada di Banda Aceh. Bahkan aku juga tak menceritakan mengapa dan untuk urusan apa aku datang ke
Ia menyebut suatu tempat di sekitaran Bandara Blang Bintang. Tak kutanya apakah ia di penampungan para pengungsi ataukah di suatu rumah. Sebab kemudian ia menceritakan detik-detik ia melawan maut. Katanya, ketika semburan gelombang berkekuatan dahsyat, ia berlari kencang menghindar kejaran air. Si kembar didekapnya erat-erat. “Nta tak mau melepaskan salah satu si kembar. Dalam pikiran Nta lebih baik mati bersama, atau kami selamat bertiga,” katanya.
Shinta bercerita bahwa saat itu yang terpikir hanyalah tempat berlindung. Tetapi, sampai lebih 50 meter ia berlari tak satu pun tempat yang dianggapnya dapat menyelematkannya. Ia terus lari. Sekencangnya. Kedua anaknya—Ranti dan Santi—terguncang-guncang dalam dekapan tangannya. Ia kalah dengan kekuatan lari air. Shinta, demikian ceritanya, sempat tergulung dan berenang dalam air bah sampai ia tertolong tembok yang ternyata adalah dinding sebuah Masjid.
Shinta berkata, “Nta naiki tembok masjid itu. Tak berpikir apa-apa, selain ingin selamat. Ingin selamat. Nta memohon diselamatkan Tuhan. Ketika air mulai surut, Nta langsung sujud syukur…”
“Suamimu di mana saat itu?”
“Abang sedang jalan pagi…” lalu suaranya tersekat. Isaknya kembali kudengar. “Nta tak punya siapa-siapa lagi di sini. Nta takut…” ujarnya lagi.
AH! Shinta Larasati. Nama itu kembali akrab di benakku. Padahal sejak Teuku Nurgani menikahinya tiga tahun silam, aku sudah melupakannya. Namanya sudah kuhapus dari memoriku, bahkan seluruh nomor telepon dan alamatnya sudah kubuang dari notesku. Aku tak ingin mengganggu kebahagiaannya. Tak hendak mengusik kehangatan rumah tangganya. Betapa pun ia pernah singgah—bahkan sulit terpisahkan, dari hatiku. Tuhan telah menentukan lain. Cuma tiga bulan perkenalannya dengan
Aku sempat putus asa ketika ia mengutarakan hendak menikah. Tetapi, aku tak dapat berbuat apa-apa. Tersebab waktu itu aku memang belum mau berumah tangga. Padahal ia sangat menunggu aku melamarnya. “Nta tak mau persahabatan kita dinodai. Segeralah melamarku, Sat!”
“Dengan apa aku melamarmu, Shinta? Modalku belum ada untuk membawamu…” kataku. Meski aku berjanji tetap akan menikahinya. “Aku juga ingin kau menjadi ibu dari anak-anakku…” 1)
“Tapi, kapan?” sergahnya. “Lagi pula Nta tak menginginkan macam-macam, cukuplah cinta sebagai modalmu…” imbuhnya.
Ah. Aku serbasalah. Hidup berumah tangga tak hanya cukup dengan cinta. Terlalu sering kusaksikan rumah tangga akhirnya hancur hanya karena bermodal cinta. Tetapi dan tetapi, betapa banyak kehidupan rumah tangga menjadi langgeng meskipun membangunnya tidak dengan cinta.
“Rumah tangga tak semata dijaga dengan cinta. Ingatlah itu Shinta. Dan aku tak ingin menelentarkanmu karena aku belum punya modal,” ujarku meyakinkan. Ia memang terbawa oleh emosi. Ia gamang ketika banyak temannya sudah berkeluarga. Selain itu, sebagai anak sulung maka kedua orang tuanya seakan menumpukan harapan padanya. Itu sebabnya, aku relakan ia ketika Nurgani melamarnya.
“Kalau begitu maafkan Nta kalau menerima lamaran abang Nurgani…”
“Kurelakan kau menikah. Semoga kau bahagia, selalu dicintai, berharta, dan dikaruniai anak yang baik…” kataku kemudian seraya membelai rambutnya. Waktu itu kurasakan kafe tempat kami bertemu menjadi temaram dan tak bersahabat. Kukuatkan hatiku untuk melepasnya, meninggalkan kursi kafe.
Sejak itu aku tak lagi menghubunginya. Aku juga tak datang sewaktu resepsi pernikahannya. Tak sedap membiarkan hatiku yang luka semakin koyak. Undangan dari Shinta kubiarkan tergantung di dinding kamarku, bahkan hingga kini masih ada di
Dan, kalau sampai hari ini aku belum berkeluarga bukan lantaran aku frustrasi. Aku juga tak bersemangat berteman khusus dengan lain perempuan. Meski banyak perempuan di kantorku yang menggoda. Aku tetap dingin dan hatiku sekeras batu sehingga tak seorang perempuan pun yang dapat memecahkannya. Daniel kerap mencoba untuk mencairkan kebekuan hatiku, namun selalu gagal.
“Aku lebih suka menyendiri. Tidak disibuki oleh urusan seperti itu…” kataku.
“Tapi kau juga harus realistis, Sat! Usiamu terus bertambah. Apa kau menginginkan perempuan seperti Shinta, mana mungkin kaudapatkan dua orang yang sama persis!” tandas Daniel.
“Aku tak mencari perempuan yang persis Shinta, aku hanya malas mencari teman perempuan…”
“Kau frustrasi ya Sat? Kau kecewa pada perempuan, karena Shinta tidak menikah denganmu?” ketus Daniel.
“Aku tidak kecewa, tak juga frustrasi. Kalau aku mau, Shinta bersedia jadi istriku. Hanya aku belum mau berumah tangga. Aku belum punya modal yang cukup untuk membangun keluarga,” jelasku. Aku tersinggung ketika ia mengira kalau aku memilih hidup seperti ini karena Shinta tidak menikah denganku. Padahal Shinta menikah dnegan Teuku Nurgani lantaran aku belum siap melamarnya waktu itu.
“Sekarang modalmu sudah cukup, bukan? Kenapa tidak mencari perempuan lain? Di kantor ini saja kukira banyak yang bisa kaujadikan istrimu, kalau saja kau benar-benar tidak frustrasi pada perempuan…” timpal Daniel.
Tak tergoda. Aku tetap sendiri. Kujadikan teman-teman perempuan di kantorku hanya mitra kerjaku. Pada waktu yang lain kutempatkan mereka sebagai kawan diskusi, ataupun lawan saing demi menyemangati pekerjaan. Awalnya Daniel mengira hatiku mulai mencair, dan suatu saat nanti akan memilih salah satu para perempuan di kantorku. Perkiraannya meleset. Sampai aku dipromosikan jabatan yang bagus dan pindah ke
“Lo, kau tak bawa salah satu dari mereka?” Daniel menggoda.
“Kau pikir mereka barang apa? Mau kumasukkan di kardus mana ha?!” jawabku antara serius dan bergurau. Kataku kemudian, “tapi kalau kau berkenan meringankan aku, boleh kaugendong salah satu dan serahkan padaku di Jk. Bagaimana, setuju?”
“Gila apa aku? Kau pikir aku bujangan sepertimu? Apa kata istriku nanti kalau ia tahu aku menggendong perempuan lain? Alamat perang dunia ketiga terjadi di rumahku!” ucap Daniel yang disambung terbahak.
Aku mengemasi barang-barang yang ada di ruang kerjaku, lalu memasukkan ke dalam kotak-kotak kardus yang telah disiapkan. Setelah itu kunaiki ke mobil. Tak banyak cakap. Aku juga jarang menyambut godaan Daniel, terutama soal perempuan. Bahkan ketika ia memberiku setangkup roti yang katanya dari Endah, tanpa kusahut langsung kumasukkan ke dalam mulut. “Ternyata kau hanya lapar makanan, bukan perempuan,” Daniel berbisik.
Setelah itu aku pamit. Pada Daniel, sahabatku yang sangat dekat di kantorku, juga seluruh karyawan lainnya. Tak ada tangis. Tak perlu mengumbar kesedihan…
AKU pikir tak perlu bersedih dalam hidup ini. Meski aku tetap punya rasa haru, begitu menyaksikan orang bersedih. Maka itu, ketika kusaksikan berita gempa dan stunami menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan Aceh, segera kuputuskan ke
Itulah mengapa sore tadi aku sudah tiba di
Pagi ini seharusnya aku bergabung dengan para relawan yang lain, kalau saja Shinta Larasati tidak meneleponku subuh tadi. Ia berharap sekali aku menemuinya di sekitaran Blang Bintang. Tetapi, aku lupa menanyakan di mana ia menetap. Di penampungan pengungsi ataukah menetap di rumah warga?
Aku berjanji menemuinya agak siang. Sebab pagi ini aku harus ke tenda pengungsian dekatku menginap untuk menolong anak-anak yang terserang diare. Shinta merajuk. Ia berharap menemuinya lebih dulu. Akhirnya aku ke Blang Bintang menumpang mobil Palang Merah
Aku tersenyum. Menatap wajah masai itu. Kedua matanya sembab. Barangkali karena kebanyakan menangis. Aku berkata kemudian, “Sudahlah, sedihnya jangan berlarut-larut. Ikhlaskan yang telah pergi. Suamimu mati syahid, pasti dia telah menantimu di surga…”
Shinta kembali terisak. Lalu ucapku lagi, “Aku sudah datang
Lalu kubuka tasku. Kuambil obat dan kuserahkan padanya. Kuperiksa tubuh Ranti dan Santi. “Kau tak apa-apa
Ia menggeleng. “Nta sehat. Hanya…”
“Jangan berpikir macam-macam, malah nanti kesehatanmu terganggu. Tenanglah. Yang perlu kauperhatikan kesehatan kedua anakmu…” aku menasihatinya. Ketika ingin pamit, Shinta seperti keberatan kutinggalkan.
“Aku harus menolong yang lain. Kedatanganku ke sini untuk memberi pertolongan, bukan…”
“Ya Nta maklum. Nta memang tak perlu ditolong. Terima kasih, Sat…”
“Bukan itu maksudku, Shinta. Sebagai dokter aku harus menolong orang lain juga. Masih banyak korban yang menderita dan membutuhkan perawatanku. Maafkan aku. Dan sore nanti, setelah tugasku selesai, aku pasti ke sini lagi. Menemuimu. Menemani Ranti dan Santi…” janjiku. Segera kutinggalkan Shinta yang memandangku tak berkedip.
“Nta mengerti. Kalau banyak tugas, kau tak kemari pun tak apa-apa. Nta bisa mengurus sendiri…”
“Aduh Shinta… kau marah ya?” kataku.
Ia menggeleng. “Oke aku akan kemari sore nanti!” lalu kutinggalkan Shinta Larasati bersama kedua anaknya. Di sebuah rumah yang kini disulap menjadi rumah sakit sementara. Aku tak mengharapkan reaksinya.
SORE ini kutepati janji. Mengunjungi Shinta. Memeriksa keadaan si kembar dan memberinya obat. Ia menerimaku riang. Wajahnya benderang. Seperti ada bintang di paras yang manis itu. Keadaan Ranti dan Santi mulai membaik. Sejak itu aku sering menemuinya setiap sore atau malam.
“Nta mau pergi dari sini. Di sini Nta sudah tak punya famili lagi,” katanya setelah tiga hari pertemuan kami. “Nta tidak sanggup menetap lama di sini, traumatik. Setiap mendengar suara, seperti suara gemuruh air…”
“Ke mana?”
“Ke rumah Tante Alin di Jakarta. Semalam Nta nelepon, dan tante akan menjemput Nta…”
“Bagaimana kalau ke rumahku?”
Entah kekuatan apa yang membuat kata-kata itu meluncur dari bibirku. Entah mengapa aku begitu lancang (atau malah itu wajar?) mengajaknya ke rumahku, padahal ia belumlah menjadi istriku? Mungkin itu sebagai tanda, cinta kami yang tertunda akan berpaut kembali? Entahlah…
Aku cemas. Tertunduk. Aku seperti tengah menanti ia mendampratku karena ucapanku barusan. Menyesal. Aku sudah berbuat kurang ajar pada Shinta, perempuan yang sejak dulu sangat kuhormati. Segera ingin kuralat, meminta maaf kalau aku lancang dan bukan karena sengaja. Namun belum lagi ucapanku keluar, Shinta mendahului dengan ujaran: “Kalau Abang menikahi Nta, bolehlah …”
17 Januari—4 Februari 2005
5. Sarmi Hamil
SARMI hamil. Tak lama lagi bakal melahirkan. Aneh? Kalau saja Sarmi bukan perempuan bisu dan idiot—artinya perempuan normal, tentu kehamilannya dianggap wajar. Paling-paling ia dituduh hamil karena pergaulan bebas. Sedang Sarmi?
Karena itu, ketika tahu bahwa Sarmi hamil maka meruap tanda tanya besar. Keanehan timbul manakala diketahui perempuan bisu dan idiot itu hamil, dan sialnya tak seorang pun lelaki di kampung kami yang mengacungkan telunjuknya sebagai penyebab kehamilan Sarmi.
Lalu siapa yang menggagahi Sarmi? Lelaki mana yang tergiur lalu tega menanamkan benihnya ke rahim perempuan bisu dan idiot itu? Barangkalikah setan dari pohon beringin di tepi sungai? Adakah makhluk halus yang menetap di pohon randu di ujung kampung? Soalnya di dua tempat yang dianggap “keramat dan angker” oleh warga kampung kami, Sarmi sering duduk berlama-lama? Saf pertanyaan sejenis itu akan makin bertambah. Namun jawabnya akan selalu bermuara pada ketidaktahuan: pekat laksana malam yang tidak memberi terang.
Di kampung kami, semua orang tahu Sarmi adalah perempuan bisu dan idiot. Sejak dari anak-anak sampai bandot—dan juga Lurah—tahu pada anak sulung Mbah Tarno tersebut. Hanya sampai seusianya kini, kami tahu kalah ia tak pernah sekalipun mengobrol dengan lelaki, apalagi dibawa jalan-jalan. Meskipun sesungguhnya kami mengakui kalau ia lumayan cantik. Kalau saja Sarmi perempuan normal, tentulah sekarang sudah memiliki kekasih.
Oleh sebab itu, ketika Mbah Tarno mengabarkan kalau anak perempuannya hamil, kampung kami gempar. Berita itu cepat sekali menyebar. Setiap yang mendengar akan tersentak, aneh, dan bahkan menganggap mustahil. “Sarmi hamil?” pertanyaan bernada aneh seperti itu lebih sering kami dengar. Atau yang berkomentar, “Ah mana mungkin? Sarmi pacaran pun tak pernah kulihat!”
Kami selalu menunggu dengan hareapa ada lelaki, terutama dari kampung kami, yang mengaku telah menghamili Sarmi. Atau setidaknya, berani jujur mengatakan bahwa Sarmi benar kekasihnya. Meski, boleh jadi, bukan dia yang berbuat. Setidaknya dengan pengakuan seperti itu, kami dapat menelusuri pelaku sehingga Sarmi mengandung. Sayangnya tak seorang pun yang berterus terang. Sehingga kami belum tahu siapa lelaki yang menghamili, atau yang menjadi pacar Sarmi. Apalagi kami tidak tahu apakah selama ini Sarmi sudah punya kekasih ataukah tidak, apakah dengan cara diam-diam ia kerap dibawa lelaki. Tak seorang pun pernah melihatnya. Karena selama ini kami kurang peduli padanya.
Sarmi memang seperti tak pernah dihitung di kampung kami. Selama ini, ia ada ataukah tidak seakan tak memberi apa-apa: ada tak menggenapkan, hilang pun tak akan mengurangi. Sarmi layaknya mentimun bengkok di dalam timbangan. Ketika Mbah Tarno mengurung Sarmi berhari-hari di bekas kandang kambing karena dianggap memalukan keluarga, kami tak peduli. Tak merasa kehilangan atau sekadar bertanya: “Ke mana Sarmi ya, kok beberapa hari ini tak melihatnya?”
Setiap pagi Sarmi acap duduk di atas batu pinggir sungai menontoni orang kampung yang mencuci pakaian atau mandi. Dia sendiri tidak mencuci atau ikut mandi bersama-sama. Duduk berjam-jam sampai tempat itu kembali sepi. Hanya memainkan air dengan kedua kakinya atau tangannya. Sesekali tersenyum, tapi lebih banyak diam. Sementara di waktu petang, ia biasa jalan mengeliling kampung dengan dandanan rapi, berpupur, dan lipstik. Lalu ia berhenti di bawah pohon randu itu.
Kini Sarmi menjadi buah percakapan di kampung kami. Tepatnya, sejak adanya perubahan di perutnya. Untuk sementara kami menengarai dia hamil. Lebih tepatnya, ada lelaki yang menghamilinya. Pembicaraan akan bertumpu dan senantiasa memuara: siapa pemilik janin dalam perut Sarmi? Benarkah perempuan bisu dan idiot itu punya cinta, ingin dicinta, dan punya berahi? Lagi kami tak menemukan jawaban. Berhenti sebagai pertanyaan dan pertanyaan.
Setiap ditanya siapa ayah dari calon janin di perutnya, Sarmi hanya menggeleng dan menggeleng sambil tangannya bergerak sebagai isyarat. Jangan kami, Mbah Tarno pun tak mampu menerjemahkan isyarat Sarmi. Akhirnya untuk sementara kami berkesimpulan bahwa sarmi dihamili genderuwo, setan dari tepi sungai atau dari pohon randu. Kesimpulan di luar nalar sehat itu, ditentang sebagian orang tua.
Kata Wak Markon, wakil dari orang tua, “Setan gundulmu yang bisa menghamili perawan! Kalian ada-ada saja, justru kesimpulan itu tak masuk alak!”
“Lalu Wak, siapa yang buntingi Sarmi? Sergah Amran, ketua RT 03 di kampung kami.
“Embuh!” jawab Wak Markon ketus. “Ya mestinya kita sama-sama cari tahu siapa penyebab kehamilan Sarmi. Kasihan…”
“Benar Wak…” timpal yang lain.
“Apa?!” sela Wak Markon mendelikkan mata.
“Sarmi. Kasihan. Hamil. Tapi dia snediri tak mau memberi tahu siapa lelaki yang telah membuatnya begitu. Tega-teganya…”
“Sarmi pasti tahu!” potong Abah Komar, salah seorang tetua di kampun kami. “Hanya ia tak bisa menyebut, tak dapat memberi tahu siapa lelaki itu. Karena dia bisu dan terbelakang, sementara kita tak bisa menerjemahkan isyaratnya. Bisa jadi Sarmi sangat kenal dan dekat dengan lelaki itu.”
“Tapi, kalau Sarmi dipaksa? Maksud saya, diperkosa misalnya, tentu wajahnya ditutup jadi tak bisa melihat dengan pasti siapa yang melakukannya. Coba bagaimana Abah…” Amran menawarkan kemungkinan.
“Boleh jadi. Kemungkinan itu bisa saja terjadi,” ujar Wak Markon sambil mengangguk-angguk. “Hanya kalau benar dia diperkosa, seharusnya dia bersedih. Tetapi malah ia tampah riang.”
Pak RT 03 menimpali, “Orang seperti Sarmi tak akan pernah tahu apa itu riang atau sedih. Akalnya tidak berfungsi dengan baik, dia juga bisu…”
“Urusan perasaan setiap orang punya. Orang yang tak waras saja atau gila, masih memiliki perasaan. Dia bisa mengaduh kalau disakiti. Apalagi sarmi…” warga lainnya mendukung.
Debat berlanjut. Bukan lagi membicarakan demi mencari tahu siapa lelaki yang menghamili Sarmi. Atau kalimat di balik itu, mengapa Sarmi bisa hamil dan kenapa dia mau disetubuhi oleh lelaki yang tak bertanggung jawab? Bukankah ia dapat saja menolak kalau dia tak mau ketika akan disetubuhi, misalnya dengan cara berteriak minta tolong. Itu jika Sarmi—seperti kata Wak Markon punya perasaan, maka dengan demikian ia bisa menampik kalau ia tak suka atau tak mencintai lelaki yang mencumbuinya.
*
BERKALI-KALI Sarmi dihadirkan saat rapat resmi di rumah RT 03 atau pertemuan keluarga besar di rumah Mbah Tarno. Tak kurang para orang tua turut melempar pertanyaan pada Sarmi soal siapa sesungguhnya kekasih Sarmi sekalgus yang telah menghamilinya. Dan seperti yang sudah-sudah, selalu saja Sarmi mengibaskan kedua tangannya. Mulutnya dimonyong-monyongkan. Sehingga tak seorang pun yang hadir dapat menafsirkan gerakan itu. Buntu. Tak juga Mbah Tarno, orang tua kandung Sarmi, sehingga membuanya berang dan nyaris tangannya yang melayang kalau tak segera dihalangi Abah Komar dan Wak Markon.
“Anak ini harus mati. Sejak kecil memang selalu menyusahkan!” teriak Mbah Tarno. Terduduk. Menutup wajahnya.
Sarmi diam. Sesekali tersenyum sambil mengelus perutnya yang buncit. Ia seperti sangat mengasihi janin yang ada di rahimnya. Layaknya seorang ibu yang sedang mencurahkan kasih sayang pada anaknya.
*
SARMI tetap menjadi buah pembicaraan. Setiap hari, warga di kampung kami mencakapkan Sarmi yang hamil. Dari anak-anak, para ibu, sampai para bandot—juga Lurah—turut membincangkan perempuan bisa dan idiot itu. Sampai sejauh ini, belum juga terjawab siapa lelaki yang telah menghamili Sarmi. Adakah lelaki itu dari kampung kami ini, ataukah lelaki lain kampung? Kami juga sempat menduga-duga, boleh jadi yang menghamili Sarmi justru di antara kami sendiri yang mengikuti berbagai rapat dan seolah-olah prihatin pada nasib Sarmi, hanya untuk menyembunyikan kebejatannya.
Wak Markon pernah membisiku pada pertemuan besar di rumah RT, bahwa ia mencurigai Abah Komar yang menghamili Sarmi. Cuma dia tak memiliki bukti akurat untuk menyeret Abah Komar. Lagi pula isu itu ia peroleh dari seorang tetangga yang pernah melihat Abah Komar memberi sepotong roti kepada Sarmi. Waktu itu sore hari menjelang senja, demikian sumber itu bercerita. Sarmi duduk di dekat pohon randu. Kemudian Abah Komar mendekati, tersenyum pada Sarmi, dan memberi sepotong roti. Sarmi menerima pemberian Abah Komar dengan riang sekali. Memakannya hingga tandas. Abah Komar kemudian membelai rambut Sarmi, sebelum perempuan bisu dan idiot itu beranjak dari tempat. Pakaian Sarmi kusut, bedaknya sudah luntur, lipstiknya tiada lagi.
“Cuma Sarmi yang tahu lelaki itu!” keluh Wak Markon saat kami rapat di rumah RT. “Sayangnya, dia bisu dan idiot…” sambunya kemudian. Seperti mewakili semua orang yang putus asa.
“Ya. Sudah pasti!” Abah Komar memperkuat.
Pada hari berikutnya, aku menampung isu yang lain.
Segala isu itu kutampung. Meski sampai kapan pun tidak akan kutebarkan kepada lain orang. Biarlah segala isi itu membusuk dan pecah di dalam perutku, daripada pecah dari mulut. Aku tak hendak menambah keruwetan persoalan yang memang sudah sangat kusut ini. Karena itu aku diam saja meski sama artinya aku membiarkan orang berbuat syirik, ketika ada usul untuk mendatangkan orang pintar ke rumah Mbah Tarno. Kehadiran orang pintar itu dengan harapan bisa tahu siapa lelaki yang telah menghamili dan menjadi ayah dari jabang bayi yang dikandung Sarmi. Tetapi bukan menjadi terang, malah membuat kami semakin menduga-duga. Mencurigai setiap orang yang dicirikan orang pintar itu.
Menurut Mbah Brajamukti, orang pintar itu, lelaki yang menghamili Sarmi berpostur tegap, rambut pendek, ada kumis tipis di atas bibir, tidak berjambang tapi berbulu jarang di tempat jambang. Selain itu kesukaannya meludah di sembarang tempat, tidak pernah bergaul dengan tetangga karena sangat penduiam, kulitnya agak keputih-hitaman, matanya agak belok dan kalau melihat orang tatapannya tajam—tepatnya nyalang.
Tentu saja ciri-ciri yang dibeberkan Mbah Brajamukti membuat kami, warga kampung ini, bertambah pusing. Sebabnya, tak ada lelaki di kampung ini yang masuk dalam kriteria yang dicirikan Mbah Braja secara pasti. Kalau ciri-ciri yang diutarakan Mbah Braja untuk seorang, bagaimana mungkin? Namun demikian, kami juga tidak percaya kalau kehamilan Sarmi tanpa sebab. Artinya, ia bukanlah seperti Bunda Mariam yang mengandung tanpa disentuh lelaki. Sarni beda dengan perempuan suci itu yang mengandung dan melahirkan lelaki kudus.
Sementara itu usia kehamilan Sarmi terus bertambah. Makin mendekati waktu melahirkan. Sedangkan lelaki bakal menjadi ayah dari bayi yang dilahirkan Sarmi, belum juga ketahuan atau diketahui. Siapa pun lelaki itu yang dengan jantan mengaku telah menghamili Sarmi, sungguh kami sudah menhyiapkan penghargaan istimewa: sebuah rumah sudah lengkap dengan isinya. Nah, siapa dari Anda, mau mengakuinya?
Meski pada sisi lain, kami sangat ingin Sarmi tidak sedang mengandung bayi. Kami berharap, anak perempuan Mbah Tarno yang bisu dan idiot itu cuma busung lapar. Apalagi sampai kini kami lupa membawanya ke bidan ataupun dokter kandungan. Sebagai orang kampung, kami memang abai. Benar-benar tidak terpikirkan.
Februari 2005
6. Lelaki Asing di Gedung Pertunjukan
AKU tak bisa lagi menandainya. Begitu sulit mengenalnya. Layaknya aku berhadapan dengan orang yang masih asing. Seperti seseorang yang tidak kukenal sebelumnya. Tetapi, sejak tadi ia tersenyum padaku.
Ah! Aku mendesah. Dengan begitu, aku berharap dapat mengembalikan ingatanku: setidaknya bisa mengenali siapa lelaki yang sejak tadi memandangiku. Meski di dalam gedung pertunjukan ini gelap, tapi aku bisa memastikan kalau ia tersenyum padaku. Giginya putih. Matanya bergerak, tangannya memberi isyarat.
Siapa ya? Aku bertanya-tanya. Wajahnya amat buruk. Hidungnya melesek ke dalam, begitu pula keningnya: berceruk. Ia lebih sering memandang ke arahku ketimbang ke panggung pertunjukan. Sudah lebih setengah jam, musisi muda berbakat itu beraksi dalam resital tunggal penggalangan dana bantuan korban gempa dan tsunami di Aceh. Perempuan cantik itu asyik memetik gitar akustik. Karena lelaki itu, aku tak lagi konsentrasi menikmati permainan resital musik Indah Saraswati.
Khayalku mengembara. Menggali kembali kenangan lampau, terutama para lelaki yang pernah kukenal. Mengingat semua teman-teman lelaki, baik semasa SMA ataupun sewaktu kuliah di jurusan hukum UI. Ah, tak juga kutemu. Lelaki berwajah seperti itu tak pernah singgah dalam benakku. Boleh jadi wajahnya seperti itu karena kecelakaan. Ya, bisa jadi. Tetapi, siapa?
Aku benar-benar sulit menandai. Mengingat-ingat seluruh lelaki yang pernah kukenal. Tetapi, ya tetapi, selalu saja gagal. Pikiranku memuara pada ruang hampa. Amat kusut. Buntu. Ah ya! Lelaki yang duduk di sayap kiri panggung pertunjukan dan aku di sayap kanan dari gedung ini, hanya bisa saling pandang. Baru kali ini konsentrasiku buyar saat menyaksikan pertunjukan seni, hanya karena keberadaan lelaki yang tidak kukenal itu. Lelaki yang sejak pertunjukan belum dimulai sudah mengusikku.
Tidak seperti bisa setiap aku menonton pementasan musik selalu ditemani, kini aku datang sendirian. Aku biasa mengajak Rani, teman sekantorku. Atau Sasmita, seorang penyair yang sangat kukagumi. Pernah juga kugandeng musisi ternama di
Lalu lelaki satu ini, lelaki berwajah buruk yang sejak tadi tersenyum seperti amat mengenalku, siapakah dia? Mungkinkah seniman, tapi seniman bidang apa? Perupakah ia? Koreograferkah ia? Ah! Di kalangan koreografer aku hanya mengenal Boy G. Sakti, Ery Mefri, atau Eko. Aku yakin lelaki itu bukan koreografer yang telah kukenal itu. Dalam dunia senirupa, aku tak begitu banyak mengenal selain Agus Jolly, Hery Dim, Dede Eri Supria, dan Syahnagra. Sampai detik ini aku belum mengenal pasti lelaki itu.
Daripada pikiranku kacau, kubuang jauh ingatan untuk mengenal lelaki yang berada di sayap kiri panggung pertunjukan—dan berhadapan denganku. Kubuang pandanganku ke panggung, menikmati permainan akustik Indah Saraswati. Musisi manis berkacamata minus berbentuk segi empat. Rambutnya sebahu. Tubuhnya sedikit kurus.
Indah tengah memainkan beberapa nomor musik dari puisi-puisi para penyair ternama. Salah satunya karya Sasmita, sebuah puisi paling kusukai dan pernah dimuat di sebuah majalah seni ternama di negeri ini. “Itu puisi terbaikmu yang pernah kubaca. Paling kusuka!” komentarku ketika kami berjumpa di kantin Pusat Kesenian ini. Sasmita hanya menjawab, “Trims.”
AKU menyesal tadi tak mengontak Dwiki. Kalau kini ia bersamaku, setidaknya dapat membantuku mengingat siapa lelaki itu. Dwiki tak kukontak dan menemaniku nonton, karena aku tak hendak merepotkannya. Ia sedang mempersiapkan konsernya di beberapa negara di Eropa. Akhirnya beginilah. Tak ada yang menolongku untuk mengingatkan siapa lelaki berwajah buruk itu.
Kini aku hanya menanti keajaiban. Mengharapkan ada kekuatan lain yang dapat menolong kenanganku untuk mengenal kembali lelaki yang masih memandang ke arahku. Benar-benar aku dibuat penasaran. Jika tak juga kuingat lelaki itu, aku berjanji akan menemuinya seusai pertunjukan resital musik Indah Saraswati. Di lobi gedung kesneian nanti. Akan kutanya siapa dia, “Maaf siapa ya Anda? Saya sudah lupa, mungkin karena Anda sudah berubah sekarang?” begitulah pertama kali yang akan kuucapkan padanya begitu kami bertemu. Nanti, usai pertunjukan resital musik ini, di lobi gedung kesenian ini.
Bisa jadi ia akan menjawab, “Tentu Anda tak mengenal saya lagi. Saya memang sudah berubah sekarang. Lihatlah wajah saya…” Atau, malah dia akan berbicara begini: “Orang seperti saya memang tak penting diingat. Saya
Bagaimana kalau ia memang lelaki yang pernah kukenal, di suatu tempat dalam suatu kesempatan? Hanya karena dia berwajah buruk, aku tak begitu pedulu lagi setelah perkenalan? “Sus
Tentu aku akan malu jika ia berkata begitu. Ia akan menganggapku perempuan yang hanya melihat seseorang dari penampilan jasmani. Sungguh tak kuharapkan seperti itu. Dalam pergaulan, aku tak pernah melihat seseorang dari penampilan semata. Aku punya teman dan amat bersahabat dengan lelaki yang menggunakan kursi roda karena lumpuh. Dia seorang cerpenis ternama. Aku juga punya teman dekat, seorang lelaki, tak berprestasi apa-apa. Tetapi karena ia selalu menampakkan optimistis dalam hidupnya, aku pun mengaguminya. Lalu tak benar kalau aku tak memedulikan dia, lelaki berwajah buruk yang sejak tadi mengusikku.
Meski aku lulusan Fakultas Hukum, tetapi aku banyak mengenal dan dekat dengan para seniman ternama. Soalnya, sejak kecil aku memang menyukai karya-karya seni: senirupa, tari, musik, teater, dan karya sastra. Karena aku banyak belajar dari karya seni untuk kehidupanku. Hukum dan seni, demikian seorang pengacara ternama di Tanah Air ini penar berujar, memiliki keseimbangan yang patut dijaga jika kehidupan ingin harmonis. “Hukum cenderung dapat dikorup, dikangkangi. Maka seni yang akan mengingatkannya, menyeimbangkannya…” kata pengacara kesohor itu dalam sebuah tulisannya. Karena itulah, sebagai pengacara pula, aku menyukai karya seni.
Kho Ping Ho juga memengaruhi jiwaku. Ia pernah berujar dalam sebuah bukunya, “Orang yang bisa hidup harmonis jika dapat mengawinkan ilmu bela diri dengan seni. Seni tanpa bela diri akan lemah dan dizalimi, sementara belada diri tanpa punya rasa seni akan menjadi zalim.”
Ah ya! Lelaki itu masih menatapku. Tersenyum. Gigi-giginya yang putih jelas. Tetapi, resital musik Indah Saraswati masih 45 menit lagi akan berakhir. Aku gelisah menunggu berakhirnya konser resital penggalangan dana ini. Tak bisa menikmati. Aku kehilangan konsentrasi. Kekhusyukan. Sebagai apresian, penikmat karya seni, sungguh kali ini aku benar-benar gagal. Menyesal.
Tanganku merogoh tas. Meraba-raba sesuatu. Dapat. Kukeluarkan. Tapi, di dalam gedung kesenian ini steril dari asap rokok. Akhirnya kumasukkan lagi ke dalam tas. Kuambil permen. Kukenyut pelan-pelan. Kuhikmati setiap rasa dari permen yang ada di mulutku.
Ketika resital musik selesai, segera aku keluar dan menunggu di lobi. Aku ingin lebih cepat berada di
Hanya tinggal beberapa orang lagi di lobi, tapi aku belum juga bertemu lelaki itu. Seorang petugas siap mematikan lampu lobi. Harapanku pupus untuk menemuinya. Mungkinkah ia sudah lebih dulu keluar dari gedung ini lalu pulang, sebelum aku tiba di lobi? Ah, tidak mungkin rasanya. Aku lebih dulu beranjak dari kursi dan langsung menuju lobi. Akhirnya aku keluar dari lobi dengan gontai. Semangatku tiba-tiba hilang. Aku menuju kafe dan siapa tahu ia masih di
Semalaman aku tak bisa tidur. Mengingat lelaki berhidung melesek dan kening ceruk ke dalam. Ia sepanjang pertunjukan resital musik penggalangan dana bagi korban Aceh dan Sumuatera Utara selalu tersenyum padaku. Seperti mengenalku. Seperti aku mengenal dia. Padahal, sampai dini hari ini aku belum menemukan siapa dia. Aneh bukan?
Kukira wajar, tak harus dianggap aneh, jika suatu ketika kita terserang penyakit lupa. Seperti aku sekarang. Aku benar-benar lupa pada lelaki itu. Ataukah aku memang belum pernah jumpa sebelum ini?
Tetapi ada pengalaman pula, seseorang mengaku pernah bertemu dengan si Pulan bahkan tahu namanya, pekerjaannya, dan seterusnya. Padahal si Pulan merasa tidak kenal karena memang ia belum pernah berkenalan sebelumnya. Tetapi, karena ingin menghormati orang lain, si Pulan akhirnya mengaku kenal. “Maafkan keterlupaan saya. Maklum sudah tua…” kata si Pulan akhirnya.
Kalau pun sekarang, kalau benar kami pernah berkenalan atau pun jumpa walau sekejap, aku benar-benar tidak mengenal lelaki itu adalah wajar bukan? Aku bukanlah orang yang gampang sekali lupa. Aku dikenal orang yang memiliki ingatan sangat kuat. Jadi kalau aku pernah berkenalan dengan lelaki itu, bagaimana bisa sekarang aku justru amat lupa? Ia benar-benar asing…
SEPANJANG bulan-bulan ini, semenjak pasca-gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, banjir kegiatan kesenian bernama peduli di mana-mana. Setelah resital musik Indah Saraswati, keesokannya aku menonton pembacaan puisi peluncuran buku puisi 160 penyair Indonesia, dua hari kemudian pelelangan karya lukis para perupa ternama di Balai Keratun, kemudian pelelangan buku-buku sastrawan yang pernah di penjara di Pulau Buru, dan malam ini aku menonton kolaborasi dua penyanyi tersohor Indonesia: Aning Katamso dan Opi Andaresta.
Lelaki itu, lelaki berhidung melesek dan kening berceruk, duduk di tempat dulu lagi. Dan aku di sayap kanan dari panggung pertunjukan. Ia menatapku dan tersenyum padaku sejak sebelum pertunjukan dimulai. Aku pindah ke dekat kursi dia, tetapi sayangnya di
“Nanti kita ketemu di lobi ya?” kataku pula dengan menggerakkan bibir dan tanganku.
Ia mengangguk. Tersenyum.
Tetapi, sampai usai resital dan aku sudah menunggu beberapa menit di lobi, seperti beberapa hari lalu tak jua kutemui. Ia kembali menghilang. Tiba-tiba aku disergap kecemasan yang sangat. Bayangan wajah Maradinata Asyikin, penyair Aceh yang pernah kukenal saat acara “Semalam di Aceh: Antara DOM dan GAM” di Balai Keratun Kesenian, timbul dan tenggelam dalam benakku. Aku pernah mendengar bahwa penyair terkemuka asal Aceh itu menjadi korban bencana alam di
Aku disergap pertanyaan yang sulit jawabannya. Sebab setahuku, penyair Aceh itu tampan. Bukan seperti yang kulihat beberapa malam ini di gedung kesenian ini: berhidung melesek dan kening berceruk. Yang pasti lelaki yang asing itu telah mengusikku sebagai halusinasi…
(kenangan duka bagi penyair maskirbi dan nurgani asyik)
Lampung, 07-08 Februari 2005
7. Pintu Vila itu Dibiarkan Terbuka
SETIAP libur perempuan itu selalu ke
“
Susi tersenyum. Mengatupkan kedua matanya. Dalam hati ia mengamini ucapan suaminya. “Ya, semoga perkawinan kita langgeng. Seperti bukit ini yang tetap kokoh meski diterpa angin dan hujan…” Susi menggumam. Kemudian ia peluk Zul dan mengecup pipinya.
Sejak itu setiap libur atau hari-hari yang dianggapnya penat dan membutuhkan santai, Zul mengajaknya ke
Pernah seorang teman Zul dari Jk mau membeli vilanya, sebulan setelah Zul meninggal. Tetapi, Susi menolaknya dengan sopan. Katanya, “Ini peninggalan Bang Zul yang sangat saya cintai. Jadi maaf, tidak akan saya jual…”
Teman Zul itu berusaha memiliki
Susi kerasan menunggui
Harmonisasi antara sinar lampu di dalam
Setiap orang memuji itu, Susi hanya tersenyum. Mengibaskan tangan kirinya, untuk menolak pujian tersebut. “Apalah artinya saya, lukisan Basuki ataupun Van Goh akan lebih indah dan menarik dinikmati…” kata itu selalu terucap dari bibir Susi. “Saya janda kini. Perempuan yang selalu dan akan tetap selalu setia pada suami. Pada Bang Zul. Ia tak akan pernah tergantikan.”
Bahkan kata itu berulang ia ucapkan. Kepada siapa pun. Terutama setiap lelaki yang mencoba mengusik kesepiannya. Karena itu ia lebih suka memilih tinggal di
“Aku tak bisa membagi cinta antara Bang Zul dengan lelaki lain. Maafkan saya. Tetapi, saya menghargai tawaranmu. Terima kasih, Endah…” kata Susi ketika teman sekantornya itu diajaknya singgah ke vilanya.
“Sampai kapan kau tetap tegar hidup sendiri? Apakah kau tak pernah merindukan kasih sayang seorang lelaki?” Endah bertanya. Hati-hati. Menjaga perasaan sahabatnya.
“Mungkin sampai kapan pun. Setiap perempuan pasti merindukan itu, tapi kita juga punya hak untuk menepis kerinduan seperti itu. Dan buktinya aku mampu, setidaknya sampai hari ini.
“Kau jangan menbohongi perasaanmu. Aku tak yakin kau bisa hidup tenteram. Tempat ini hanya pelarian. Benarkah begitu, Sus?”
Mata Susi menatap tajam Endah. Tatapan berang. Ia memang tersinggung dengan ucapan Endah. “Kau jangan menyudutkan aku dengan pertanyaan seperti itu. Aku akan benar-benar marah kalau kau ulangi lagi ucapanmu itu, Endah!”
Maka keduanya terdiam. Bahkan hingga meninggalkan
“Di mana kau mau. Kalau kau tega, di sini pun aku bisa. Aku akan menyetop taksi nanti…” jawab Endah.
“Oke, kuturunkan di sini saja. Aku mau kembali ke
*
TETAPI, benarkah aku mampu sendiri? Tiba-tiba ia disergap pertanyaan yang selama ini selalu ia bunuh. Endah telah menggoyahkan batinnya. Susi menuding Endah, sebab kini ia digayuti perasaan gamang. Ia seperti bimbang setiap keinginannya mendaki bukit itu. Mengubur kesunyian, menggali kembali keriangan di vilanya itu. Setiap kali, ya saban kali, ia pandangi wajah Bang Zul di bingkai foto amat besar itu. Di ruang depan. Menghadap akuarium besar. Di atas vas bunga asparagus. Dan Susi selalu duduk di antaranya. Sesekali mencuri pandang (tepatnya lebih lama menatap foto Bang Zul!), lalu ke akuarium ikan di sebelah kirinya, dan ke vas bunga. Bunga itu pemberian Bang Zul ketika ia berulang tahun. Kemudian ia belikan vas untuk memasukkan buket bunga itu, dan lalu ia letakkan persis di bawah foto Bang Zul.
Pertanyaan seperti itu—tepatnya kegamangan itu—belakangan ini kerap mengusik batinnya. Lebih tepatnya sejak Endah sering datang dengan membawa setangkup nama lelaki: Cal, Jim, atau Sar. “Kau bisa memilih dari ketiga nama yang kusudorkan itu,” bisik Endah.
Kau pikir para lelaki itu dagangan? Ingin rasanya ia menampar perempuan itu. Cuma ia tak mampu mengayunkan tangannya lalu mendaratkan ke pipi Endah. Perempuan itu bukan sekadar sahabat, tapi lebih dari saudara. Susi mengenal Endah bukan hanya karena sekantor, tetapi sejak SMA dulu. Oleh karena itu, Susi hanya tersenyum memandangi sahabatnya itu setiap disodorkan nama-nama lelaki itu. Nama itu lagi.
“Aku jadi sedih padamu, Endah. Sungguh prihatin…” desis Susi.
“Lo kenapa sedih padaku? Mestinya kau yang perlu dikasihani…”
“Alasanmu?”
“Karena kesetiaanmu itu, sehingga kau melupakan kodratmu. Kau tahu Tuhan menciptakan perempuan, karena ada pasangannya. Bernama lelaki,” ujar Endah. “Anehnya, kau menampik kodrat itu…”
“Aku tak menampik. Hanya dalam hidupku cukup sekali bersuami. Hanya sekali berumah tangga dan mencintai. Apakah aku salah?”
Endah menggeleng. “Kau lupa, perempuan tak mungkin bisa hidup sendiri. Ia ditakdirkan sebagai bagian dari lelaki…”
“Anggapanmu yang keliru, sayang,” bantah Susi. “Bukan zamannya lagi perempuan harus tergantung pada lelaki. Perempuan mesti menjadi istri. Lagi pula, aku sudah mengalami hal itu, apa yang dikatakan orang berumah tangga. Aku sudah pernah punya suami. Aku juag sudah mengalami melahirkan dan punya anak. Apa lagi?”
Endah mendesah.
“Kau sungguh-sungguh?”
“Aku tak pernah main-main, Endah. Selalu serius,” Susi meyakinkan.
Tetapi, benarkah aku serius? Benarkah aku mampu hidup sendiri? Menjadi singel parent? Lagi-lagi Susi disergap ragu. Setiap pertanyaan itu muncul, ia malu. Sebab, sesungguhnya Susi tak pernah merasa sepenuhnya kokoh dalam menjalani hidup sendiri. Jiwanya kerap rapuh. Terutama setiap malam menjelang. Tak dapat dipungkiri bahwa ia kadang merindukan jalan bersama seorang lelaki, bergandeng tangan. Turun dari mobil lalu memasuki mal atau kafe atau ke pesta.
Kerinduannya itu kemudian dia hapus. Atau mati sendiri begitu ia tertidur. Dan esok pagi ketika bangun, merasa kembali segar. Susi tetap semangat menyiapkan sarapan pagi dan segala sesuatu bagi kedua anaknya. Juga bagi dirinya. Bahkan seperti tak terjadi apa-apa ketika ia duduki kursi tempatnya bekerja. Mungkin hanya Endah, teman karibnya, yang tahu kalau semua yang dilakukan Susi hanya tampak luarnya. Sesungguhnya, hati Susi tetap kesepian.
Aku tidak kecewa pada lelaki, karena memang Bang Zul tak pernah mengecewakanku. Bahkan Bang Zul amat baik, ia sangat mencintai dan menyayangiku. Bang Zul bertanggung jawab pada keluarga. Itu sebabnya ia tak kenal hari libur jika ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Karena itu pula usianya digerogoti penyakit, membuat Bang Zul lebih cepat dipanggil Tuhan. “Jadi maafkan aku kalau aku tak mau lagi berkeluarga. Tak ingin mengkhianati cinta Bang Zul. Biarlah orang mengatakan aku apa saja, karena kesetiaanku ini pada suamiku,” Susi selalu mengutarakan itu pada Endah, setiap temannya itu menawarkan agar berumah tangga lagi.
“Kau tak berkhianat pada Bang Zul, Sus. Kesetiaan tak harus diujudkan dengan cara sepertimu ini,” tegas Endah. “Aku juga pernah sepertimu. Yang membedakan bahwa suamiku mati di sebuah bar saat mabuk. Ia mati di tangan para preman…” ucap Endah lirih.
Lanjut Endah, “Aku tetap mencintai Mas Im, meski kutahu di luar ia berkhianat. Lantas apa cukup cinta itu untuk hidupku mendatang? Tidak, Susi. Tidak. Aku hanya bisa bertahan
“Sampai sekarang?”
“Tidak. Aku sudah bisa melupakan Mas Im. Aku tak mau berkhianat dengan suamiku yang baru. Aku harus realistis, sekarang aku adalah istri Kang Daniel.”
“Begitu cepatkah?”
“Tidak juga. Prosesnya cukup lama.”
Setelah itu Susi mendesah. Dalam hati ia menolak apa yang dikatakan Endah. Perasaannya tak dapat menerima perjalanan hidup sahabatnya itu. Cinta memang tergantung yang merasakannya. Bagi Susi, cinta adalah segalanya yang dipenuhi keindahan. Di
“Aku pikir kita realistis saja. Seperti hidup ini selalu realistis,” kata Endah lagi setelah beberapa lama hening.
“Itu pandangan seorang realisme. Aku bukan menganut aliran itu,” bantah Susi. “Adakalanya hidup ini tidak dilihat secara realistis. Kita harus mengakomodir pandangan-pandangan lain, misalnya absurditas, surealis, bahkan mistis!”
“Terserah kaulah kalau begitu,” Endah kehabisan cara. “Aku hanya menyarankan. Itu kalau kau mau menerima. Aku kasihan dengan kedua anakmu. Mereka masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah…”
“Kalau soal anakku tak ada masalah. Aku dapat berperan sekaligus sebagai seorang ayah…”
“Oke. Oke…”
Endah lalu mengatup mulutnya. Pembicaran sudah saatnya dikunci. Ia menginginkan dialog dengan Susi untuk mendapatkan kebenaran, namun karena percakapan menjurus pada pembenaran lebih baik tak perlu diteruskan. Ia yakin kalau dilanjutkan akan meruncing jadi perdebatan, dan ujungnya bakal bertengkar. Selalu ia menghindari pertengkaran jika berdialog dengan Susi. Sesungguhnya Susi pun begitu, kalau saja ia tidak tersudut. Cuma kalau bicara soal rumah tangga, Susi merasa dipojokkan oleh Endah. Itulah yang membuatnya kerap tak bisa menahan emosi. Lalu keduanya bertengkar. Seperti pernah dilakukan Susi, menurunkan sahabatnya itu di jalan.
*
SUSI mendaki bukit menuju
Hanya sebentar di dalam, lelaki itu keluar. Ia mengitari
“Tak bisa kurang?”
“Itu harga mati,” jawab Susi pendek. “Kalau tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Hanya…”
“Kenapa
“Malas merawatnya saja. Butuh biaya lain…”
“Sayang…”
“Benar. Kalau sudah tidak lagi penting, buat apa saya pertahankan?”
Diam. Selanjutnya suasana hening. Sama-sama kikuk. Ragu untuk memulai percakapan kembali. Sesekali saling curi pandang, namun Susi selalu menunduk setiap hendak beradu tatap. Sebagai perempuan, ia tak mampu kokoh menahan gejolak hatinya jika lama dipandang seperti itu. Karena itu segera membalikkan wajah. Menutup pandangannya dengan helai-helai rambut. Hatinya berdegup…
“Oke, aku bayar
Susi mengangguk. “Kapan saya bisa terima?”
“Sekarang pun bisa, saya akan kasih cek,” jawab lelaki itu pendek. “Tapi saya sedang menunggu seseorang…”
“Siapa?”
“Ah, maaf. Maksud saya, apakah Anda tak menyesal menjual
“Tapi, saya sudah bertekad menjualnya.”
“Maksud saya, apakah Anda tak menyesal?”
“Itu soal lain…”
“Bukankah
“Itu dulu. Sekarang sudah tak lagi.”
“Maksudnya?”
“Ah, maaf. Itu urusan pribadi, sangat privasi.”
“Kalau begitu, maafkan saya.”
“Saya juga mohon maaf,” kata Susi pendek. Pelan.
Keduanya kemudian kembali terdiam. Sebuah taksi Siger meluncur dari bawah. Berhenti di depan mobil Susi. “Sory aku terlambat!” teriak Endah. Turun dari taksi. “
“Lo, siapa yang mengundangmu?” olok Susi.
“Jimmy!” sergah Endah yakin. “Bukan karena undanganmu aku ke sini, tapi Jimmy. Inilah orang yang selalu kusebut. Pengusaha sukses, tapi gagal dengan rumah tangganya. Makanya dia duda sekarang…”
Duh! Hati Susi berdesir. Nyaris kehilangan degup. Kini ia benar-benar yakin, bahwa hidup ini absurd.
“Tapi ini serius, Sus. Jimmy memang mau membeli vilamu,” kata Endah lagi.
“Benar. Saya memang menyukai
“Juga… sudah lama menyukai pemiliknya,
“Aku tak ragu kok. Cuma kau bikin aku malu…”
“Kok melibatkan aku?” Susi menunduk. Melengos. Beranjak dari tempat itu. Hatinya galau. Ia masuki vilanya. Dibiarkan pintunya terbuka lebar. Angin seakan dipersilakan masuk. Bebas. Jika pintu sudah terbuka, siapa pun tak akan ragu memasukinya. Itu juga untuk Endah dan Jim. Bukankah tidak baik (tak etis?), pesan Bang Zul yang selalu diingatnya, bila kau tutup pintu sementara tamu di luar menunggu? *
Lampung, 11-14 Februari 2005; 11.29
8. Hanya untuk Satu Nama
HANYA untuk satu nama: Demi.
Kalimat itu terukir rapi di atas foto Mas Zen berlatar belakang bunga tulip yang tengah mekar. Tentunya foto itu diabadikan saat musim bunga sedang berlangsung di Belanda. Aku menerima kiriman itu dari Mas Zen dua tahun lalu. Saat Zen kuliah di negeri Kincir Angin itu.
Di bawah kalimat itu tertulis dengan tipografri puisi: “Rademi Pratiwi,/bila musim salju tiba seperti sekarang ini,/aku makin rindu padamu./Ingin mendekapmu/sepanjang tidurku/di balik selimut tebal.//Atau dalam mantel tebal menembus salju/sepanjang jalan di Amsterdam ini/kita saling melingkarkan tangan/di pinggang.//Kau tahu,/aku selalu bayangkan/kau ada di dekatku,/dalam dekapanku…”
Dan hingga kini kenang-kenangan dari Zen masih dipajang di tembok rumahku. Kalimat indah itu, “Hanya untuk satu nama: Demi”, seperti ingin mengekalkan waktu. Tetap tidak luntur karena usia. Dan, saban hari aku selalu menatap kenangan itu. Membaca kalimat-kalimat puitik yang diukir rapi itu.
Aku menerimanya dengan bahagia sekali saat itu. Rasanya aku ingin segera terbang. Segera mendekapnya. Berlari-lari menembus salju. Dan jika gigil menyergap akan kupeluk Mas Zen. Maklum waktu itu kami baru enam bulan menikah. Kata orang, perkawinan kami masih masa bulan madu. Karena itu, masih dipenuhi oleh fantasia dan imajinasi yang indah-indah.
Sesungguhnya aku berat membiarkan Zen meninggalkanku sendiri. Kalau saja bukan karena tugas dari tempatnya bekerja dan kesempatan disekolahkan oleh perusahaan amatlah langka—tidak akan terulang oleh orang yang sama, akan kukatakan padanya: “Jangan tinggalkan aku, Mas Zen. Aku tak berani didera rindu…”
Waktu itu Zen membujukku, “Tiga tahun tidak lama, sayang. Hanya sekedip mata jika hati kita sama-sama terpaut. Kau bisa meneleponku setiap malam jika rindu. Aku pasti akan menghubungimu bila aku kangen. Kesempatan baik seperti ini tidak akan datang dua kali…”
Lalu kujawab, dengan perasaan cemburu, “Gadis-gadis
“Kau lebih cantik dari mereka, kau adalah segala-galanya bagiku. Lagi pula aku ke
Itulah percakapan saat-saat jelang keberangkatan Zen ke Belanda. Sehari sebelum Zen meninggalkan
Tiga tahun bagi orang lain memang hanya sekejap. Tetapi tidak untukku yang kala itu tengah menikmati indahnya awal berumah tangga. Aku ingin menemani Zen, cuma perusahaan tempatnya bekerja tidak membolehkan. Alasannya, karyawan yang disekolahkan tidak boleh diganggu sehingga ia bisa kembali dengan sukses. Selain itu, perusahaan tidak menanggung di luar yang mendapat beasiswa. Artinya, jika aku menyertai Zen aku harus menanggung seluruh biaya transportasi dan segala keperluan selama di Belanda. Bagaimana mungkin bisa? Biaya hidup di
*
MAKA aku menanti Zen dengan rindu yang mendalam. Deru kangen karena kesepian bagai ribuan lebah yang mendengung. Meski Zen tak pernah alpa meneleponku setiap malam, jelang aku ke peraduan. Hanya telepon dan suara penuh kerinduan dari Zen itu, seakan dapat menenteramkan hatiku. Aku pun bisa terlelap hingga esok pagi terbangun. Tiga bulan di Belanda, kiriman foto Zen dengan latar belakang bunga tulip yang lagi mekar kuterima. Di foto yang terbingkai rapi itu terukir tulisan Zen: “Hanya untuk satu nama: Demi”.
Ya. Aku tahu dan sekaligus aku percaya. Hanya satu nama—namaku, yang terukir di hatinya. Nama perempuan yang sejak lama mencintainya. Perempuan—dan aku tentunya—yang setia menanti, dan kini telah resmi menjadi istrinya dengan setia pula akan menanti ia kembali.
Bila rindu memendam, kupandangi foto kiriman Zen itu. Kubayangkan seindah apakah bunga-bunga tulip sesungguhnya? Kuangankan Zen menyusuri taman bunga itu. Atau melintas di bawah Kincir Angin. Sendiri. Gigil. Sebab salju turun tak kenal waktu. Seandainya, ya seandainya, aku ada di sisinya tak kubiarkan salju menyentu kulitnya. Aku akan segera menepis agar dia tak merasa kedinginan.
“Ah, kau terlalu obsesif. Dingin memang jika salju sedang turun, namun tidak seperti kita bayangkan. Buktinya tak ada orang yang mati di sini tertimbun salju
“Bener Mas, enggak kedinginan. Demi mengkhawatirkan Mas Zen,” kataku manja.
“Benar, sayang. Kalau aku kedinginan, akan kubayangkan kau ada di dalam mantelku. Atau mendekapku di balik selimut tebalku. Agar gigil hilang, kehangatan datang.”
“Aih Mas, bercanda terus!” aku merajuk. “Jangan-jangan sudah ada yang menggantikan aku ya di situ?”
“Tu
Aku malu. Lalu, kujawab, “Tidak kok. Aku tidak cemburu…”
“Lalu, apa?”
“Kangen…”
“Sama.”
Kemudian kami tertawa. Aku membayangkan Zen memelukku. Erat sekali. Lalu menggiringku ke kamar. Ah, sedang apa Zen di
“Belum tidur, Tiwi?”
Ah! Ternyata Mama yang meneleponku. Keluargaku memang biasa memanggilku Tiwi. Sedangkan teman-temanku acap menyapaku dengan Demi, bahkan kadang ditambah dengan
“Belum, Ma.
“Enggak. Hanya ingin tahu keadaanmu.”
“Tiwi sehat-sehat saja, baik-baik saja kok. Mama juga baik-baik saja
“Syukurlah,” ujar Mama kemudian. “Zen sudah meneleponmu? Beberapa menit lalu dia menelepon Mama, menanyakan kabar keluarga kita. Katanya, dia sehat-sehat saja di Belanda. Hanya sebentar menelepon Mama, katanya mau meneleponmu…”
“Kok, Mas Zen tak bilang kalau habis menelepon Mama? Ya Ma, dia baru teleponku. Hampir dua jam dia ngobrol dengan Tiwi. Cerita macam-macam deh…”
“Mungkin, menurut dia, tak begitu penting,” jawab Mama pendek. Lalu lanjutnya, “Mama sehat, papa juga baik-baik. Tapi sudah empat hari ini belum pulang. Kau tahu sendirilah kelakuan Papamu.
“Jadi, Mama sendirian sekarang?”
“
“Ya. Tapi, Mama tetap sendirian!” kataku menegaskan. Dalam hati aku membenci Papa yang selalu meninggalkan Mama sendirian di rumah. Menelantarkan Mama di rumah. Sementara dia asyik berjudi sambil ditemani perempuan-perempuan anjing. Jangan-jangan papaku yang sesungguhnya anjing?
“Jangan mengkhawatirkan Mama, Tiwi. Mama baik-baik saja kok…” Mama membuyarkan lamunanku.
“Kalau begitu, besok pagi Tiwi pulang. Tiwi mau tidur dengan Mama, menemani Mama…”
“Tak usah Tiwi. Jangan tinggalkan rumah selagi suamimu tidak ada. Apalagi kau belum izin dengan Zen, tidak baik.”
“Aku akan menelepon Zen, minta izinnya. Sekarang. Besok pagi aku ke rumah…”
Setelah kumatikan hubungan telepon ke Mama, segera kutelepon Zen. Berkali-kali kuhubungi nomor tempat Zen menginap tak diangkat-angkat. Aku berpikir, mungkinkah Zen tidur kagi setelah meneleponku karena hari libur? Atau, pikiran lainku menyergap, jangan-jangan ia sedang keluar bersama perempuan bule? Aku cemas. Membuatku sulit sekali memejamkan mataku.
Pada pukul 02.01 kembali kutelepon. Seorang lelaki, tentulah teman Zen di tempat kosnya itu, yang menyambut. Ia katakan kalau Zen sedang keluar. “Katanya mau cari buku,” jelasnya. Lalu aku menitip pesan: jika Zen pulang segera teleponku.
*
SUDAH lama aku tidak mengunjungi Mama. Kini kurasakan tubuh Mama makin menyusut. Pandangannya tidak seperti dulu lagi, bercahaya. Tersadar bahwa aku sudah lama meninggalkan Mama. Tepatnya sejak aku menikah, Zen memboyongku ke lain
Aku akan menetap di rumah Mama untuk beberapa hari. Mungkin juga sepekan atau lebih. Zen sudah mengizinkan. “Itu bagus, Demi. Daripada kau kesepian di rumah, lebih baik temani Mama. Kasihan Mama juga sendirian…” . kata Zen.
Dan, memang Mama selalu sendirian. Papa tak pernah pulang. Kalau pun pulang hanya mengganti pakaian atau seperti menumpang tidur, lalu pergi lagi untuk beberapa hari kemudian. Tanpa percakapan. Tiada lagi sapa dan menyapa antara Mama dan Papa. Keduanya pun tampak tak bersitatap. Bila Papa mau makan segera ia ke meja makan, dan Bik Sumi sudah menyiapkan hidangan.
Aku tahu Mama amat kecewa pada Papa. Mama telah dikhianati. Diam-diam Papa main perempuan saat di luar rumah. Bahkan, ini menurut Mama, Papa sudah menikah. Selain itu, Papa penjudi berat. Hampir ludes harta di rumahku dibawa Papa ke meja judi. Padahal, kekayaan itu ditabung Mama bertahun-tahun dari hasil kerja Papa. Untunglah peursahaan Papa tidak ambruk. Untung pula Mama segera mengambil alih kemudi perusahaan tersebut, kemudian dijalani oleh Om Firman—adik bungsu Mama hingga kini. Om Firman S2 ekonomi lulusan Amerika. Kalau tidak, entah apa jadinya dengan nasib perusahaaan Papa. Kini Papa tak lagi diperkenankan menjalani roda perusahaan. Hanya mendapat bagi keuntungan setiap tahunnya.
Papa juga tak punya hak atas saham perusahaan tersebut. Kata Mama, sejak ketahuan Papa beristri lagi, Mama langsung menggugat. Tidak tanggung-tanggung, Mama menggugat cerai dan sekaligus menyoal gono-gini. Papa keberatan digugat cerai. Lalu Mama kasih solusi. “Baik kalau kau tak mau menceraikan aku. Cuma aku minta syarat, serahkan saham dan perusahaan itu padaku.”
“Untuk apa? Apakah kau sudah tak percaya lagi dengan kemampuanku menjalani perusahaan?”
“Dulu aku percaya,” jawab Mama ketus. “Kalau kau masih pegang perusahaan, bisa-bisa kekayaan kita kauhabisi di meja judi dan untuk perempuanmu itu. Aku akan menggaji Firman untuk memajukan kembali perusahaan itu. Sementara soal saham, itu ganti dari pengkhianatanmu padaku.”
Papa tak berkutik. Akhirnya Papa keluar dari perusahaan miliknya itu. Meski begitu, Mama tetap menaruh kasihan pada Papa. Mama selalu membuka pintu bagi Papa untuk pulang. Menyilakan Bik Sumi menghidangkan makanan buat Papa. Membelikan pakaian beberapa bulan sekali untuk Papa. Mama juga menyediakan satu kamar tidur buat Papa jika pulang. Dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali satu: Mama tak lagi memberikan cintanya. Mama juga tak hendak dicumbui…
Mama senang sekali ditemani aku. Waktu-waktu senggang, kami isi dengan berdialog. Bahkan jelang tidur (kebetulan aku meminta tidur bersama Mama di kamarnya), kami masih mengobrol. Sampai mata kami mengatup sendiri. Begitu pula di meja makan saat sarapan pagi, kami pun mengobrol. Intensitas percakapan kami melebihi ketika aku belum berkeluarga. Entah mengapa tiba-tiba aku merasakan keakraban yang berlebihan justru ketika kami sudah sering tak berjumpa. Mungkin benar, kata orang, sebuah pertemuan akan menjadi indah dan bermakna apabila intensitas pertemuan sebelumnya amat kurang. Kini kurasakan itu. Baik aku atau Mama seperti tak ingin melewatkan waktu tanpa berdua-dua dan berdialog. Suasana itu juga dibarengi dengan tertawa atau tersenyum.
Akhirnya aku lupa pada Mas Zen. Lupa kalau sesungguhnya aku sedang kehilangan suasana bulan maduku. Bila di rumah aku selalu menunggu Zen menelepon, namun bersama Mama aku tak begitu lagi berharap-harap. Mungkinkah aku sudah kehilangan rindu? Adakah Zen juga sudah kehabisan kangen, disebabkan kesibukannya? Ah! Aku tak yakin lantaran kesibukan, ia bisa abai meneleponku. Jangan-jangan sudah ada perempuan lain yang merebut kerinduannya padaku? Jangan-jangan karena aku mendapatkan kebahagian dan keriangan bersama Mama, membuatku tak berharap lagi perhatian Zen?
Teringat ucapan Zen bahwa saling percaya dan jujur akan menjaga cinta, belakangan ini sudah tidak begitu kuyakini. Mama adalah contoh paling dekat bagiku. Betapa tingginya kepercayaan Mama, betapa jujur dan setianya Mama pada Papa. Tetapi, sekaligi lagi tetapi, Mama terlempar ke tepi paling sepi oleh ketidakjujuran Papa. Terbukti akhirnya Papa mencampakkan kepercayaan Mama dengan bermain perempuan lagi. “Papamu buktinya tidak jujur, diam-diam dia mengkhianati kesetiaan Mama…” kata Mama yang tampak benci sekali.
Kata Mama lagi, “Semua lelaki sama. Bajingan! Pengkhianat. Tidak jujur. Merobek-robek kepercayaan yang diberikan perempuan!” Entah mengapa, Mama berulang mengutuk Papa di depanku. Mungkinkah di balik itu semua, ia ingin mengingatkan aku bahwa jangan terlalu percaya pada bahasa dan janji lelaki. Berkali-kali kubela Zen bahwa suamiku bukan tipe lelaki seperti Papa, tetapi berkali pula Mama membongkar kebejatan Papa. Supaya tak terjadi perdebatan yang berakibat retaknya kebahagiaan kami, aku tak lagi mengimbangi dialog Mama. Aku diam. Mendengarkan keluh-kesah Mama.
*
ZEN menelepon pada malam kedelapan aku menginap di rumah Mama. Aku santai saja mengambil gagang telepon ketika Mama memanggilku bahwa Zen ingin bicara padaku. Tidak seperti ketika aku di rumahku: mendengar dering telepon sekali saja aku segera menyambar dengan hati berbunga-bunga.
“Halo…”
“Kau sehat Demi?”
“Ya. Mas Zen sendiri, juga sehat
“Aku sehat. Tentang studiku juga sampai hari ini aman-aman saja. Tak ada masalah,” jawab Zen. Entah mengapa aku mendengar suaranya tidak berapi-api seperti dulu, tidak hangat karena penuh oleh kerinduan. Kini dingin. Datar. Bahkan terdengar sumbang dan sember.
“Syukurlah. Kalau kau bahagia di
“Ya.”
“Kau sudah makan?”
“Baru saja. Kebetulan ada teman yang mengajakku makan di luar. Aku ditraktirnya, karena dia berulang tahun,” ujar Zen kemudian. Ketika Zen menyebut “dia”, tiba-tiba kedengarannya terasa asing. Aku ingin sekali tahu siapa “dia” yang disebut Zen.
“Siapa temanmu, Mas? Lelakikah?”
“Oh, maaf Demi. Aku belum mengenalkan temanku yang mentraktir makan. Dia perempuan, asli dari
“O ya? Aku yakin dia pasti cantik…”
“Ya sejujurnya, Juliana memang cantik,” jawab Zen pendek.
“Dia menyenangkan, bukan?”
“Ya. Orangnya ramah. Mungkin karena ia pernah tinggal beberapa lama di
“Tak usah Mas. Terima kasih…” jawabku. Aku seperti enggan melanjutkan dialog soal perempuan
“Orangnya familiar, Demi. Kau pasti suka kalau sudah mengobrol dengannya.”
“Mudah-mudahan…”
Setelah itu, Zen mengutarakan rencananya ingin berlibur ke beberapa
“Ini kesempatan yang tak akan datang dua kali. Sayang
Aku sudah kehabisan kalimat lagi, karena selalu kata-kata “langka dan kesempatan yang tak akan datang dua kali” akan meluncur dari mulut Zen. Akhirnya aku hanya berpesan, “Hati-hati di jalan. Ingat orang Eropa berbeda dengan bangsa Timur.”
Zen tersenyum. Ia juga mengakui sejujurnya kalau sebenarnya Juliana Derks menyukainya. Tetapi, ia tak mungkin terjebak untuk jatuh cinta. “Cintaku hanya untuk satu nama: kau, Demi…”
Cuma aku tak lagi merasa tersanjung dengan pujian seperti itu. Aku bahkan ingin segera menyudahi percakapan ini. Dengan alasan mau tidur karena sudah larut dan aku juga sudah mengantuk, aku meminta Zen menutup gagang telepon.
*
AKU sangat kaget, nyaris tak sadarkan diri ketika teman kost Zen mengabarkan kalau suamiku mengalami kecelakaan di Jerman. Pesawat mereka tak bisa landas dengan baik karena pacuan bandara licin. Akhirnya pesawat itu menabrak pagar pembatas bandara dan terganjal di pemakaman. Sekitar 50 penumpang, termasuk Zen dan Juliana Derks, tewas di tempat kecelakaan.
Dibiaya oleh perusahaan tempat Zen bekerja, aku menjemput mayat Zen di Jerman. Lalu membawanya ke
Aku sungguh-sungguh sedih. Entah karena kematian Zen, nasibku yang kini harus menjadi janda tak beranak, atau karena kejujuran dan kepercayaanku pada Zen yang dikhianati. Sebab, seperti kata Ronald Rijkad, perempuan
Aku kasihan pada Zen, sekaligus membencinya!
*
HANYA untuk satu nama: Demi.
Kalimat itu terukir rapi di atas foto Mas Zen berlatar belakang bunga tulip yang tengah mekar. Foto itu masih tetap terpajang di dinding rumahku. Di ruang tamu. Aku akan memandangnya, setiap aku merasa benar-benar rindu pada Zen. Aku belum ingin menurunkannya dari tembok itu untuk kusimpan di lemari atau gudang.
“Phuihh!”
Aku seperti hendak muntah setiap membaca baris-baris kalimat yang ditulis rapi dengan tangan Zen itu. Cuma sampai kini belum menghasutku untuk menurunkan atau membakarnya…*
Lampung, Februari 2005
9. Batas Rencana
/1/
“AKU selalu berencana. Entah itu awal bangun tidur pagi hari atau malam menjelang mengatupkan mata. Rencanaku selalu yang besar-besar. Sebab aku meyakini bahwa dengan rencana yang besar, maka peluang kegagalan dalam hidup makin kecil.”
“Kalau aku lebih percaya dengan rencana-rencana kecil, yang sederhana. Ingatlah dengan Ebiet1), ia punya renana yang selalu sederhana. Kehidupannya pun sederhana. Tetapi, kini dia sukses—setidaknya sebagai penyanyi…”
“Aku tak sependapat denganmu. Aku percaya dengan falsafah orang-orang besar: berpikirlah besar, berencanalah yang besa-bersar. Karena apa yang kaupikirkan, apa yang kau rencanakan niscaya itulah yang didapat.”
/2/
“ABANG aman-aman saja, selamat. Tapi keluarganya tak bisa tertolong, hilang…” katamu.
Waktu itu tampak sekali kau terpukul. Pandangmu kosong. Kau sakit? Stres. Bencana itu telah merontokkan rencana-rencana yang telah dibuat.
Kau sadar kini. Betapa pun teliti dan besarnya rencana, dapat saja sekejap berantakan karena kekuatan lain di luar kemampuan manusia. Kau pernah membanggakan segala rencanmu yang besar itu. Segala urusan untuk penyambutan abang dan keluarganya sudah disiapkan.
Katamu, “Untuk Ibu dan Ayah sudah kusiapkan kamar di depan. Spresi, selimut, bantal, guling… Semuanya baru kubeli dan sudah rapi kusimpan di lemari. Sedang untuk Abang sudah pula kusiapkan kamar di tengah. Kami di kamar belakang. Ayam kampung sudah kubeli dan kini masih kupelihara di kandangnya. Aku ingin setiap hari, keluarga abang makan daging ayam…”
Kemudian kau lisankan rencana-rencana besar lainnya. Misalnya, soal prosesi perkenalan antara keluarga Abang dengan keluargamu. Kau mau mengundang seluruh tetangga dekatmu untuk menyambut keluarga Abang. Meski hanya lamaran, kau tak menghendaki kesan dipersiapkan sekadarnya. “Aku ingin tetap meriah, riuh, dan ramai,” katamu berencana.
“Bukankah yang penting diramaikan saat menikah?” tanyaku. Aku menyarankan daripada prosesi lamaran dimeriahkan, lebih baik biaya tersebut disimpan saja untuk pernikahan atau untuk modal memulai rumah tangga.
Kau berang. Tidak menerima saranku. Kau bilang, “Ini hanya sekali dalam hidup. Kenapa tidak dimanfaatkan? Lamaran dan resepsi pernikahan sama bernilainya bagi seseorang!”
Menurutmu, untuk apa bekerja kalau bukan untuk mendapatkan uang? Untuk apa uang kalau tidak digunakan hal-hal yang bahagia? Dan, paling bahagia dalam hidup perempuan adalah saat dilamar dan dinikahi. “Aku ingin saat-saat berbahagia itu tidak aku sia-siakan. Aku senang uang simpananku habis, asal hari bahagiaku terlaksana dengan sukses,” ujarmu.
Kau berencana, setelah menikah akan kau boyong Abang ke rumah yang dibeli dari tabunganmu bertahun-tahun. Bukan sebaliknya, kau yang diboyong Abang ke tempat tinggalnya. Tegasnya, kau menolak tinggal di rumah orang tuamu atau menumpang di rumah orang tua Abang setelah menikah. “Seindah-indah tinggal di rumah orang tua, lebih indah dan bahagia menyewa rumah. Di rumah sendiri, kita diajarkan hidup mandiri. Tidak cuma menyusu dari orang tua…”
Aku tak setuju pada pendapatmu. Banyak pengalaman orang yang baru beurmah tangga tidak bisa hidup mandiri, karena pasangan itu belum dewasa. Tetapi, banyak pasangan muda yang justru sukses tinggal bersama orang tuanya. Jadi, smeua itu tergantu dari orangnya. Bukan tempat atau rumah di mana ia menetap. “Kalau dasarnya memang pemalas, ya di mana pun tak akan sukses,” kataku.
Benar. Kau menyetujui pendapatku. Hanya saja, katamu, orang yang tidak berakallah yang akan menelantarkan rumah tangganya. Kalau menumpang di rumah orang tua, sebab dasarnya pemalas maka dia akan makin pemalas. Sebab dia selalu mengandalkan kekayaan orang tuanya.
“Berbeda kalau tidak menumpang di rumah orang tua. Kita akan berpikir bagaimana hari ini atau besok harus makan. Bagaimana mengisi perabot rumah tangganya. Kita juga dituntut untuk membeli pakaian, ranjang, kasur, bantal,” katamu. “Kalau genting bocor, kita berpikir untuk menutup atau menambalnya supaya tidak kebanjiran…”
Rencana-rencana itu selalu kau kibarkan. Rencana-rencana besarmu yang kau yakini bakal terwujud. Tetapi, bencana besar itu kini telah menghancurkan rencanamu. Mengoyak hingga tak ada lagi kepingannya.
/3/
SUDAH kuingatkan, bahkan berkali-kali, jangan terlampau besar berencana. Tidak setiap rencana menghantar kita menjadi sukses. Sebab banyak pula orang yang malah tak memiliki rencana-rencana, kemudian menjadi orang sukses?
Itu sebabnya, aku menaruh simpati dan salut pada anak-anak yang menggeleng jika ditanya oleh orang tuanya, “Apa cita-citamu kalau sudah besar?”
Aku mencurigai adanya campurtangan orang tua atau orang-orang dewasa untuk menentukan cita-cita seorang anak. Karena itu, anak-anak dengan fasih dan angkuhnya saat menyebut cita-citanya saat besar kelak. Misalnya, ingin jadi dokter, menteri, presiden, gubernur, walikota, bupati, peragawati, artis, perawat, guru, hakim, pengacara. Pernahkah anak-anak bercita-cita menjadi seniman, preman, ustad, ataupun pendeta? Bahkan, belum pernah kudengar anak-anak melontarkan cita-citanya kelak menjadi diri sendiri. Sungguh, aku punya dugaan yang besar bahwa peran dan campur tangan orang dewasa telah memengaruhi rencana anak-anak. Aku tak menyukai cara orang dewasa mencekoki jiwa anak-anak!
Batas itu terbukti dari rencana-rencana yang dicapai. Sebab itu, aku tak bosan dan segan mengingatkanmu, akan batas rencana itu. “Semakin besar rencanamu, kian besar pula lubang kekecewaanmu jika tak tercapai. Jadi, rencana itu sederhana-sederhana saja. Yang kau yakin pasti dapat tercapai. Sehingga kalau pun tak tercapai, sederhana pula kekecewaanmu,” kataku, suatu kesempatan.
Tetapi kemudian, kau melengos. Pergi untuk meninggalkan aku sendiri di kursi ini. Minuman yang belum kau sentuh, kau tinggalkan. Sungguh mengecewakan. Hanya aku suka pada sikapmu. Ketegasanmu. Dan, hingga kapan pun, kau tetap mempertahankan rencana-rencana besarmu. Maksudku menyampaikan rencana-rencana besarmu, seraya kau meyakini bahwa rencana-rencanamu itu pasti kesampaian. Tak berbatas. Seperti pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apakah dan di manakah batas langit itu? Tak terbilang bukan?
Maka aku hanya diam ketika kau berencana ingin membangun rumah mewah, begitu kau telah menikah kelak. Di lantai dua rumahmu akan dibuatkan sebuah kolam renang. Di sanalah, jika penat dan pikiran kacau maka kau akan menceburkan dirimu. Berenang hinga sepuas-puasanya. Sampai badanmu dingin. Hingga pikiranmu kembali segar. Lalu kau naik dari kolam renang itu, menggandeng suamimu ke kamar. Handuk masih melilit tubuhmu ketika kau mengajak suamimu bercengkerama…
“Bukankah itu indah? Siapa pun akan menyukai suasana seperti itu. Entah itu pengantin baru atau suami istri yang telah beruban!” tegasmu.
Aku diam. Sebab, tiba-tiba gelombang besar yang dimuntahkan oleh laut meluluh-lantakkan segala renacamu. Seluruh impianmu. Rumahmu hancur hingga rata dengan tanah. Buku tabunganmu. Buku cek yang menyimpan uangmu di bank hanyut. Juga bank beserta uang di teller lenyap.
“Takdir menentukan lain. Tetapi, aku tetap punya rencana. Rencana yang sangat besar. Aku tak akan pernah mati berencana. Orang hidup harus berencana, jika tak ingin dikatakan dia telah mati,” ujarmu lagi.
/4/
AKU perempuan. Lalu, salahkah aku mencatat segala rencanaku? Rencana-rencana yang besar? Apakah hanya lelaki yang boleh dan dihalalkan berencana, sementara perempuan cukup punya rencana sebagai ibu rumah tangga, hanya bercita menjadi istri yang baik yang tak pernah abai mengurus suami, memasak yang enak buat suami dan anak-anaknya? Melahirkan, menyusui, mengasuh anak-anak? Jadi ibu rumah tangga di rumah, tak perlu menjadi wanita karier, sebab karier seorang perempuan sebatas dapur-sumur-kasur?
Sungguh tidak adil! Itu peraturan-peraturan yang sengaja dibuat kaum lelaki. Koridor-koridor itu, petuah-petuah itu, sengaja dibuat lelaki agar para perempuan membunuh rencana-rencananya. Perempuan tak boleh memiliki rencana!
Karena itukah Tuhan tak mengutus nabi dari kalangan perempuan? Politik selalu menutup pintunya bagi perempuan. Parlemen hanya sedikit dimasuki perempuan. Jabatan-jabatan empuk dan strategi bukan diserahkan pada perempuan. Karena perempuan dianggap tabu memiliki rencana. Sejak kecil perempuan hanya dibelikan boneka dan perabot masakan oleh para orang tua. Berbeda dengan anak-anak lelaki. Mereka dibelikan pistol-pistolan, mobil-mobilan, pesawat terbang, helikopter, panser, dan kursi.
Kursi? Ya sengaja kursi dibelikan oleh para orang tua untuk anak lelaki. Karena kursi itu simbol bagi kedudukan. Dan, itu kemudian yang selalu dikejar oleh para lelaki. Meninggalkan perempuan yang memang kodratnya lamban bergerak, karena sejak kecil hanya dijejali dengan mainan boneka dan masak-masakan. Mainan-mainan itu cukup dimainkan sambil duduk-duduk. Tidak seperti mainan para lelaki: selalu membutuhkan energi. Bergerak.
Bayangkanlah. Bukankah itu tidak adil?
/5/
KINI kau tak lagi dapat merebut kembali rencana-rencana besarmu yang tersapu air besar itu yang datang tiba-tiba. Calon mertuamu—juga bakal adik iparmu—menjadi korban atas bencana itu. Semua mati. Ketika abangmu (kau selalu menyebut kekasihmu seperti itu) sampai di rumah dari kepergiannya ke luar
Kau menangis. Airmatamu mengalir deras. Ketika Abang mengabarkan nelelui telepon genggam dini hari, kau tak mampu menahan untuk tidak menangis. Kemudian berulang-ulang kau ingatkan abang harus tegar menerima kenyataan itu. Pasrah. Manusia datang dari Allah dan akan dipanggil-Nya kembali. Segala yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya kematian bisa di mana saja dan pada saat apa saja. Orang bisa mati di lautan, di air yang menghitam, di kasur saat tidur atau sedang bercinta, di rumah sakit, di kenderaan, di pesawat terbang, juga di semak-semak, hotel, kompleks pelacuran… (“Tapi aku ingin mati saat beribadah, dalam keadaan tunduk pada-Nya,” kataku tegas. Kau mengangguk).
Lalu bayangan kedua orang dan adik abang seperti berkelebat di benakmu. Mereka datang dengan pesawat terbang—karena memang kotanya sangat jauh dan harus ditempuh oleh pesawat terbang—membawakan oleh-oleh untuk lamaran. Kau menerimanya dengan sukacita. Kau sumringah. Meski airmatamu mengalir, tapi itu tangisan bahagia. Aku merasakan itu.
Kau menerima lamaran keluarga abang. Ditetapkan tanggal, bulan, dan pada tahun ini berlangsung pernikahanmu. Sudah terbayang rumah mewah dengan kolam renang di lantai dua. Kau menggandeng abang yang menyambutmu di tepi kolam sambil menyerahkan handuk. Kemudian kau menggandeng abang memasuki kamar.
Entah mengapa secepat itu kau menangis. Tersedu-sedu. Kaututup kedua wajahmu. Mungkin malu, mungkin tak sanggup menerima kenyataan. Keluarga abang tak pernah datang. Mati ditelan bencana. Hari perkenalan dan lamaran batal dilangsungkan. Entah pula, apakah pernikahan bakal dibatalkan?
Abang pergi setelah air bah menyusut. Mengembara tanpa arah yang pasti, karena tak ada lagi kenangan dan harapan di
Aku tak begitu yakin, itu sebuah jawaban yang telah kaupertimbangkan secara masak. Seperti juga rencana-rencana besarmu. Begitu cepat menderas. Seperti hujan. Seperti tiada batas...
Lampung, Desember 2004—Januari/Februari 2005
10. Pasien Terakhir
AKU pasien terakhir di rumah sakit pusat di Kota B ini. Sudah lebih 50 pasien masuk dan keluar dari ruang pemeriksaan. Aku pasien ke 53 dan mulai masuk ruang pemeriksaan begitu namaku dipanggil oleh petugas.
Sejak pukul 8.30 tadi, aku tak pindah duduk dari bangku panjang di ruang tunngu ini. Setia menanti giliran dipanggil untuk memasuki kamar periksa pasien, meski berulang kuamati jarum jam tanganku. Seperti merangkak, sewaktu mendaki dan tergelincir. Membosankan.
Harus kuakui, aku suka sekali menjalani penantian usai mendaftar dan menyerahkan
“Mau berobat, Nak?” lelaki tua bertanya. Kukira, tepatnya, sekadar bertanya. Ingin membuka percakapan agar tak jengah menanti panggilan dokter. Kulihat kartu yang dipegangnya: nomor 51.
“Bapak juga?” aku balik bertanya.
“Sebenarnya bapak sudah malas ke rumah sakit, berobat. Penyakit bapak amat banyak. Sejak muda dulu bapak sering sakit-sakitan. Tetapi anak bapak yang memaksa agar bapak berobat. Supaya bapak ke rumah sakit. Anak bapak yang mengantar ke sini dengan mobilnya, lalu ia pergi. Nanti siang dia menyusul bapak…”
“Kenapa malas, pak?” aku menyelidik. “Bukankah setiap orang menginginkan sehat? Dan untuk mendapatkan kesehatan harus dperiksa dokter, harus berobat kalau punya penyakit. Saya kira anak bapak tidak salah. Ia benar…”
“Anak bapak benar. Hanya bapak yang sudah bosan ke rumah sakit. Bayangkan bapak harus berobat dua kali sepekan. Belum lagi harus cuci darah sepekan sekali. Bapak terkena gagal ginjal…”
“Kalau bapak tak berobat, bagaimana bapak mau sehat?”
“Sudah bertahun-tahun bapak ke sini, tapi tetap saja penyakit bapak tak hilang. Itulah yang membuat bapak bosan ke dokter. Bapak ingin segera mati…” kudengar suaranya pelan. Pesimistis.
“Bapak tak boleh pesimis begitu. Berobat sama artinya usaha. Tuhan yang menentukan apakah kita akan sehat setelah berobat ataukah…”
“Mati!” Bapak itu menegaskan. “Kalau bapak harus memilih, lebih baik bapak mati saja. Uang sudah habis banyak, penyakit bapak tetap saja. Daripada menghabis-habiskan uang, belum tentu bapak sehat.
“Tak ada keajaiban itu, pak! Yang ada ialah usaha. Kita diharuskan berusaha, dan kalau sudah berusaha belum juga berhasil ya kita serahkan pada Yang Kuasa. Itu sebagai takdir…”
“Kalau takdir, mungkin inilah takdir bapak.”
“Maksudnya?”
“Ya, bapak tak perlu lagi susah-susah ke rumah sakit. Menunggu saja di rumah. Kalau sembuh ya syukur, kalau harus mati ya usia bapak memang sedah pantas…”
“Bapak jangan berkata begitu. Tak baik,” kataku memberi saran. “Seharusnya bapak berdoa supaya diberi umur lebih panjang, sehingga makin banyak punya kesempatan beribadah.”
Bapak tua itu tersenyum. Dipandangnya wajahku penuh heran. Seperti menyelidik, bola matanya seakan menggerayangi diriku. Aku jadi serbasalah ditatap seperti itu. Sedikit menggeser…
“Kau benar, Nak,” tiba-tiba Bapak tua itu berujar. “Tetapi persoalannya, apakah bisa dijamin makin diberi banyak usia oleh Tuhan maka semakin berpeluang bagi kita untuk beribadah?”
“Jangan berkata begitu, Pak? Beribadah itu luas. Kalau tak bisa berdiri, duduk, atau tidur pun dibolehkan…”
“Ah, Bapak akan menambah waktu untuk menyusahkan orang…” ujar bapak tua itu lirih.
“Siapa orang yang Bapak maksud? Anak Bapak?”
Ia mengangguk.
“Itu sudah kewajiban anak. Waktu mereka kecil Bapak yang mengurus mereka. Bapak telah disusahkan mereka. Nah, sekarang tanggung jawab anak yang mengurus Bapak,” kataku. Aku ingin menegaskan bahwa tidak ada yang merasa dibebani untuk mengurus orang tua, apalagi yang sudah jompo.
“Bapak tidak suka dengan cara seperti itu. Itu namanya tidak ikhlas. Kewajiban orang tua adalah mengurus anak hingga besar, tetapi anak belum tentu punya kewajiban yang sama kepada orang tuanya. Karena mereka juga bertanggung jawab pada anaknya. Kalau ia dibebankan lagi untuk mengurus orang tuanya, dua beban yang dipikulnya. Rasanya tidak adil…” jelas Bapak tua itu.
“Ini bukan soal adil atau tidak. Tetapi masalah kewajiban. Soal tanggung jawab dan bakti seorang anak pada orang tua.”
Ah! Bapak tua itu mendesah. “Sayang kau bukan anakku…”
“Kenapa Pak?” aku mengejar dengan pertanyaan. Rasanya menarik untuk kukorek dari balik apa yang diucapkannya barusan.
Bapak tua itu tak menjawab. Ia mengalihkan pembicaraan ke soal penyakit yang kuidap. Kukatakan saja, bahwa penyakitku sudah komplikasi.
“Karena itu, seminggu sekali saya harus ke sini. Mengontrol sekaligus berobat,” kataku kemudian.
“Sudah berapa lama?”
“Kalau daging yang ada di paru-paru saya, sudah setahun. Kalau hepatitis, penyakit sejak kecil.”
“Gagal ginjal?”
“Baru gejala, Pak. Saya berharap bukan, hanya salah diagnose,” jawabku yakin.
Setelah itu, bapak tua itu dipanggil. Ia masuk ke ruang periksa. Setelah bapak tua itu, baru giliranku masuk.
*
DOKTER menahanku untuk pulang. Aku harus diopname. Gagal ginjalku positif. Keluar dari ruang periksa aku tertunduk. Lesu. Bayangan ruang opname yang membosankan akan kumasuki, dan aku akan terpenjara di
Aku baru terdasar begitu bapak tua berdehem. Aku tak menyangka ia masih duduk di kursi tunggu. Mungkinkah ia tengah menanti jemputan anaknya? Aku mendekatinya, menggangguk tanda hormat.
“Kenapa kau tertunduk. Lesu.
Aku mengangguk. “Kata dokter, saya harus diopname. Gagal ginjal saya positif. Juga yang paling mengkhawatirkan daging yang tumbuh di paru-paruku…”
“Oohh!”
“Mengapa Pak tua?”
“O tidak. Bapak hanya tak bisa bayangkan, kau akan merasa bosan dalam bangsal itu. Kau sudah hubungi keluargamu?”
Aku menggeleng.
“Harus segera hubungi mereka. Kau butuh bantuan mereka, mengurusmu selama diopname…” saran Pak tua itu kemudian. Ia memandangku lama sekali. Tatapannya seakan menusuk wajahku.
“Saya tidak punya keluarga di sini, Pak. Saya sebatang kara, setelah istri saya menjadi TKW dan kawin dengan lelaki lain di Johorbahru…” jawabku tenang, setenang hatiku ketika diputuskan dokter aku harus diopname tadi.
“Orang tuamu?”
“Sudah tak ada. Meninggal…”
Setelah itu hening. Aku pamit untuk menuju ruang opname seperti disarankan dokter tadi. Sebelumnya aku mengurus surat-surat masuk di loket lain. Tetapi, Bapaki tua itu tiba-tiba menawarkan diri untuk mengantarku. Aku mengangguk. Kami beriringan menyusuri koridor RS AM ini.
“Bapak sudah dijemput?”
“Mungkin sudah tadi. Tetapi Bapak tidak menunggu di tempat yang dijanjikan anak Bapak. Biarlah Bapak pulang sendiri nanti, setelah kamu masuk ruangan…”
“Anak Bapak pasti khawatir. Bapak akan dicari-cari…”
“Ah, tidak. Sudah biasa,” jawabnya santai. Lalu Bapak itu menambahkan, “Lagipula apa yang dikhawatirkan dari orang seperti Bapak? Mungkin dia malah senang kalau Bapak tidak pulang, dianggap merepotkan saja…”
“Itu perasaan Bapak saja. Bahkan mungkin anak Bapak sangat mengkhawatirkan keadaan Bapak,” kataku membela anaknya.
Bapak tua itu hanya diam. Ia kemudian mendampingiku menuju loket mengurus surat-surat berobat inap, setelah itu mengantarku ke Ruang Melati. Kukatakan padanya, “Bapak boleh ulang. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Tak akan masalah…”
“Kamu punya simpanan uang?”
Aku menggeleng. Entah mengapa aku tak berani berdusta padanya. Di kantongku memang tak ada uang, kecuali kartu ATM yang kuperkirakan berisi 2 juta rupiah! Bapak tua itu tersenyum, menyisihkan dua lembaran 50 ribu rupiah ke saku bajuku. “Ambillah untuk keperluanmu nanti. Bapak sekarang pulang dulu ya…”
Ingin kutolak pemberiannya, tetapi ia berkeas agar aku menerimanya. Akhirnya kubiarkan uang pemberiannya di kantong bajuku. Aku mengucapkan terima kasih, dijawabnya dengan mengangguk. Ia meninggalkan aku sendiri di ruangan opname yang penuh oleh pasien lain.
Aku adalah pasien terakhir di ruang opname Melati ini. Ruang kelas 3 ini dipenuhi oleh pasien, yang entah dari mana. Kecuali, yang kutahu pasti, tentulah kelas masyarakat kebanyakan. Kulihat sejak masuk tadi, para penunggu dan pembesuk menghamparkan tikar dari depan ruangan. Juga, bahkan, sampai di bawah ranjang pasien. Sumpek. Pendingin ruangan tak ada. Pakaian basah berjejer di jendela. Membuat sirkulasi udara semakin terhambat.
*
SUDAH tiga hari aku diopname. Pagi tadi aku harus cuci darah. Besok, kata dokter yang memeriksaku, aku harus diperiksa secara intensif atas daging yang tumbuh di paru-paruku. Tadi dokter hanya memperkirakan bahwa daging yang tumbuh di paru-paruku sudah sebesar jari jempol.
“Kalau masih memungkinkan dioperasi, akan diambil daging itu,” kata dokter tadi. Tetapi, secara samar kudengar dokter itu berdiskusi dengan temannya, bawah mengambil daging yang tumbuh di paru-paru berisiko tinggi. Paru-paru manusia tak jauh beda dengan busa. Jika sesuatu yang ada di
Aku tetap tenang. Bahkan kalau harus menghadapi kemungkinan terberat sekalipun. Kalau sudah sampai waktuku saat operasi nanti, apa yang dapat kuperbuat? Aku hanya pasrah. Orang hidup harus siap dengan segala risiko kehidupan. Apalagi aku tak mewariskan apa-apa: bagi anakku, istriku, atau pun orang tuaku. Aku seperti terlempar di
“Tapi, kau tidak sendiri. Bapak akan selalu membesukmu, menemanimu…”
Aku seperti berada di dalam mimpi, ketika Bapak tua membisikkan kata-kata di telingaku. Ia seperti mengetahui apa yang kupikirkan dan kurasakan saat ini.
“Bapak akan datang setiap pagi ke mari, sampai kamu keluar dari ruangan ini,” sambung Bapak tua itu lagi.
“Bagaimana mungkin, Pak? Bapak sudah tua, nanti malah saya dimaarahi oleh anak Bapak karena sudah merepotkan Bapak,” kataku pelan. Aku tak yakin ini smeua bisa terjadi.
“Anak Bapak yang akan mengantar dan menjemput Bapak ke mari,” katanya kemudian. “Bapak bilang, kalau Bapak harus ke rumah sakit setiap hari. Bapak harus kontinyu memeriksa penyakit Bapak…”
“Padahal Bapak mau ke mari?”
Bapak tua itu tersenyum. Mengangguk.
“Jangan Pak. Bapak telah berdusta…”
“Apakah anakku juga tak pernah berbohong pada Bapak?” sergahnya.
“Biarkan dia mendustai kita, tapi jangan lantas kita ikut-ikutan berbohong,” kataku. Suaraku pelan. Menahan sakit di pinggangku yang terasa melilit.
Ia tak menyahut. Memegangi tangan kananku. Kemudian, seperti kepada orang tuaku sendiri, aku memberi tahu kalau besok aku menjalani operasi pengambilan daging yang tumbuh di paru-paruku. Biayanya 3 juta. Bapak tua itu hanya tersenyum mendengar laporanku. Kini giliran aku yang cemas, psimistis. Sementara ia, di mataku, selalu riang. Optimistis. Itulah yang kutangkap dari cahaya geraknya.
Sebelum pulang, ia meletakkan amplop berisi uang ke balik bantalku. Ia berpesan hati-hati, karena di ruangan yang boleh dibilang amat bebas orang masuk akan mudah pencuri bergerilya. “Bantuan dari anak Bapak, 2 juta!”
Sungguh! Aku tak mampu lagi berkata. Aku kehilangan kata-kata termanis dan terindah untuk mengucapkan terima kasih. Selain, tanpa kusadari, airmataku mengalir. Deras…
Tetapi, Saudara, uang pemberian Bapak tua itu belum kusentuh. Sebab, pada pukul 04.11 sebelum aku salat subuh, Tuhan mengambilku lebih cepat dari kerja para dokter yang akan mengoperasiku siang nanti. Entah, apakah Bapak tua itu kembali membesukku siangnya dan melihatku sudah dipindahkan di ruang mayat, lalu ia akan menanyakan barangku beserta amplop pemberiannya kepada petugas rumah sakit. Ataukah ia tidak lagi datang menengokku?
*
AKU pasien terakhir di ruang Melati ini. Sejak aku masuk ke ruang inap ini sepekan yang lalu, semua ranjang sudah terisi pasien lain. Tetapi, aku orang pertama yang lebih dulu diambil Tuhan…
(RSU Abdoel Moeloek B.Lampung, 18 September 2004; pakai comunicator 9210i)
Lampung, 20 Februari 2005
11. Batu Itu tak Terbang ke Langit
SELEPAS zuhur jenazah selesai dimakamkan.
Ia mengangguk. Tersenyum. Aku berharap ia tak mendendam pada orang-orang kampung yang telah menghabisi nyawa bapaknya. Kami menuruni pebukitan sebagian ladang miliknya di belakang rumah (katanya akan dijadikan pekuburan keluarga). Menyeberangi balong pelihara ikan, meniti jalan setapak dan kemudian menanjak.
Anak almarhum adalah temanku di
Ia pernah bercerita tentang bapaknya. Katanya, sampai usia 50 tahun bapaknya tak juga meninggalkan kebiasaan buruknya. “Siapa pun di kampungku tahu kalau bapakku suka berjudi. Bapak juga sering meminta jatah keamanana di pasar,” ia menjelaskan. Sudah tak terhitung lagi ia meminta agar bapaknya meninggalkan perbuatan buruk itu. Orang yang sudah tua seharusnya tobat dan ingat pada kematian. Tetapi, bapaknya malah tersinggung. Ia didamprat dan diusir oleh bapaknya, bahkan diharamkan menginjak rumahnya. Sejak itu sahabatku itu tak pulang, apalagi ia tak lagi punya Ibu. Dan, kebiasaan buruk bapaknya makin menjadi-jadi. Sudah tak ada lagi yang mengontrol bapaknya. Tak ada yang mengingatkannya. Kelakuan buruk bapak kian berkibar. Tak cuma berjudi, mabuk, dan memalak pedagang di pasar. Bahkan, ia kerap mengganggu janda dan istri orang!
Sebagai anak, ia mengaku, sudah cukup mengingatkan bapaknya. Ia kirim
Ia pun menyerah. Ia mengajakku untuk menemaninya.
Kami berboncengan dengan sepeda motor. Kampung sahabatku itu di balik Bukit Barisan. Tepatnya di Desa Waiheni. Untuk mencapai desa itu dengan waktu yang tak begitu lama, harus menembus taman nasional. Udara pagi berselimut kabut kutembus. Tubuhku dingin. Sepanjang jalan yang menanjak, menurun, dan berliku yang terhampar hanya belantara: hutan penghijauan, hewan yang dilindiungi.
Aku tak hendak membayangkan jika motor kami ngadat di tengah belantara ini. Aku juga tak ingin sering bertanya kapan kami sampai di kampung sahabatku. Meski perjalanan kami sudah dua jam, dihitung pertama kami menaiki Bukit Barisan. Kami tiba di rumah, jenazah masih di pembaringan. Pekuburan sedang digali. Air untuk mandi jenazah sudah disiapkan. Kain kafan pun sudah disediakan.
“Tentulah adik bapak yang menyiapkan semua ini,” bisik temanku. Ia tahu kalau aku hendak bertanya tentang semua itu. “Bapakku hanya punya adik satu, perempuan. Rumahnya setikungan dari sini…”
**
SELEPAS ashar temanku mengajak mandi di Way Bambang. Tiga kolimeter dari rumahnya. Aku setuju. Dengan riang kuterrima ajakannya. Kalau mandi dengan air sumur sudah biasa, pikirku. Sudah lama aku tak mencecapi air sungai. Di
Aku bawa handuk dan sabun. Temanku juga. Namun aku heran ketika melihat ia membawa dua lembar karung bekas beras. Dan aku makin terheran-heran, sesampai di sungai ia memunguti batu-batu di pinggir sungai lalu dimasukkan ke dalam karung. Ketika kutanya untuk apa batu-batu itu, ia jawab dengan enteng, bahwa batu-batu itu –mereka menyebutnya sebagai “batu amal”—digunakan untuk menghitung berapa banyak amal para takziah malam nanti selama tujuh malam. “Satu batu berarti sembilan kulhu. Jadi kalau sebelas batu, berarti 99,” katanya. Ia pun mencontohkan, aku menyimaknya.
Setiap malam seusai takziah, batu-batu yang terpakai akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung khusus. Anak-anak muda akan telaten menghitung dan mencatat di buku. Semakin banyak batu yang terpakai, makin menggembirakan keluarga yang ditinggalkan. Seperti juga ketika jenazah disalatkan, banyak orang yang menyebahyangkan menunjukkan kalau yang mati itu disenangi masyarakat semasa hidupnya. Setelah nujuh hari, batu-batu amal itu akan diletakkan di atas gundukan tanah. Batu-batu di atas makam itulah sebagai simbol berapa banyak amal orang yang berada di dalam kubur.
Aku benar-benar heran. Tapi, ia seperti tahu apa yang ada dalam benakku. Ia segera menjelaskan, kalau itu sudah menjadi tradisi di kampungnya. Sudah bertahun-tahun dan turun-temurun diyakini dari generasi ke genarasi. Orang kampung percaya betul dengan tradisi itu. Mereka yakin sebagai batu amal, batu-batu itu akan terbang ke langit. Lalu meringankan dosa yang mati. Batu-batu amal itu juga akan menjaga si mayat di dalam kubur. Jika makamnya disemen, maka batu-batu itu akan ditabur di tengah-tengahnya.
“Kau bantu aku malam nanti…”
“Maksudmu?” aku tak mengerti.
“Kau ikut membaca alfatihah, kulhu, yaasin, dan zikir. Berapa banyak amal yang kau baca, terlihat dari batu yang kau kumpulkan. Semoga dengan amalmu, dosa bapakku bisa berkurang,” katanya kemudian.
Terdiam. Aku ingin membantah. Bahwa amal seseorang bukan ditentukan oleh batu-batu itu, bukan oleh amal dan kebaikan orang lain. Melainkan oleh perbuatan baiknya sendiri. Tak akan batu-batu itu terbang ke langit. Meminta Tuhan mengurangi barang secuil pun dosa orang yang telah mati. Amal seseorang terputus begitu ia mati, kecuali sedekah ilmu dan doa dari anak-anak yang saleh. Batu-batu itu tetap sebagai bilangan jumlah, berat dalam timbangan. Tetapi, bukan hitungan amal. Bukan pula sakti karena ayat-ayat yang dibacakan untuk menjaga kuburan. Tak.
Tak kurang 75 petakziah duduk bersila di tikar pandan, di pekarangan rumah di bawah langit hitam. Sekitar sepuluh lampu stromking menerangi halaman rumah. Orang kampung yang bertakziah berebut mengambil batu-batu dari karung. Mungkin ada yang 50 kerikil, 25, dan tentu ada yang melebihi 100 batu. Lalu sunyi. Amat hening. Masing-masing bibir petakziah berkomat-kamit, kemudian memisahkan satu batu, dan seterusnya.
Untuk menjaga perasaan temanku, aku pun ikut memisahkan batu-batu yang diberikan di depanku. Aku seakan ikut larut mendoakan almarhum. Aku tersenyum ketika sahabatku menunjukkan tatapan senang yang dikiranya mengikuti tradisi itu. Tetapi, aku amat percaya, orang yang membaca quran walau hanya seayat akan mendapat pahala. Dicatat Tuhan sebagai kebaikan.
Malam pertama takziah terkumpul batu amal dua ember. Malam berikutnya hanya satu setengah bakul kerendon. Pada malam ketiga hanya satu berunang, dan malam berikutnya terkumpul hampir dua ember. Malam ketujuh terhimpun dua setengah ember. Total selama nujuh hari takziah, batu-batu amal terkumpul sepuluh ember. Batu-batu amal itu pada hari ke delapan diletakkan di atas makam almarhum.
**
SELEPAS zuhur kami pamit dengan orang kampung untuk kembali ke
Beberapa kali ia pandangi rumahnya yang nyaris punah karena dirusak
“Sudahlah,” kataku. “Tak baik lama-lama bersedih. Kita dilarang meratapi kematian,” lanjutku di atas motor. Sebentar lagi kami akan masuki hutan lindung.
“Aku tidak bersedih karena bapakku mati,” jawabnya dengan suara tersendat. “Aku hanya kecewa, kematian bapakku tak bisa mengundang lebih banyak lagi ornag yang bertakziah. Apakah karena bapakku penjahat? Apa karena kami bukan keluarga terhormat ataupun kaya?”
“Apa maksudmu?”
“Di kampungku, keluarga terhormat dan kaya akan dihormati. Bahkan sampai mati pun, orang akan berduyuun-duyun melayat dan bertakziah. Sehingga makin banyak batu amal yang bisa terkumpul. Tetapi, bapakku? Kau sudah melihat sendiri bukan? Hanya sepuluh ember selama nujuh hari! Keterlaluan. Aku benar-benar kecewa,” dia melanjutkan. “Sekiranya aku punya duit akan kubayar orang kampung untuk datang bertakziah…”
“Untuk apa?”
“Untuk mengumpulkan batu-batu amal,” jawabnya singkat. “Aku malu kalau ada yang melihat makam bapakku, dan mendapati batu-batu amal hanya sedikit. Aib bagi keluargaku jika ia bercerita kepada orang lain…”
“Jadi…”
“Makanya aku menambah dengan batu-batu yang tak terpakai, tetapi kukira masih sedikit,” katanya. Sepertinya ia khawatir terdengar orang lain atau karena ia sedih dan kecewa sehingga suaranya sangat pelan.
Temanku tak akan pernah tahu, kalau aku di depannya kini tersenyum-senyum. Sebab setiap malam aku mencomot tiga sampai empat tumpukan batu, kemudian kuakui sebagai jumlah amalku. Ditambah lagi sebelum ke makam bapaknya pagi tadi, aku telah mencuri setengah karung batu tak terpakai para takziah, lalu kucampur dengan batu amal lain. Dan sepuluh ember batu itulah yang kemudian ditabur di atas gundukan kuburan almarhum. Batu-batu yang tak akan terbang ke langit…
Wayheni Lambar 13 Juni—Bandar Lampung 21 Juni 2005
Catatan:
Way Bambang (Sungai Bambang) ada di Dewa Wayheni, Bengkunat Krui, Lampung Barat. Dinamakan sungai Bambang karena ada cerita di zaman dulu bahwa sungai itu kerap membambangi atau menghanyutkan orang dan benda lainnya. Ingat sebambang yang berarti melarikan.
Nujuh hari, tradisi ini masih berkembang di sebagian muslim. Namun dalam konteks cerita ini, tradisi menggunakan batu kecil yang diambil dari pinggir kali (batu kali) saat membaca ayat dan doa pada malam takziah untuk menghitung jumlah amal maka disebut “batu amal”, sudah berlangsung turun-temurun—terutama di Desa Wayheni, Bengkunat, Lampung Barat.
12. Perempuan di Ladang Tebu
BULAN sepotong menggantung di pucuk-pucuk daun. Ladang tebu sekitar 250 ribu hektare tak lagi kelam. Bagai pasar malam. Orang-orang berkumpul di sana
Batang tebu yang telah tua disisihkan ke pinggir jalan, kemudian diikat jadi satu setelah ditimbang per-10 kilogram, sebelum diangkut oleh truk untuk dibawa ke pabrik. Sementara tebon atau helai-helai daun tebu dibiarkan menggunung di tengah ladang, sebelum dijual ke para peternak.
Begitulah. Setiap musim tebang setiap buan April selama kurang lebih enam bulan, di ladang tebu itu tak cuma buruh pabrik yang bakal berpesta. Tapi para penebang, pedagang, dan tukang kredit!
Sejak pabrik gula putih itu beridiri sepuluh tahun lalu, diakui atau tidak banyak yang diuntungkan. Pengangguran bisa diperkecil karena para pemuda di sekitar ladang tebu dipekerjakan. Begitu pula masyarakat di sekitar ladang tebu, dibolehkan berdagang atau membuka bank jalan dan tukang kredit saat musim tebang hingga masa tanam. .
Musim tebang biasanya akan usai enam bulan. Setelah itu penanaman bibit kembali, biasanya memakan waktu dua atau tiga bulan. Otomatis para buruh berada di ladang itu bisa delapan atau sembilan bulan. Itu sebabnya, mandor ladang seperti membiarkan warung-warung penganan bermunculan di
Meski cahaya bulan tak begitu benderang, tak membuat keriuhan di tengah ladang tebu itu memudar. Bahkan, menurut sejumlah buruh di
para buruh bisa mencuri waktu istirahat atau menambah sedikit waktu untuk berkencan dengan penjaga warung.
Suara radio batere empat band terdengar saling bersahutan dari warung-warung penganan. Di beberapa warung berada paling ujung, bahkan menyetel lagu-lagu Barat: seperti bertikai dengan cahaya lilin.
Mira, penunggu warung penganan, perempuan tercantik di ladang tebu tampak tak acuh dengan keriuhan di situ. Ia asyik dengan pekerjaannya: membuat tapis 1). Sudah dua lembar (kain) tapis ia selesaikan selama musim tebang, yang dia kerjakan di sela-sela melayani pembeli. Mira yang ditemani putri satu-satunya yang sudah berusia 13 tahun itu, membuka warung penganan di
Hidup menjanda di tengah-tengah buruh di ladang tebu, bagi Mira bukan tak berisiko. Pendengarannya yang masih normal acap mendengar bisik negatif para lelaki di
Pernah suatu malam, beberapa buruh tebang mendekati kamar tidurnya yang terbuat dari geribik. Waktu cuaca sangat panas. Ia dan Midah hanya mengenakan pakaian tipis, dan itu pun setengah tersingkap. Sungguh ia tak mengira kalau itu mengundang para buruh untuk menyatroni rumahnya. Mendengar desahan di luar, ia ambil bantal dan melemparnya ke dinding. Lalu, terdengar gemuruh langkah yang menjauh. Keesokan pagi, ia marah besar.
“Kopi ah…” Chairil, salah seorang buruh tebang duduk di sisi kiri warung. “Jangan terlalu manis ya?”
“Memangnya pernah kemanisan, Yai?” Mira menyela.
“Kemarin. Seperti kolek….”
Mira tersenyum. “Maaf, Yai. Enggak akan lagi…”
“Ngelamun kali… Siapa sih yang dilamunin?” Yudi, buruh lain, menimpali. “Makanya kalau lagi melayani orang, pikiran jangan bercabang…”
“Ah, enggak apa-apa. Sekali-kali biasa melakukan kesalahan. Perempuan yang berpengalaman masak pun, pasti masakannya pernah gosong,” ujar Chairil. Tersenyum. Mira mengangguk. Menunduk.
Midah ke dapur membawa gelas dan piring kotor dari meja depan untuk dicuci. Tak lama ia sudah kembali dan membantu Mira membuatkan kopi untuk para buruh. Seperti hari-hari lalu, warung Mira paling banyak didatangi pembeli. Seperti memiliki jimat, begitu isu yang tersebar. Mira tak segan-segan menyervis istimewa pembelinya, demikian isu lain menyebar. Tapi, Mira tak pedulikan fitnah itu.
Chairil, pemuda asli dekat pabrik gula itu, yang memilih bekerja sebagai buruh daripada menuntut perusahaan soal ganti lahan yang digunakan ladang tebu. Untuk apa protes meminta ganti rugi, kalau hanya menguntungkan para petani berdasi? Ya. Sejak masyarakat dekat ladang tebu itu protes atas penyerobotan lahan ulayat, tiba-tiba banyak petani berdasi bermunculan dan mengaku punya hak waris pula dari ladang itu. Mereka inilah yang siap menjadi negosiator dengan pengusaha pabrik. Asal bagi hasil.
Tetapi, setelah berhasil, hanya sedikit yang mengalir ke tangan pemilik lahan. Yang lain dikantongi negosiator ke
“Pekerjaan sia-sia…” kata Chairil suatu hari. Namun, sejak itu Chairil dimusuhi masyarakat. Ia pernah nyaris dihakimi
Untunglah Mira menolongnya. Ia dibopong Mira dibantu oleh Midah dan seorang buruh masuk ke dalam warung dalam keadaan tak sadar. Setelah sadar Chairil hendak membalas, namun Mira mencegah.
“Untuk apa membalas dendam? Mau mati dikeroyok?” ujar Mira. “Kalau musuh tak berotak, mestinya dilawan dengan akal…” Mira menambahkan.
Chairil terdiam. Perempuan ini begitu arif. Tuturnya lembut, hati-hati, dan setiap ucapan mengandung akal pikiran yang jernih. Alangkah bodohnya lelaki itu kalau mau meninggalkan perempuan seperti Mira. Chairil menerawang…
“Minum tuh kopinya, kalau dingin enggak enak lo!” Atie, karyawati pabrik gula, tiba-tiba berada di sisi Chairil. “Kok melamun terus, seperti seniman?”
Chairil memandang Atie. Perempuan ini lagi, gumam dia. Atie, menurut Chairil, penyebab ia dibenci tetangga. Atie kecewa karena cintanya ditolak bujang ini, lalu membuat cerita kepada masyarakat di
“Kok diam aja?” Atie berujar lagi.
“Kau lihat sendiri aku lagi makan?” Chairil ketus. Atie senyum. Kemudian beringsut ke warung sebelah. “Kalau aku jadi dia, malu aku menemui orang yang telah kucelakaan!” Chairil berujar setelah Atie menjauh.
“Mas Chairil
**
BULAN sepotong menggantung di pucuk-pucuk daun tebu. Suasana di ladang tebu itu masih sepi. Para buruh tebang belum selesai mengambil upah di depan kantor mandor. Mira ngelangut di depan pintu warungnya. Menatap ke tengah ladang tebu yang agak kelam. Pecahan cahaya rembulan yang jatuh di pucuk-pucuk daun tebu, bagai sapuan sebuah lukisan nan indah.
Sudah lama Mira ingin membunuh kesendirian. Mira ingin kembali merengkuh kebahagiaan bersama suami yang mau mencintainya. Tidak seperti Sapto, pikir Mira, lelaki itu benar-benar pengecut. Tak bertanggung jawab. Sebelum menjadi TKI di Malaysia , ia Malaysia
“O, pedih hati ini rasanya dikhianati!” desis Mira. Itu ia keluhkan setiapkali mengingat Sapto. Seperti saat ini, ketika para TKI diusir atau dihukum cambuk oleh Pemerintah Malaysia
Tapi, setiap kali Mira mengungkap kebenciannya kepada Sapto, Midah datang sebagai penyejuk. “Tak baik menanam dendam seperti itu. Ibu pernah bilang padaku berbuatlah baik pada siapa pun, meski orang itu membencimu. Iya
Mira tersenyum. Melirik Midah yang asyik menyulam tapis di depan tape radio empat band. “Kenapa tersenyum, Bu?” tanya Midah. “Ayo, ada apa?
“Ah, tidak,” jawab Mira ringan. “Sebaiknya kau tidur duluan, kau capek seharian bekerja. Istirahatlah. Besuk kau harus bangun pagi lagi,
“Sebentar lagi, Bu. Pekerjaanku masih tanggung.”
“Ah, kamu selalu begitu. Tak mau berhenti sebelum selesai pekerjaan.”
“Ibu mau nungggu…”
Mira menggeleng. Tersenyum. Mengurai rambutnya. “Om Chairil langsung ke Menggala, mau menengok orang tuanya. Begitu katanya sebelum mengambil upah tadi sore.”
Midah mengangguk. Hatinya merasakan kalau ibunya menyukai Chairil, pemuda asal Bakung yang kemudian pindah ke Menggala seusai pengeroyokan dulu. Hanya ibunya enggan mengatakan itu padanya. Padahal, Midah akan menyetujui ibunya jika ingin berkeluarga lagi. Apalagi dengan lelaki yang ia tahu pribadinya baik.
“Om Chairil bilang begitu sama ibu?”
Mira mengangguk.
“Ibu yang tanya?”
“Ya.”
“Ibu senang dengan om Chairil?” Midah bertanya lagi. Kali ini sangat hati-hati. Ia khawatir kalau ibunya tersinggung.
Mira mengangguk. “Ia sangat baik kepada kita, pantas kalau ibu menyenanginya…”
“Cuma senang?”
Mira menggeleng. “Ibu juga menyukai perilakuknya, sikapnya, kebaikannya. Ia baik, suka menolong kita…”
“Cuma itu, Ibu?”
“Ya. Ia juga suka menolong kamu mengambilkan air untuk mencuci piring,” kata Mira kemudian.
“Itu aku tahu, Ibu,” sela Midah. “Midah cuma ingin tahu, apa ibu juga men…”
“Ibu memang selalu menunggu om Chairil. Kalau dia di ladang tebu ini, ibu merasa terlindungi,” potong Mira. “Sudahlah, Midah tidur duluan. Sudah malam. Biar ibu saja yang menutup warung.”
“Bukan itu maksud Midah. Apa ibu mencintai om Chairil?” Midah menegaskan.
Mira mengangguk cepat. “Hanya mencintai, karena ia pantas kita cintai. Ia amat baik.”
Ah! Midah ingin menegaskan kembali kepada ibunya, bukan itu yang ia maksud. Ia ingin keterusterangan Mira, apakah ibunya mencintai Chairil sebagai perempuan dengan lelaki? Ingin menjadikan Chairil pengganti ayahnya? Hanya pertanyaan itu tak juga ia ucapkan. Midah kahwatir ibunya akan malu, atau malah tersinggung?
“Ibu mengerti apa yang ada di dalam pikiranmu. Tapi, ibu tak ingin mengatakannya itu sekarang. Kamu masih terlalu kecil untuk tahu masalah itu,” ucap Mira setelah membiarkan beberapa jenak hening. “Sudahlah, sebaiknya kau tidur. Kamu kelihatan capek sekali.”
Midah melipat kain tapis dan meletakkannya di meja, sementara jarum dan benang ia simpan di kotak khusus dan ia simpan di lemari pajangan rokok. Ia bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke kamar tidur.
Malam terus merangkak. Sepotong bulan persis di atas ladang tebu. Cahayanya menyiram peladangan yang tengah musim tebang. Mira mengetatkan baju dinginnya. Malam berparas kelam. Ladang membentang misteri.
“Aku tak ingin mengecewakan Midah. Ia sangat berharap Chairil menjadi ayah tirinya,” Mira menggumam. Midah tak akan pernah tahu, ibunya tak mau mengkhianati nurani perempuan. Chairil bukan ke rumah orang tuanya, tapi ke Bandarjaya. Malam ini ia menikah, begitu kata Chairil. Entah apakah ia akan tetap menjadi buruh tebang di sini setelah berkeluarga, atau bekerja di tempat lain.
“Tapi, kita akan tetap di sini, di tengah ladang tebu. Membuka warung bagi para buruh tebang, meski tak ada lagi Chairil…” bisik Mira seraya membelai rambut putrinya yang terlelap.
Bulan sepotong rebah di dadanya. Ingin menikmati pula desir angin di daun tebu, seperti nyanyian rindu.
Lampung, Agustus—September 2002
13. Ruang Asap
Ibu lima
diperkirakan karerna terlilit ekonomi dan penyakit darah tinggi
yang tidak sembuh-sembuh.
(“Patroli” Indosiar, 9 Oktober 2002)
HIDUP begitu singkat dan sepertinya mudah dia selesaikan. Mungkin tak pernah terbayangkan selama hidupnya bakal mengikat lehernya dengan tali di atas tiang kaso rumah. Tetapi, pagi buta itu, ia lakukan apa yang tak pernah ia bayangkan itu.
Malam larut berparas legam. Udara dingin, angin di musim kemarau tahun ini begitu kencang berembus. Kelima anaknya sudah terlelap dengan mimpi-mimpi indahnya. Mungkin mimpi tertidur di kasur empuk di sebuah apartemen mewah. Atau mimpi mengelilingi kota
Ah, di mana engkau Parman? Tiada di sebelah. Lelaki paro baya itu tengah bertugas sebagai satpam di toko. Dingin. Gigil tak terbagi. Senyap. Mengetatkan bajunya, mengangkat tinggi-tinggi kain sarungnya. Angin menembus tubuhnya. Sebatang rokok membunuh kantuknya. Tapi, tak pula mampu mengubur gigil.
Pukul 04.00 pagi. Parman beringsut meninggalkan tempat kerjanya. Aman. Tak ada penjarah apalagi perampok yang datang kemudian mengancamnya dengan mengikat kedua tangan dan kakinya di pagar besi toko itu. Tak. Dan, tak pula ia inginkan nasib seperti itu.
Parman menyusuri gang di perkampungan kumuh menuju rumahnya. Aroma keringat khas istri dan dengkur kelima anaknya, seakan mengusik. Ah, alangkah nikmat aromanya. Alangkah indah dengkur mereka di telingaku. Gumam. Ia melangkah agak cepat. Angin menembus kulit tubuhnya.
Pintu terkunci. Malam kian menghitam. Sunyi. Bulu di kuduk Parman tiba-tiba berdiri. Ia ketatkan kain sarung. Ia nyalakan sebatang rokok, tapi hanya sekali isap kemudian rokok yang baru terbakar sedikit itu ia empaskan di tanah. Kaki kirinya memelintir hingga remuk-redam 1), setelah itu ia membuka pintu rumahnya.
Dan, alangkah terkejutnya ia. Iyah, istrinya, sudah kaku tergantung di tiang kaso dengan lidah yang menjulur keluar. Kiranya maut demikian akrab. Setinggi itukah ia atas dirimu 2), Iyah? Lalu, terisak. Lalu, menjerit membangunkan anak-anak. Suaranya bagai kentongan bagi orang kampung yang menandakan adanya bencana. Puluhan warga menyerbu rumahnya. Menurunkan Iyah. Parman tak bisa berbuat apa-apa selain tepekur di lantai: kenapa Iyah begitu cepat mengakhiri kekecewaannya?
Anak-anak terisak. Matanya lembab. Rambutnya berkerudung, sementara di tangannya kitab suci. Baru saja mereka menamatkan
Sebentar lagi Iyah dimakamkan. Sebentar lagi Iyah akan didatangi malaikat yang ditugaskan Tuhan di alam kubur. Setelah itu, setelah para pelayat pergi dari pekuburan, bagaimana peristiwa di
Aku, seperti juga para pelayat lain, meninggalkan pekuburan umum itu.
“Iyah… Iyah…”
*
TAK pernah terbayang sebelumnya, aku bakal berada di ruang penuh asap seperti ini. Lampu temaram. Sejumlah meja penuh botol yang menyebarkan aroma alkohol. Orang-orang berjoget. Gemuruh musik. Berdebam-debam.
Kenapa aku bisa berada di sini? Ah! Kenapa pula si
Laut akan membawa anganku berlayar ke mana kamu suka. Perahu akan melayarkan imajinasimu jauh ke tengah lautan. Memetik lampu-lampu yang mengusik setiap pelayar. Perempuan teman si
Aku naik mobil
Ah, perempuan itu lagi yang menggodaku. Kenapa pula? Menarikkah? Menggairahkan? Mungkin. Mungkin? Ya! Kupikir hanya soal selera dalam memandang seorang perempuan. Bisa saja aku tergoda, terusik, tergiur? Tetapi, bisa saja, Anda tidak? Beni mungkin asyik berada di sisi perempuan yang kemudian kutahu dari
Nora? Bukan Nora plus k? Tampaknya memang pas, kalau Nora yang satu ini ditambah huruf “k” di akhir namanya. Dia memang Norak. Sungguh. Lisptiknya merah menyala. Begitu mencolok. Jangan-jangan untuk mengelabui mata yang melihat, kalau bibirnya sudah penuh nikoten?
Laut hanya sejenak menggodaku. Pantai cuma sesaat menerpa anganku. Selebihnya gemuruh ombak yang menampar tepi pantai. Ah, tidak! Mesti aku ralat sebelum aku telanjur berdusta lagi. Aku tidak pernah mendengar riuh ombak yang berlari-lari menuju tepi pantai. Aku tengah mendengar dentum musik, yang sebenarnya tak kuterima.
Tetapi, kau sudah ada di sini. Di ruang penuh asap. Lampu temaram. Gemuruh musik yang berdebam. Dentuman bas. Orang-orang berjoget bagai ikan yang berkelepar-kelepar karena kekuarangan air di dalam akuarium.
Si Beni menggoyang-goyangkan kepala. Herman asyik-masyuk dengan irama musik. Dua butir pil, mungkin lebih, sudah masuk ke mulut kedua anak itu. Tadi aku juga ditawari. Aku tolak. Aku sudah mabuk dengan banyak persoalan hidup ini, untuk apa mabuk lagi oleh benda itu? Kataku setengah tertawa.
Si Beni maklum. Ia tahu, bahkan ia kerap mengejekku sewaktu di SMA, aku anak emak. Zali malah menyebutku “orang sufi”. Ah, tahu apa Zali dengan orang-orang suci? Eh, ke mana mantan wartawan itu? Kabar terakhir yang kuketahui, dia sudah jadi pengacara politikus yang kini sedang melirik kursi gubernur! Bisa kubayangkan politikus yang sehari-hari pengusaha dengan beban sarat oleh berbagai jabatan di tubuhnya, mampu memimpin provinsi ini? Apa provinsi ini mau dijadikan wilayah preman?
Zali, menurutku, terjebak oleh permainan si bajingan Izar itu. Cuma, mau apa lagi? Ia sudah kecewa dengan profesi wartawannya. Ia punya keahlian, sarjana hukum. Pikirnya, kenapa tidak aku manfaatkan saja? Bukan karena ingin menegakkan kebenaran. Terlalu abstrak bicara kebenaran di zaman yang carut-marut seperti ini, kata Zali lagi. Si Beni mengangguk-angguk, tertawa, ketika kuceritakan alasan Zali menjadi pengacara si gila jabatan itu. Tepatnya bukan pengacara, tapi melindungi Izar.
Kenapa kau tertawa,
Itu pilihan bagus.
Musik berdentam. Di ruang ini, aku pernah membaca di media daerah, Hidayat terjebak. Orang-orang partai tertangkap. Anggota Dewan diseret ke kantor polisi. Di ruang penuh asap ini? Sekarang aku berada di sini. Menikmati suasana tak sedap. Tetapi, kapan
Ruangan ini tak memberi tanda waktu. Untung aku membawa jam. Kudekatkan mataku melihat jarum pendek di arlojiku. Jam 05! Gila! Sepertinya irama waktu tak mencapai ruang pengap penuh asap ini. Orang-orang sudah melupakan detik menit dan jam! Orang-orang sudah seperti berada di luar angkasa. Tiada lagi perlu waktu. Juga rumus ilmu tentang apa saja. Uang mengalir ke dalam kas bar. Ke saku perempuan-perempuan itu.
Ruang makin mengabut oleh asap. Aku terbatuk-batuk. Aku seperti tidak berada di dalam sebuah ruangan mewah, tapi di dalam kubur. Benar. Aku bertemu Iyah, perempuan
Iyah… Iyah…
Iyah… Iyah…
Mungkin ini pengalaman pertamaku masuk ke dalam ruang penuh asap. Lampu temaram. Aroma alkohol dimuntahkan dari puluhan botol di meja. Orang-orang kesurupan di bawah bias lampu. Dentuman musik kian memekakkan telingaku. Si Beni asyik merapat-rapatkan bibirnya, entah ke mana, soalnya suasana ruangan yang gelap dan pengap ini orang tak bisa jelas melihat seseorang atau pun sesuatu. Karena itu pula, aku tak pernah akan percaya aparat polisi bisa menemukan pil ekstasi di ruangan seperti ini. Kecuali cuma lawakan dari pihak kepolisian…
Dasar bajingan!
*
ASU? Aku teringat si Djenar yang suka disebut monyet, atau kadang minta disapa asu. Aku heran kenapa dia mau begitu. Memang dia aneh, lucu, atau jangan-jangan sakit? Ah, Hudan sudah lama menjadi orang sakit. Tepatnya, ia menginginkan keluarga sakit. Masyarakat sakit. Lihatlah orang-orang sudah mengidap penyakit: aids, gila, dan entah apa lagi. Sampai ke gedung-gedung dewan, birokrasi, dan Presiden Negeri Anuland. Kata Hudan suatu malam.
Jadi benar kalau Djenar menyebut dirinya monyet atau asu. Memang orang-orang kini, seperti kata kitab suci, bahkan polahlakunya lebih rendah dari binatang! Saksikan film-film porno, saksikan saja para anggota Dewan dan MPR dan birokrat dan pejabat negara. Toh semuanya sudah sakit? Hanya mementingkan diri sendiri, menangguk kekayaan untuk menumpuk harta di rumahnya. Padahal nasib para transmigran yang sial di
Iyah,
“Karena rasa haru dalam dirimu telah lenyap, itulah yang menyebabkan aku tak lagi mencintaimu…” kata sang kekasih dan meninggalkan Musolini terpana sendiri.
Iyah. Iyah. Kau pergi juga meninggalkan rasa haru. Kau selesaikan hidup ini dengan cepat dan nekat. Sepertinya kematian begitu akrab padamu. Tidak. Bukan karena dekat, tetapi melawan takdir. Ingin cepat-cepat merebut maut…
Perbuatan asu! Tak tahu diuntung. Diberi anak
Ya. Betul. Pemerintah itu memang asu,
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet.
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet.
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet.
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet.
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet
Asu Monyet Asu Monyet Asu Monyet. Asu Monyet. Asu Monyet
A s u
M o n y e t
Nah, itu dia asu, itu dia monyet! Di bawah remang lampu di dalam ruang berasap banjir aroma alkohol. Ia saling menggosok-gosokkan kemaluannya sambil saling menggigit bibir. Dasar binatang! Di mana saja, dalam waktu apa pun, menerjemahkan syahwatnya dengan syahwat. Mengumbar nafsunya dengan nafsu yang lain.
Kematian…
Tentang kematian karena sakaw, aku teringat dengan dua pemuda dekat rumahku. Sebut saja Henda dan Angga. Yang satu mati di pinggir toko karena ia tak punya rumah lagi setelah ia jual. Untung ia punya adik yang sudah bekerluarga, lalu jenazah yang sia-sia itu dikebumikan dengan sebuah prosesi. Sedangkan yang stau lagi, Angga, tewas di rumah sakit. Untung ia cepat-cepat kabur dari tahanan dan masuk ke rumah sakit. Kalau tidak, hanya mautnya yang kabur dari ruang tahanan.
Angga tidak dituntut karena melarikan diri. Polisi tak mungkin bisa menuntut jenazahnya untuk disidangkan, kemudian dipenjara beberapa tahun. Bisa-bisa busuk seluruh ruangan tahanan. Tetapi, sialnya, jelang sebulan kemudian, ayahnya ditangkap aparat kepolisian karena ketahuan sebagai penjual putaw. Dasar keluarga gila!
*
RUANG penuh asap, di sebuah kapal penumpang Tanjungpriok—
Iyah menatapku. Seperti kesal pada rokoknya yang belum juga menyala. Ia buang kotak korek api ke lantai yang sebenarnya masih terisi banyak, lalu sepatu kanannya menginjak hingga remuk redam. Kubiarkan.
“Punya api? Korek sialan!” kata Iyah.
Aku menggeleng. “Aku hanya punya korek ini. Kalau kau gerakkan roda ini dengan jempolmu, maka timbullah api…”
“O iya, maksudku, korek,” katanya santai. Tersenyum. Menggoda. “Tetapi, api tak pernah timbul dari korek ini. Maksudmu, mungkin menyala?”
Skor sama: satu satu. Aku bergumam. Gila. Ternyata seorang ayam di depanku ini, lain daripada yang lain. Pintar. Tak mau kalah. Ibarat pemain bulutangkis atau volly ball, smashannya akurat. Langsung mengena muka.
“Ya, itu maksudku. Tetapi, bisa saja timbul lo api, misalnya, api yang tiba-tiba timbul dan membakar hutan…”
“Salah. Yang bener muncul,” kata seorang ayam itu lagi tak mau kalah. “Sudahlah, untuk apa kita persoalkan yang sepele itu. Kayak para politikus kita saja, suka membesar-besarkan yang kecil dan menghapus persoalan yang besar!”
“Tahu apa kau dengan politik?”
“Menghina ya?” Iyah memelototkan matanya. “Gini-gini dari keluarga politikus. Tetapi, sudahlah, aku enggak suka menyoalkan politik. Lagian lebih nikmat mengisi perjalanan ini dengan hal-hal yang indah dan memesona. Bagaimana, Anda setuju?”
“Untuk sementara aku belum setuju. Aku masih menikmati kesendirian. Aku baru saja membaca seorang perempuan
“Bagus itu, bagus…”
“Bagus apa?” kataku tak mengerti. Iyah memandangku. Tersenyum.
“Berita tentang anggota DPR yang mati karena overdosis itu. Buat pelajaran anggota Dewan yang lain…”
“Pelajaran?” tanyaku. “Enggak salah, itu sudah yang kelima kali anggota Dewan mati di tempat hiburan!”
“Haa?? Itu sih belum banyak. Anggota Dewan
“Hustts. Kau anggap maut identik seleksi? Sama saja kamu mendoakan orang celaka. Tak baik,” kataku segera agar perempuan di depanku tidak jauh ngaco.
“Mendoakan celaka buat orang yang buruk, pahalanya besar!” kata Iyah bergurau.
“Tahu apa kau dengan pahala? Lagian dari pengajian mana kau dapatkan itu?”
“Dari pengajian sendiri. Artinya, mereka-reka alias menafsir-nafsir saja…”
Dasar gila! Gumam. Tetapi, itu didengar Iyah. Ia protes minta aku mengulangi gumamanku itu. Aku tak mau. Berkeras tetap tak mau. Biar ia paksa. Aku juga tidak sengaja melontarkan kata itu. Cuma aku tak mau meminta maaf. Apa perlu minta maaf, aku tidak salah. Pikirku. Perempuan di depanku ini juga bukan kawan lamaku. Kukenal baru saja beberapa menit barusan. Aku baru tahu namanya: Iyah. Yang lainnya tidak tahu atau aku memang tak mau tahu. Aku hanya mengira kalau Iyah adalah ayam alias perempuan pekerja seks komersial alias wanita tuna susila alias pelacur! Aku tak tahu apakah masih ada alias yang lain.
Ayam, di kapal penyeberangan Tanjungperiok—Belawan (
Aku pernah tak berteman, rasanya tersiksa. Akhirnya sepanjang waktu aku mendekam di kamar. Kalau bosan aku menuju ruang bawah yang ada bioskopnya. Menonton film berkali-kali. Sampai bosan. Naik dan mengunci kamar lagi. Malam hari aku ke bar, minum-minum, dan menikmati musik. Pukul 00.00 bar tutup. Masuk ke kamar. Membosankan bukan?
Seperti kali ini. Aku tengah membunuh kebosanan di dalam kamar sendiri. Aku memilih kursi paling sudut. Memesan minuman. Iyah lalu datang dengan alasan meminta api. Uhh! Aku tergoda. Ngobrol basa-basi seperti yang kuceritakan tadi. Dari soal meminjam api akhirnya melebar ke politik, anggota Dewan yang tewas karena OD, Hudan yang sakit, Djenar yang suka disapa asu atau monyet! Kok, jadi tak beraturan perbincangan?
Begitulah kalau dalam perjalanan bertemu teman baru. Basa-basi yang juga habis dengan basa-basi. Seperti kau ketika berada di sebuah terminal lalu naik bis dan bertemu seseorang dan dilupakan begitu kau turun. Sebagaimana butiran embun di daun talas yang lesap begitu matahari terbit. Ya! Seperti hidup ini, amat fana…
Iyah mendekatkan mulutnya ke telingaku. Musik berdentum-dentum. Tak begitu jelas terdengar Iyah ngomong begini: “Sendiri? Boleh aku temani malam ini? Aku juga sendiri. Kesendirian membuat kita kesepian. Kesepian apa yang paling menjemukan? Tidak ada teman ngobrol. Dan sekarang, dalam perjalanan ini, aku amat sangat merasakan itu. Bagaimana kau?”
“Biasa saja,” kataku menghindar. “
“Kayak seniman saja. Kamu pengarang? Maksudku kamu sastrawan, itu lo yang suka menulis puisi, cerpen, atau novel?” Iyah bertanya. Rupanya, perempuan di depanku, bukan perempuan sembarangan. Setidaknya ia tahu sastra. Apakah ia jebolan PT? Aku tak yakin kalau ia hanya tamatan SMU, soalnya anak-anak SMA sekarang sangat buruk pengetahuannya tentang sastra!
“O bukan. Saya orang biasa saja. Seperti Anda.”
“Anda? Ah, terlalu berjarak kita. Bagaimana aku usul kau memanggilku cukup Iyah atau ‘dik’ biar obrolan kita lebih akrab.”
“Oke,” jawabku. “Aku lebih suka memanggilmu Iyah. Dik rasanya terlalu mengikat, padahal kita baru saja berkenalan. Belum dua jam…”
Please. Please.
“Tetapi, banyak orang menyenangi teman perjalanan. Kadang tak mau jalan kalau tidak ditemani, apalagi memerlukan waktu sangat lama seperti sekarang. Teman perjalanan kadang juga membantu,” kata Iyah memulai percakapan lagi.
“Boleh jadi pendapat Iyah benar. Cuma saya punya pengalaman pahit pada teman dalam perjalanan. Teman saya itu bukannya membantu ketika saya diancam preman. Ia malah ketakutan dan ngacir ketika uang dan jam tangan saya dipreteli. Kesempatan lain, waktu saya ke luar negeri, teman saya itu malah menyusahkan. Dia nekat masuk bandara di
“Ya, tapi tidak setiap teman seperjalanan akan merepotkan,
“Tetapi, saya sudah traumatik.”
“Itu sebabnya pertama kali aku datang ke meja ini, kau mencurigaiku?
Aku mengangguk.
“Sekarang sudah tidak lagi,
“Saya belum berani menjawabnya sekarang. Toh, perjalanan kita belum sampai tujuan? Jadi, bagaimana bisa aku simpulkan apakah Iyah bakal menyusahkanku ataukah malah membantu.”
“Kita akan memperoleh apa yang kita pikirkan atau inginkan. Kalau kau menginginkan saya berguna dalam perjalanan ini, pasti akan berguna. Sebaliknya, kalau kau berpikiran saya bakal menyusahkan ya itulah yang kau dapatkan,” ujar Iyah.
Oke. Oke. Ini orang cerdas sekali, pikirku. Tetapi, kenapa ia sendiri dalam perjalanan ini?
“O iya, aku lupa. Iyah sendiri dalam perjalanan ini? Mau ke mana?” tanyaku kemudian.
“Saya juga punya pengalaman pahit sepertimu. Hanya kemudian saya hapus kenangan pahit bersama teman perjalanan. Lalu, saya dapatkan apa yang saya harapkan. Saya banyak mendapat teman justru di saat perjalanan ini. Dan, itu ternyata banyak membantu…”
“Itu tendensius namanya! Mencari teman karena mengharap keuntungan! Tidak benar itu!!” tandasku.
“Tidak tendensius, kukira. Hanya akibat dari suatu pertemanan. Apa salahnya? Bahkan, sebenarnya lebih banyak aku yang menolong mereka…”
“Pertolongan apa itu?” tanyaku ingin tahu.
“Tak baik kusebutkan. Mengungkit pertolongan kepada orang lain akan menghilangkan pahala…”
“Iyah seperti tahu banyak soal agama?”
“Ya, aku dapat saat masih kecil dan waktu di sekolah. Ibu dan guruku banyak mengajarkan soal itu…”
“Sekarang, apa pekerjaan Iyah… Maksud saya, apa Iyah bekerja di Belawan atau kerja di
“Sebelum berkenalan denganmu beberapa jam lalu, saya memang bekerja. Sekarang menganggur. Iyah menyatakan berhenti dari pekerjaan yang membuat Iyah selalu dihantui dosa.”
“Maksud Iyah?”
“Sejak berkenalan denganmu, saya menyatakan berhenti sebagai pelacur!”
“Hstts… pelan sedikit, malu terdengar orang. Maksud Iyah, kau ayam di kapal ini?”
Iyah mengangguk.
“Sudah berapa lama?”
“Hampir empat tahun.”
“Kenapa berhenti?”
“Kalau kita berani memulainya, kita juga harus berani untuk menghentikannya kapan pun. Dan, saat inilah yang menurutku sangat tepat untuk berhenti dari profesi yang meng-asu-kan diriku! Profesi itu benar-benar seperti asu, tak kenal waktu dan tempat melakukan per-anjing-an asalkan ada imbalan uang, uang, uang…”
Berhenti sekejap. Iyah mengusap airmatanya.
“Aku memang anjing. Menjilat-jilati tubuh lelaki agar isi dompetnya keluar. Membuka lebar-lebar kedua pangkal paha supaya para lelaki mabuk dan lupa kalau ia telah membuka isi dompetnya untukku. Begitulah anjing. Begitulah monyet. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan lalu menjulurkan lidahnya dan meninggalkan orang yang telah memberinya. Tak pernah berterima kasih. Benar katamu, anjing itu tak berbudi!”
Anjinglah aku… Iyah terisak. Mematikan rokoknya yang baru diisap dua kali. Puntung rokok yang baru terbakar semili itu, ia remas-remas di dalam perut asbak.
kau dengar hatiku yang sepi? katamu. menunggu abu dan
puntung rokok, di antara tawa dan patahhati!
tiba-tiba kita bersapa: berapakah harga pertemuan
dan perpisahaan?
amboi, perjalanan yang bermil ini sampai juga
di liang asbak. mengukur panjang cinta dan
khianat. tapi apakah kau tahu, luka bisa
pula tumbuh dari dalam asbak?
seribu waktu pernah mati di lambung asbak. tapi,
lantaran kesetiaan aku akan siap dilumat
oleh senyum dan ketulusanmu. seperti seorang aktor
akan tenggelam dan mati oleh lampus cahaya!
kesetiaan selalu abadi. meski luka oleh api,
asbak tak akan mau berubah nama! 2)
*
IYAH mengajakku mencari angin, seusai bar itu tutup. Duduk di kafe yang masih buka di buritan kapal, kami kembali meneruskan obrolan. Orang-orang menatap kami.
Pemilik kafe menyapa Iyah. Genit. Iyah hanya tersenyum. Membawa dua botol sprite ke mejaku. Iyah meletakkan dua botol minuman itu dan berbisik padaku: “Mereka tak tahu kalau saya sudah tidak seperti biasanya…”
“Tak harus Iyah beritakan kepada mereka. Biarkan Tuhan saja yang tahu. Seperti ketika Iyah memilih profesi itu…”
“Aku tidak memilih. Tetapi, diperosokkan…”
“Cuma Iyah enggak punya keberanian keluar dari jurang itu,
“Awalnya jelas beda. Tetapi kemudian, karena aku menganggap profesi ini mengasyikkan dengan gampang memperoleh apa yang saya inginkan, akhirnya bukan lagi terperosok melainkan dengan sadar memerosokkan diri sedalam-dalamnya. Untungnya, kini aku hendak sekuat tenaga bangkit dari
“Sesungguhnya Iyah bisa…”
Iyah mengangguk. “Karena bertemu kau?”
“Memangnya aku malaikat?”
Iyah menggeleng. “Entahlah, setidaknya hampir seperti itu…”
“Aku bukan malaikat, bahkan hampir pun tidak. Aku manusia biasa, yang mungkin saja lebih nista dari Iyah…”
“Aku melihatnya tidak.”
“Iyah belum banyak tahu siapa aku…”
“Justru aku sudah lama mengenalnya, makanya aku banyak tahu tentangmu: dalam anganku, dalam mimpiku, dalam gemuruh kapal ini yang selalu membawaku dari Belawan ke
“Aku baru beberapa kali menumpangi kapal laut ini…”
“Tetapi, kau ada dalam impianku…”
“Iyah pelamun. Terlalu banyak melamun…”
“Untuk suatu impian, harus melamun lalu berusaha…”
“Dan, kini bukan lagi mimpi?”
“Masih dalam antara… Antara mimpi dan kenyataan.”
“Artinya….”
“Aku belum bebas benar, sebelum kapal ini menepi di dermaga Belawan.”
“
“Entahlah, apakah ia mengancam ataukah tidak,” jawab Iyah dengan suara pelan. Iyah menunduk. Memandangi lantai kapal yang kotor…
Dan, Iyah tidak bisa mengelak ketika seorang lelaki tiba-tiba berada di sisinya. Memegang kuat-kuat lengannya. Iyah tergagap. Ingin menolak. Lelaki itu makin kuat mencengkeramnya. Iyah berdiri. Memberontak. Menghindar dan lari. Menembus koridor kapal yang kelam. Aku segera mengejar. Memotong langkah lelaki itu yang juga mengejar Iyah.
Tetapi, kami terlambat. Terdengar teriakan penumpang di ujung koridor
“
“
“Kok, nekat berenang di lautan…”
Lalu gemuruh. Kapten kapal menjenguk ke laut. Aparat kemanan di kapal segera ke pinggir kapal sambil mengucek-ucek matanya yang baru bangun tidur. Kapal berhenti. Anak buah kapal diperintahkan untuk terjun ke laut mencari Iyah. Di malam gelap seperti ini, apakah tubuh Iyah bisa ditemukan lagi baik dalam keadaan bernyawa ataukah sudah jenazah?
Lagi-lagi aku berurusan dengan aparat keamanan. Lelaki yang menyebabkan Iyah lari dan melompat ke laut, menunjuk diriku sebagai teman ngobrol sebelum Iyah bunuh diri. Tentu aku membela diri. Aku jelaskan apa adanya. Aku katakan aku baru bertemu dia di bar dan melanjutkan percakapan di kafe di luar. Aku juga menceritakan kalau Iyah sudah berhenti dari profesi pelacur, begitu ia sampai di Belawan…
“Tetapi, Anda teman kencannya,
Aku menggeleng. “Ketika ia bertemu dengan saya, dia sudah berhenti jadi pelacur. Ia hanya menginginkan saya sebagai teman bincang di perjalanan, tumpuan curahan hatinya. Tidak lebih. Tetapi ketika lelaki ini datang dan memegangnya, ia berontak lalu lari. Terjadilah apa yang dilakukan Iyah. Melompat ke laut…”
Tak urung aku tetap dijadikan sebagai saksi. Lelaki yang kuanggap penyebab kematian Iyah juga dibawa ke kamar khusus, sampai kapal melabuh di Belawan.
*
Parman mengaku kepada petugas penyidik, ia membunuh istrinya itu karena sakit hati dikhianati. “Iyah kerap berselingkuh saat saya bekerja pada malam hari. Setiap saya jadi satpam yang tugasnya pada malam hari, istri saya memasukkan lelaki lain ke rumah. Bayangkan, apa saya tidak sakit hati? Saya bekerja itu
Ya, ampun! Ini dunia macam apa? Benar-benar asu, sungguh-sungguh monyet!
**
MENTOK, 23, 25 Februari 2003
Seorang copet melompat dari kapal cepat Bom Baru (
“
“Tapi, aku yakin suatu waktu di sini pun mereka tak akan diberi ruang juga,” jawabku santai tanpa eksresi. Meski air amarah dalam hatiku bergolak juga.
“Ya, mereka akan mencari ruang yang baru…”
“Kalau seluruh ruang sudah ditutup, tangan-tangan pencopet tak ada lagi, ya?” aku berujar.
“Ruang selalu dibuka, kalau pun tidak ya disediakan….” Desis Bayu. Zain, sahabatku dari Betawi menimpali, “Pengangguran membuat orang mencari ruang lain berekspresi, mislanya ya jadi pencopet, pencuri, perampok, penipu, dan banyak lagi…”
Ya!
“Lihat! Pencopet itu tertangkap!” Bayu berteriak. Kami berhenti di ujung dermaga. Bus yang siap membawa kami ke Pangkalpinang sudah menanti. Tak ada AC, pasti panas dan melelahkan di jalan, pikirku.
Penjahat pelabuhan itu diseret beramai-ramai dalam keadaan pingsan. Wajahnya sudah berubah: seperti diantup lebah. Bengkak dan lebam. Dari lubang hidung menanglir cairan merah. Mata kirinya sudah tak bisa lagi dibuka. Tangan kanannya pengkor. Dari kepala bagian kiri satu inchi di atas telinga, juga terlihat cairan darah.
“Aku yakin ia pasti masti….” Aku mendengar desis, tapi tak kutahu dari mana.
Bandar Lampung, 14 Oktober 2002
(Ditulis kembali, Maret 2003)
Catatan:
1) Teringat baris puisi Chairil Anwar
2) Teringat puisi “Nisan” Chairil Anwar
3) Puisi “Dongeng Asbak” (bagian 1 dari 4 bagian) karya Isbedy Stiawan ZS, ditulis di Banjarmasin—Lampung, 1998 (Datang dari Masa Depan: Antologi 37 Penyair Indonesia, Sanggar Sastra Tasik, Februari 2000, baca juga Aku Tandai Tahi Lalatmu, Gama Media, Januari 2003).
14. Hikayat Wajah
SELAMA hidupku, tak pernah merasakan kaget sehebat ini: kehilangan wajah. Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba wajahku raib. Tentu saja aku kaget sekaligus malu. Ke mana harus kusembunyikan diriku, kalau wajahku sendiri sudah tiada? Memang aku tak perlu menyembunyikan wajahku karena memang sudah tak punya wajah, tapi bagaimana pula aku mesti menyembunyikan diriku di hadapan orang ramai?
Akhirnya aku tak ingin ditemui orang. Aku mengurung diri di dalam kamar yang kuncinya hanya aku yang pegang. Istriku tak kubolehkan menjengukku. Juga ketiga anakku. Mereka, kalau perlu denganku, cukup berkomunikasi dari luar kamar. Malah kadang ia mengirim rekaman kaset jika mau berdialog cukup panjang, lalu kujawab pula dengan rekaman kaset yang tak kalah panjang.
Pada jam-jam makan, istriku atau salah satu anakku akan mengirimkan makanan ke tempatku. Lalu, aku makan dan minum. Setelah selesai aku kirimkan lagi melalui sela-sela ventilasi pintu yang sengaja kubuat. Kamarku sengaja tak kuhidupkan lampunya. Gelap. Orang yang di luar tak akan bisa melihat wajahku, sementara aku bisa melihat mereka. Aku seperti manusia kamar.1
Sejak kehilangan wajah, di kamarku sengaja kubuatkan kamar mandi dan buang air besar. Istriku mulai uring-uringan: ia memohon agar aku tak perlu bersembunyi di dalam kamar. Terimalah apa adanya, sebagaimana menerima petaka dan bahagia dari Tuhan. Ia juga berjanji tak akan meninggalkanku—maksudnya bercerai—betatapa pun aku sudah kehilangan wajah.
Katanya, “Toh, banyak pejabat, wakil rakyat, dan tokoh publik, secara fakta sudah kehilangan wajah, tak punya muka lagi. Namun, mereka tetap berani keluar rumah, bertemu kolega, dan macam-macam. Kenapa Bapak tidak berani? Kalau Bapak tak merasa berdosa dengan kami, orang lain, apalagi rakyat banyak, kenapa mesti risih? Kenapa malu? Kenapa sembunyi-sembunyi segala?”
Sebenarnya masih panjang ucapan istriku yang direkam di dalam kaset yang dikirimkan kepadaku. Misalnya, ia bilang, apakah karena wajahku banyak yang menyamai sehingga takut dipalsukan, direkayasa? “Memangnya kenapa kalau wajah Bapak mirip dengan orang lain? Siapa tahu seorang jenderal, presiden, atau menteri? Kan yang bangga kita juga. La, orang yang mirip artis saja seneng-nya bukan main…”
Aku terdiam mendengar ucapan istriku yang direkam melalui pita kaset yang baru saja dikirimkan ke kamarku. Aku hampir saja menangis menyimak pertanyaan-pertanyaan istriku. Aku menangis karena sedih, sebab masih terlalu banyak yang belum diketahui istriku tentang diriku. Aku bayangkan istriku mengucapkan semua itu, lantaran sudah tak tahan lagi merasakan kesepian. Ya, sudah hampir sebulan ini, aku tak lagi tidur seranjang. Aku juga tak memberi uang makan sehari-hari. Untungnya aku punya tabungan di bank, dan dari sanalah istriku menutup keperluan sehari-hari.
“Jawab, Pak…” kata istriku dari bilik pintu. Istriku berharap aku mau menjawab pertanyaannya yang direkam kaset barusan.
Aku diam. Kupikir belum waktunya aku menjawab semua pertanyaannya. Aku malas. Aku kecewa, setiap kali mengingat kenyataan seperti ini: kehilangan wajah. Siapa pula yang berani mencuri wajahku, padahal ia menempel di tubuhku? Bukankah kalau wajah dipretel dari tubuh, pemilik wajah bisa mati? Kenyataannya, aku tidak. Ini benar-benar ajaib, mukjizat (?), keanehan yang luar bisa. Itulah sebabnya, baru kali ini aku merasakan kekagetan yang sangat dahsyat sepanjang hidupku!
Tetapi, aku tak bisa protes karena siapa pencurinya pun aku tidak tahu. Sialnya, wajahku hilang dari tubuhku saat aku terlelap. Seperti seorang dokter saat melakukan pembedahan, aku tak merasakan apa-apa. Aku tersadar begitu bangun, wajahku sudah tak ada lagi. Anehnya, kalau itu pembantaian, tak ada darah menodai tempat tidurku. Aku hanya bisa meratapi nasibku, menyesali takdir—kalau ini benar-benar takdir Tuhan—kenapa aku kehilangan anggota tubuh yang amat berharga?
Kalau aku harus memilih, lebih baik dan lebih ikhlas aku kehilangan harta, daripada kehilangan wajah. Sungguh kasus ini amat naif sekaligus tak masuk akal. Tak masuk akal? Ya, kendati ini fakta. Banyak orang kemudian mendatangi rumahku, ingin membezuk atau katakanlah ingin melihat sesungguhnya yang terjadi pada diriku. Mereka ingin membuktikan apa yang mereka dengar dari cerita atau berita di koran dan televisi bahwa wajahku telah hilang.
Melalui istriku, mereka berharap aku bisa menampakkan diri barang semenit saja. Mereka cuma ingin bukti. Ibarat seorang wartawan, perlu cross check alias konfirmasi. “Soalnya, pemberitaan yang mereka baca dan dengar, semuanya hanya dari satu sumber. Mereka ingin langsung melihat atau setidaknya mendengar langsung dari Bapak!” ujar mereka sebagaimana yang diutarakan istriku.
Aku malas menjawab. Aku ingin melihat reaksi masyarakat dengan kabar yang diterima apa adanya. Dan, benar, reaksi yang kemudian kudengar sungguh-sungguh beragam dan cenderung simpang siur antara yang satu dengan lainnya. Ada yang menudingku hanya ingin mencari popularitas. Yang lain mencurigai hendak mencari kekayaan, misalnya, dengan banyak yang berkunjung ke rumahku lalu mereka mengeluarkan uang tanda simpati atau turut berdukacita.
“Mungkin suami Jeng punya utang banyak di kantornya, jadi takut ditagih atasan lalu membuat rekayasa seperti itu?” kata tetanggaku lainnya. Masak iya, kalau aku punya utang, apalagi dengan kantor dan besar, istriku tak tahu sama sekali?
Terhadap kecurigaan atau pun tudingan itu, aku pun tak bereaksi. Masyarakat hanya bisa menuding, menyalahkan, mencurigai, tanpa pernah menyelami perasanku ketika harus kehilangan wajah. Sialnya mereka tak memerolehnya dari sumber korban. Karena itu ebih baik aku diam, dan aku percaya dengan peribahasa bahwa diam adalah emas.
**
“TIDAK bisa, Pak. Zaman sekarang peribahasa itu sudah tak berlaku lagi. Semakin Bapak diam, orang makin mencurigai macam-macam,” kata istriku lagi melalui kaset rekaman. “Barusan saja di warung Bik Minah, Ibu-Ibu bergunjing kalau Bapak itu bohong. Pendusta kelas wahid. Demi sesuatu yang besar: ketenaran. Jadi selebritis tanpa pengorbanan! Aku malu, bapak. Malu mendengarnya. Ayolah keluar. Tunjukkan wajah Bapak sesungguhnya, biar masyarakat tahu kalau benar Bapak kehilangan wajah. Aku enggak bisa menjawab dengan pasti, karena aku sendiri tak pernah tahu kalau wajah bapak benar-benar hilang!”
“Keluar dari kamar ini? Untuk apa? Toh, kalau mereka tahu juga, mereka tak akan bisa mengembalikan wajahku yang telah hilang? Aku juga tak yakin, mereka bakal menemukan pencuri wajahku,” jawabku dalam rekaman pita kaset. “Aku juga bukan pejabat, wakil rakyat, tokoh publik, apalagi selebritis. Jadi, untuk kepentingan apa kalau aku mencari popularitas dalam kasus ini? Tolonglah hargai perasaanku. Katakan pada mereka yang masih mencurigaiku macam-macam, saat ini aku ingin ketenangan dan bukan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas, yang absurd!”
“Apakah bukan absurd kalau Bapak tidak mau keluar kamar?” sanggah istriku. “Justru mereka menilai sikap bapak yang selalu bersembunyi di kamar, jadi orang kamar, justru absurd. Tak masuk dalam logika berpikir kebanyakan orang. Bapak malah ditengarai tengah merekayasa sesuatu demi sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang sensasi. Tetapi, sekaligus dengan cara murahan!”
“Ah, kamu sudah termakan opini publik!” bantahku. “Kau ikut-ikutan dengan pendapat umum, tanpa pernah menyelami perasaanku yang kini tengah gundah-gulana karena kehilangan wajah! Semestinya kau jangan terpengaruh, sebaliknya ikut memikirkan bagaimana caranya menemukan kembali wajahku. Apa kau takut, kalau suatu ketika wajahku dipalsukan oleh orang lain demi kepentingan pribadinya? Misalnya, wajahku itu dimanfaatkan untuk merampok negara, membumihanguskan negeri ini. Dan, apa kau tidak lebih malu ketika melihat wajahku terpampang di sejumlah media massa sebagai penjahat?”
“Bapak jangan terobsesi macam-macam, yang bisa menghancurkan psikologis Bapak sendiri. Mana mungkin wajah Bapak dimanfaatkan seperti itu? Memangnya Bapak itu siapa? Kan tak ada keistimewaan? Lalu, untuk apa mereka memalsukan wajah Bapak, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi? Apalagi dijadikan penjahat? Jangan macam-macamlah Bapak…”
Aku makin enggan menjawab ucapan istriku. Lebih baik aku mengingat-ingat sejak kapan orang menginginkan wajahku. Apa alasan pencuri tiba-tiba sangat tertarik dengan wajahku? Apakah karena tampan? Apakah aku cerdas? Apakah wajahku punya pengaruh besar bagi suatu perubahan atau pendapat umum, jika wajahku dicuri dan dimanfaatkan untuk suatu kejahatan? Dan, berpuluh-puluh pertanyaan menggoda benakku. Sialnya, tak juga terjawab. Akhirnya aku terlelap.
Istriku lupa. Saat ini justru banyak orang dari kalangan tak istimewa diseret untuk dimanfaatkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Lalu ia terkenal, diberitakan setiap waktu oleh seluruh jaringan media. Hanya karena wajah mereka mirip atau sengaja dimirip-miripkan dengan seketsa wajah yang disebarkan.
“Kamu lupa…” aku bergumam.
Namun, pada siang hari aku dikejutkan gedoran pintu. Aku mendengar teriakan istriku memanggil-manggilku. Juga suara anak-anakku yang berteriak, “Bapak! Bapak! Bapak!”
“Ayo, keluarlah Bapak. Ini ada kejutan yang lebih dahsyat lagi!” istriku menambahkan dengan teriakan yang tak kalah dengan anak-anakku.
Kejutan? Ada berita apa pula, sehingga istriku mengatakan bahwa ada kejutah yang lebih dahsyat lagi? Apakah rumahku kebakaran? Apakah ada ledakan bom di desaku? Atau banjir? Aku tak mendengar semua itu. Aku juga tak mencium rumah yang hangus? Tak merasakan banjir memasuki rumahku. Lalu, kabar apa?
“Kau lihat di koran hari ini!” kata istriku.
“Kami juga melihat di televisi!” anak-anakku berteriak.
“Ada sketsa wajah Bapak. Benar-benar mirip! Makanya keluar dari kamar Pak, orang-orang kampung sudah berkumpul. Mereka ingin kepastian dari Bapak, apakah seketsa wajah yang mereka lihat itu benar-benar wajah Bapak? Mereka juga ingin mengucapkan sesuatu kepada Bapak. Ayolah keluar…”
Aku terpana. Tetapi, aku masih belum percaya. Bagaimana mungkin secepat itu orang menemukan wajahku? Aku malah yakin kalau wajahku yang raib itu sudah dimakan binatang buas, atau dilepar ke laut auat sungai dan hanyut entah ke mana. Sekarang gantian aku yang mencurigai orang-orang kampung, istriku, ataupun anak-anakku, yang ingin buat sensasi. Mereka juga, ternyata, ingin popularitas. Ingin dikenal. Mereka pembohong besar.
“Tidak!” teriakku dalam kaset rekaman. “Aku tidak percaya kalau wajahku sudah ditemukan. Terlalu cepatnya orang menemukan wajahku yang aku sendiri yakin sudah dimakan binatang buas, atau ditanam, atau hanyut di sungai maupun laut. Kalian jangan mengarang-ngarang, jangan membuat karangkan fiktif, rekayasa. Aku ingin tahu dulu siapa yang menemukan wajahku itu?”
“Polisi!” jawab istriku. “Cuma yang dipublikasikan mereka baru seketsa wajah Bapak!”
“Aku makin enggak percaya. Bagaimana mungkin polisi bisa menemukan wajahku, apalagi bisa membuat seketsanya yang mirip wajahku? Jangan percaya, Bu, itu pasti fitnah, pasti rekayasa. Toh, kalian sendiri bilang, aku bukan orang penting, orang kebanyakan? Kepentingan apa polisi memburu wajahku?”
“Mereka tidak memburu, kalau aku tidak meminta bantuan mereka,” istriku menjawab. “Tolonglah keluar, Pak, aku lakukan ini demi kebahagiaan Bapak, demi keutuhan rumah tangga kita, demi anak-anak kita yang sudah begitu rindu pada Bapak…”
“Ya, aku juga merasakan itu, Bu. Aku amat tahu. Aku juga tersiksa di dalam kamar ini terus-terusan. Aku janji akan ke luar, kalau wajahku kembali,” ucapku kemudian. Kataku lagi, “Semula aku yakin wajahku bakal ditemukan kembali bersama pencurinya, tetap kemudian aku tak lagi mengharapkannya…”
“Tak mengharapkan? Bapak sudah gila, apa? Banyak orang menginginkan wajah, justru Bapak tak membutuhkan wajah saat wajah itu ditemukan. Bapak depresi, mesti diperiksa dokter kejiwaan!” teriak anak tertuaku.
“Bapak jangan membuat kami gila!” teriak yang bungsu.
“Sebaiknya kalau mau gila, cukup Bapak seorang! Tapi, kami berharap Bapak tidak gila. Maka itu keluar, lihat seketsa wajah Bapak ini! Ayolah, Bapak…” istriku merayu.
“Tidak! Sekali lagu kukatakan tidak, maka tetap tidak! Aku tak percaya seketsa itu adalah wajahku. Mana mungkin orang secermat itu membuat seketa, sementara wajahku dibawa kabur pencuri? Pokoknya aku tidak percaya. Dan, aku tak mau keluar!”
“Ini benar-benar seketsa wajah Bapak!” teriak anak-anakku kembali. “Tapi…” kudengar ketiga anakku dan istriku menangis menggerung-gerung. Riuh. Mengiba-iba. “Kenapa Bapak lakukan itu? Kenapa Bapak ledakkan bom itu hingga ratusan nyawa melayang? Kenapa Bapak jadi teroris?”
“Kau bukan Bapakku!” pekik anak sulungku. Lalu terdengar langkahnya menjauh.
“Tidak, ia tetap suamiku!” istriku membalas.
Kurebahkan tubuhku di dinding kamar. Benar apa yang kukhawatirkan, wajahku bakal dimanfaatkan untuk suatu kepentingan yang sangat besar. Prestise. Kemudian aku tak sadar untuk beberapa lama. Mungkin tertidur. Barangkali juga aku bermimpi.
***
SELAMA hidupku, tak pernah merasakan kaget sehebat ini: kehilangan wajah.Tentu saja aku kaget sekaligus malu. Dan, aku tak pernah merasa bangga ketika dikabarkan wajahku ditemukan lagi siang ini. Sebab wajahku yang ditemukan pihak polisi ini dan masih dipublikasikan dalam betuk seketsa itu ada di mana-mana dan dikenakan oleh siapa saja. Termasuk para tersangka peledakan bom di sejumlah tempat. Sungguh aku benar-benar sedih, ingin rasanya semua ini benar-benar mimpi…
Lampung, 2002-11-18
15. Kota
akan ke mana bintang pergi
bila malam tiada langit1)
LANGIT memang pekat di
Ya.
Aku orang pendatang. Pelaut yang seakan terdampar di sebuah pulau tanpa nama. Dan, aku memang tak tahu apa nama
Sampai suatu ketika, seorang kaphe tahu benar untuk menundukkan penduduk
Orang kaphe itu yakin benar, bahwa dengan menginjak-injak kitab suci atau membakar rumah-rumah ibadah adalah pekerjaan bodoh dan segera akan mendapat kebencian masyarakat
Dan, sekali lagi dan… sejak itu
Kalau masa penjajah, seluruh hasil bumi dikeruk ke luar negeri. Maka saat-saat merdeka, hasil bumi diangkut ke pusat.
Karena itu, akan ke mana bintang pergi/bila malam tanpa langit? Di
Begitu matikah
Jika kemudian penduduk
Lalu, sebagian penduduk, melakukan perlawanan. Memanggul senjata, menodongkan senapang, menembaki para musuh yang mengganggu. Dan,
Bertahun-tahun, sayang, bertahun-tahun.
Perjuangan tak selesai-selesai. Peristiwa mencekam silih datang dan pergi.
Salahkah jika penduduk
Sebab, kata mereka, hanya dengan hukum Tuhan maka hidup bersosial tidak akan bergolak. Hukum yang mutlak, tak perlu ada tafsir-tafsir menurut kadar keuntungan pribadi. Hanya saja, perjuangan untuk itu amatlah berat. Orang-orang kaphe tak akan pernah senang sebelum kalian mengikuti milah-nya.
**
DEMIKIAN, orang-orang kaphe tak hanya mengirim serdadu ke
Lalu cobaan itu didatangkan Allah. Bencana dahsyat itu telah meluluhkan sebagian
Dan, bagi orang-orang yang beriman, bencana yang dahsyat itu adalah benar-benar ujuan; cobaan yang datang dari Tuhan. Sedangkan bagi orang-orang kaphe maka bencana itu adalah azab. Tinggal kini, kau mau memaknai apa?
Sedangkan aku hanya bisa menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan di sembarang tanah setiap jengkal kita melangkah. Rumah-rumah atau bangunan yang luluh-lantah. Semuanya diterjang air besar yang datang tiba-tiba. Air yang dimuntahkan dari laut. Dikirim oleh tangan yang mahagaib!
Entahlah. Boleh jadilah….
Lampung, Januari, Maret, Juli 2005
16. Sonar Melanesia
TIMIKA, jam 13.40. Pesawat yang kutumpangi dari
Ya! Itu jika pesawat mendarat dengan ciamik. Seperti yang dilakukannya selama ini. Sebagaimana pesilat yang tak pernah melakukan kesalahan sehingga harus menjadi pecundang.
Kalau tidak? Ah, tak pula akan kubayangkan. Aku ingin sekali menikmati keindahan penerbangan ini. Menikmati kehijauan belantara dan gunung-gunung yang membiru. Dari udara ini. Kabut memutih yang menutupi sebagian daratan Papua. Danau bagai sekeping kolam susu. Sungai yang layaknya ular. Meliuk-liuk dan mengecil di ujung
Tak lama singgah di Timika. Cuma transit. Tapi sudah cukup bagiku menghirup udara daratan hitam yang kaya. Di sini ada tambang emas. Dan di sini pula, dulu pernah terjadi kerusuhan.
“Kita orang tak butuh pendatang!”
“
“Tanah ini haram bagi kaki kalian!”
“Pergiii….”
“Serbuuuuu….”
Mereka membawa busur dan anak panah. Mengayunkan tombak. Menujah udara. Sekelebat bayangan menyeramkan itu seakan mengusik lamunanku. Di pesawat ini. Dalam penerbangan menuju Jayapura. Padahal tak lama lagi aku akan sampai. “Di bandara akan ada orang yang menjemput,” demikian pesan yang masuk ke handphoneku. sewaktu di Makasar.
Aku tak ragu akan kesasar. Atau bimbang soal tujuan setelah turun dari pesawat nanti. Aku membayangkan setelah kuambil tasku yang diturunkan dari bagasi, seseorang atau lebih akan mendekatiku dan bertanya: “Anda mau ke kongres? Kami utusan panitia yang akan membawa Anda ke penginapan…”
Dengan perasaan bangga akan kujawab, “Ya.” Lalu kuminta salah seorang panitia membawakan tasku ke mobil. Setelah itu kunikmati perjalanan dari bandara menuju penginapan. Pastilah kendaraan yang kutumpangi melewati Danau Sentani yang menurut cerita teman-temanku yang pernah singgah di Jayapura, pemandangannya sangat menawan. Aku sempat menikmati keindahannya saat pesawat tepat di atasnya. Teman seperjalananku tadi berulang-ulang merekam ke dalam kameranya.
Tetapi, aku menyukai gumpalan awan putih bercampur kebiru-biruan. Sepulang nanti aku akan meminta dicetakkan gambar itu. Kubayangkan aku tertidur di atas tumpukan awan itu…
*
Aku letih sekali meski waktu penerbangan dari
“Apa bapak mau ke pesta budaya?” tanya lelaki berusia 13 tahun, setelah pintu kubuka.
“Panitia sediakan mobil?” aku balik bertanya setelah menyilakan dia masuk.
Ia mengangguk.
“Tetapi bisnya sudah jalan setengah jam lalu.”
Aku tercenung sejenak.
“Kita naik taksi saja, pak. Hanya 30 ribu. Saya bisa mengantar bapak,” jelasnya seperti mengerti apa yang hendak kutanyakan.
“Boleh kalau begitu. Tunggu saya mandi dulu ya…”
Ia mengangguk.
Sepanjang jalan ia banyak menjelaskan tentang Jayapura—sebuah
“Tetapi saya dari Timiki. Apakah Bapak tadi transit di
“Ya. Ya.” Aku mengangguk berulang.
“Bapak banyak tahu soal Timikia?” ia bertanya lagi.
“Lumayan. Hanya yang saya ketahui dari pemberitaan di koran-koran.”
“Begitulah…”
“Maksud Sonar?”
“Timika sebenarnya kaya. Namun kami bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan. Seperti juga Sorong…” Sonar terdiam. Menunduk. Aku lebih tertarik pada rambutnya yang hitam keriting-meringkel. Kupegang setelah meminta izin darinya. Juga kalung terbuat dari tulang yang tergantung di lehernya.
Ia tersenyum. Gigi-giginya yang putih tersusun rapi menguar.
Lalu ia berkisah tentang ayahnya yang mati namun dianggap pahlawan oleh suku asli. Itu sebabnya, Sonar selalu bangga jika nama bapaknya disebut-sebut: Dominggus Ramandey Upessy. “Dominggus bukan saja pahlawan bagi masyarakat Timika—bahkan Papua, lenih dari itu: ia pahlawan bagi keluarga kami,” katanya berapi-api. “Walau saya harus kehilangan dia. Kitaorang tak punya pahlawan lagi setelah bapak tiada. Katanya ia mati ditembak oleh penjaga penambang….”
“Kau tak bersedih, Sonar?” tanyaku karena melihat tatapannya tak juga redup. “Seharusnya….”
“Orang papua tak boleh bersedih. Kitaorang tak lagi punya airmata. Orang hitam dari dulu tak diurus,” jawab Sonar. “Seduka apa pun orang papua tetap bersenang-senang, tetap mengunyah pinang,” dia menambahkan.
Aku terdiam. Mengagumi dia. Tak lama, sebab kami sudah sampai di tujuan. Berkali-kali Sonar menjelaskan tentang suku-suku di Tanah Papua. Ia juga fasih menyebut ke 29 kabupaten yang tersebar di Papua.
“Kau guide yang menyenangkan, sahabat kecilku,” aku bergumam. Seperti tahu apa yang ada dalam pikiranku, Sonar menyeringaikan gigi-giginya.
Aku mengaguminya karena keberaniannya menjelajahi
Ketika kami berpisah di hote, dengan senang kumasukkan ke sakunya 100 ribu rupiah. Awalnya ia menolak, tetapi makin kutenggelamkan ke dalam saku celananya. Esok sore ia janji akan menjemputku di arena kongres untuk menemaniku jalan-jalan. Ia juga berjanji akan memberiku kalung terbuat dari tulang hewan.
Malam ini kubayangkan Sonar. Ingatan dan kenangan padanya membuatku sulit sekali terlelap. Lelaki hitam dari tanah merah itu telah mengusik hatiku. Aku ingin menjadikan sahabat kecilku, esok hari dan esoknya lagi.
*
SONAR datang ke hotel, tapi aku maish berada di ruang kongres. Demikian ia mengadu ketika kami berjumpa sore hari di ruang rapat kantor Pemda Papua yang menghadap laut. Ia katakan sepulang sekolah setelah makan dan ganti pakaian, ia langsung ke penginapanku.
“Saya sudah dapat izin dari mama,” kata Sonar yang kini tinggal bersama ibunya yang berdagang buah pinang. “Mama cuma pesan hati-hati,” ia menambahkan.
Ya! Hati-hati. Aku bergumam. Orang Papua memang harus sering hati-hati kepada pendatang atau tamu. Terlalu kerap mereka beramahtamah dan terbuka kepada tamu, tapi diakhiri dengan tak sedikit kekayaan buminya hilang. Seharusnya orang Papua itu kaya-raya. Seharusnya bisa mengalahkan rakyat Sultan Bolkiah. Penduduk Papua cuma 2.233.530 jiwa pada 2001 dengan keluasan mencapai 21,9 persen dari luas Indonesia, atau luas daratan seluruhnya 410.660 kilometer persegi. Lalu, mengapa mereka tak bisa kaya-raya?
Sonar terpaku. Tiada jawaban. Mungkin juga ia tak punya jawaban. Tubuhnya menyender di sebatang tembok di tepi laut depan Kantor Gubernur. Matanya tajam menatap para penjual buah yang berbaris di trotoar. Semua pedagang itu berkulit lebam dan rambut keriting.
“Sonar, apa kau tak rindu Timika?” aku membuyarkan lamunannya.
Ia memandangku nyalang. Aku seperti menyaksikan kobaran api di matanya, belantara pekat, gunung emas mentah. Api belantara emas. Belantara emas api. Silih berganti.
“Itu tanah kelahiranku. Darah pertamaku tumpah di
“Kau pernah pulang selama kau tinggalkan Timika?”
Ia menggeleng. “Mama tak punya ongkos pesawat…”
Hening sejenak. Kami mengalihkan pandangan ke deburan ombak yang menjilat tepi pantai. Kemudian telunjuknya mengarah ke bukit di tengah laut. Ia pasti hendak menunjukkan Menara Salib di atas bukit itu. Tetapi urung. Mungkin ia tahu kalau kami berbeda agama. Sebenarnya tak masalah kalau ia mau menjelaskan sejarah pembangunan Menara Salib itu. Sebagai tamu aku akan mendengarkan dengan baik.
“
Ia diam. Kemudian menggeleng.
“Tak ada yang menarik kuceritakan. Setiap orang punya Tuhan yang selalu melindunginya…” jelasnya kemudian.
Setelah itu ia memintaku untuk mengabadikannya dengan kamera digitalku. Ia berdiri dengan latar belakang Menara Salib. Aku memencet beberapa kali tombol kamera. Kuperlihatkan hasilnya pada Sonar. Ia sumringah. “Kirimi aku kalau sudah dicetak ya?” Sonar berharap. Aku mengangguk.
Sampai matahari terbenam di balik laut dan lampu jalan di tepi laut itu menyala, kami pun beranjak. Ia menyetop taksi (sebenarnya lebih tepat angkutan
“Kalau sekolahku berhasil, baru aku pulang ke Timika,” kata Sonar setelah kami menyantap makanan. “Saya mau mama pulang juga ke Timika, karena di sanalah kampung kami.”
“Tapi, Jayapura ini tanahmu juga. Bahkan
“Aku mencintai Timika. Saya ingin orang Timika menjadi pintar supaya tak dibodohi oleh pendatang,” katanya kemudian. Tersirat kekecewaan bercampur kebencian setiap kata yang diucapkannya.
Meski aku pendatang, namun aku tak tersinggung. Bahkan aku tersenyum, sebab kuyakin kata-katanya bukan untukku. Apalagi, selayaknya pelaut, aku hanya singgah sejenak untuk kemudian berlayar kembali.
“Maaf, yang kumaksud pendatang bukan Bapak. Tetapi….”
“Ya, saya memahami. Saya pernah jumpa dan mengobrol dengan orang Papua lainnya. Juga orang Jawa di sini,” kataku kemudian.
Tadi, saat makan siang di kongres, aku mengobrol dengan orang Jawa yang sudah menetap lama di Jayapura dan orang Papua sendiri. Menurut orang Jawa itu, justru yang kerap membuat kerusuhan adalah pendatang. Orang Papua sendiri malah ramah dan pasrah.
“Yang banyak membuat keonaran malah pendatang. Terutama orang Jawa, mereka hanya suka menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Padahal seharusnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya sering mengingatkan para perantau agar menghormati budaya dan bahasa daerah sini. Orang Papua itu amat sederhana, rindu persaudaraan,” kata Slamet Sukiran, salah satu peserta kongres.
Sedangkan Marcus Krey hanya manggut-manggut. Tersenyum. Memamerkan gigi-giginya yang berwarna merah karena buah pinang. “Bukan begitu, Krey?” Yang ditanya kembali mengangguk.
“Maaf, Pak!” Sonar membuyarkan kenanganku. Kutatap wajahnya. Ia seperti meminta bantuanku. Aku mengangguk. Tersenyum. “Saya lupa sudah janji mau jemput Mama… Ah, dia pasti sudah lama menunggu.”
Segera kugamit lengannya. Meninggalkan ruang makan di mal terbesar di Papua. Segera kustop taksi. Di suatu sudut jalan ia turun. Melambaikan kedua tangannya setelah menginjakkan kaki di tepi jalan. Kusambut lambaiannya. Aku kembali ke hotel.
*
MALAM ini aku menulis
Aku tak hendak melukai hatinya. Tak sampai hati…*
Dalam penerbangan Jayapura-Jakarta, 25 Agustus 2005 (ditulis dengan communicator 9210i) —Lampung, September 2005
catatan:
· judul cerpen ini saya ambil dari nama lelaki yang kini masih bersekolah di SMP Negeri 1 Jayapura (kelas 2): Sonar
· Sepanjang jalan di Papua atau di sudut gedung dan kotak sampah selalu saya lihat bercak merah bekas pinang. Masyarakat Papua memiliki tradisi makan pinang (inang), karena itu pula pada Festival Teater Nusantara di Bandung seniman Papua menampilkan lakon “Lelaki dari Tanah Merah”.
Tentang Publikasi
Cerita pendek dalam buku ini sampai 13 September 2005, di antaranya pernah dimuat di pelbagai media massa seperti: “Pertempuran hingga Pagi” (Sumatera Post, 2005), “Kupu-Kupu di Jendela” (Suara Pembaruan, 13 Maret 2005), “Ibu Berperahu Sajadah” (Horison, April 2005), “Perempuan yang Berenang saat Bah” (Republika, April 2005), “Sarmi Hamil” (belum dipublikasikan), “Lelaki Asing di Gedung Pertunjukan” (belum dipublikasikan), “Pintu Vila itu Dibiarkan Terbuka” (belum dipublikasikan), “Hanya untuk Satu Nama” (Kompas, April 2005), “Batas Rencana” (belum dipublikasikan), “Pasien Terakhir” (Lampung Post, 28 Agustus 2005), “Batu itu Tak Terbang ke Langit” (Media Indonesia, 26 Juni 2005), “Perempuan di Ladang Tebu” (Nova, Oktober 2002),”Ruang Asap” (Horison, Agustus 2003), “Hikayat Wajah” (Lampung Post, November 2002), “Kota yang Selalu Mencekam” (belum terpublikasi), “Sonar Melanesia” (belum dipublikasikan)
KATA PENUTUP
Di Cerpen, Saya “Bebas Bermain”
WARTAWAN Mustafa Ismail dari Koran Termpo menulis profil penyair-cerpenis Isbedy Stiawan ZS untuk halaman Buku di media tersebut, dan narasinya telah dimuat edisi Minggu, 27 Februari 2005. Untuk menggali informasi penulisan profil tersebut, berlangsung wawancara tertulis antara Mustafa Ismail dengan Isbedy Stiawan ZS melalui e-mail. Mengingat pentingnya pandangan Isbedy terhadap kepengarangannya, berikut kami muat hasil wawancara tersebut.
Kapan awalnya menulis? Bagaimana ceritanya?
Saya menulis sekitar 1979 ketika gairah kepenulisan di Lampung masih sangat kering. Saya memulai menggeluti dunia seni dari teater. Saat-saat jeda latihan kami diskusi soal sastra, dan dari sanalah aku menulis sastra (puisi khususnya). Tetapi, sejak SMP saya banyak membaca karya-karya Ko Ping Ho, membuat saya dipengaruhi oleh pandangan Ko Ping Ho bahwa seseorang yang menyenangi seni tanpa memiliki ilmu beladiri akan lemah dan dizalimi, dan orang yang memiliki ilmu beladiri tanpa diimbangi nilai seni maka ia akan jadi zalim.
Saya lahir dari keluarga tidak mampu dan tinggal di DPR (daerah pinggiran rel). Untuk menghidupi 8 anak, ayahku yang menjadi pegawai rendahan di pemerintah membuat ibuku membuka warung kue dan kebutuhan sehari-hari di depan rumah untuk biaya hidup keluargaku. Pada waktu-waktu tertentu sebelum aku ke sekolah atau pulang sekolah, ibu menugaskan saya untuk menunggu warung. Sambil menanti pembeli itulah, aku sering melamun (mungkin istilah sekarang menerawang imajinasi kita) dan lalu menulisnya di secarik kertas. Istilahnya puisi. Hasil goresan itu aku kirim ke RRI Tanjungkarang untuk ruang remaja. Goresanku itu dibacakan dalam acara puisi remaja... Itu pada tahun 1979.
Anda lebih dikenal sebagai penyair, tapi belakangan terjun menulis cerpen juga---bagaimana ceritanya?
Benar saya lebih dikenal sebagai penyair. Saya diundang DKJ bersama 80-an penyair se Tanah Air pada Forum Puisi Indonesia tahun 1987, dan saya saat itu disebut-sebut sebagai penyair berbakat oleh Sutardji Calzoum Bachri dan Abrar Yusra sebagai pembicara pada forum terseut dan sebagai penyair berkecenderungan sufistik bersama beberapa penyair (muda) Indonesia lainnya, seperti Soni Farid Maulana, Acep Zamzam Noor, Nirwan Dewanto, Mathori A Elwa, dan lain-lain. Abdul Hadi WM juga di banyak tulisannya sering menyebut saya sebagai penyair berkecenderungan sufistik.
Tetapi jangan lupa bahwa karya saya pertama yang dimuat media
Saya makin intens menggeluti penulisan puisi selepas 1984. Ketika puisi saya mulai dimuat Berita Buana yang waktu itu digawangi Abdul Hadi WM pada 1986, lalu bermunculanlah puisi-puisi saya di media bergengsi saat itu seperti "Pendakian" Suara Karya, Budaya Pelita, Jayakarta, Terbit, Prioritas, dan seterusnya.
Pujian Sutardji pada puisi-puisi saya dalam Forum Puisi
Kalau kini saya menulis cerpen juga, disebabkan "lebih menjanjikan". Selain itu, ini yang terpenting, sangat menantang saya. Dalam menulis cerpen, saya harus banyak memiliki "tabungan” kata dan kalimat, harus banyak memahami seluk-beluk alur cerita, penokohan, beserta konflik-konfliknya. Memang awalnya saya menganggap menulis cerpen untuk jeda saja, ketika saya sudah merasa jenuh dan kehabisan ide lantara terlalu produktif menulis puisi. Maka saya harus istirahat dulu menulis puisi sehingga puisi-puisi saya tak monoton atau tiada peningkatan kualitas.
Ternyata mememang cerpen "lebih menjanjikan" ketika booming prosa di pasaran dan penerbit berbondong-bondong lebih besar perhatiannya menerbitkan buku cerpen ketimbang puisi. Dengan demikian, penulis cerpen seakan merayakan pesta booming itu. Kenapa tidak, saya juga turut merayakan pula. Ditambah lagi cerpen-cerpen saya mulai diterima oleh media massa bergengsi seperti Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Horison, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan media lainnya. Padahal, sebelumnya saya minder sekali mengirimkan cerpen. Berbeda jika saya menawarkan puisi ke media-media tersebut. Bahkan, dengan nada canda, Triyanto Triwikromo (Suara Merdeka) tak mengakui saya sebagai cerpenis. "Kalau pun Anda mengirim cerpen tak akan kumuat, sebab kekuatanmu ada di puisi." Tetapi, belakangan cerpen-cerpenku lolos seleksi Suara Merdeka yang kita tahu Triyanto sangat ketat untuk meloloskan karya sastra. Begitu pula, tentunya, ketika Nirwan Dewanto meloloskan cerpen “Mata Elangmu Nyalang” di Koran Tempo. Cerpen ini mungkin kedua atau ketiga yang saya kirim ke Koran Tempo.
Produktivitas menulis cerpen memang saya akui cukup tinggi belakangan ini, itu tak lepas dari menyambut “perayaan” booming prosa di Tanah Air. Tetapi saya juga tergolong produktif melahirkan puisi. Kalau kemudian saya lebih dikenal sebagai penyair:, mungkinpredikat itu sudah demikian menyatu dalam diri saya sejak lama. Dan, terus terang, saya justru merasa percaya diri disebut penyair ketimbang cerpenis. Boleh jadi suatu waktu saya akan meninggalkan dunia cerpen. Hanya untuk saat ini saya masih bergairah menulis cerpen. Sebabnya cerpen lebih mendapat tempat di mata penerbit dan pembaca. Hal itu ditunjukkan dengan amat bergairahnya penerbitan buku-buku prosa (cerpen dan novel) ketimbang puisi. Terbukti pula Sapardi Djoko Damono atau Sutardji Calzoum Bachri menulis dan menerbitkan kumpulan cerpen.
Bayangkan bertahun-tahun saya geluti dunia penyair, hanya dua buku puisi yang dapat diterbitkan oleh penerbit bergengsi: Aku Tandai Tahilalatmu (Gama Media, 2003) dan Menampar Angin (Bentang Budaya, 2003). Selebihnya—4 kumpulan cerpen—saya diterbitkan nyaris berdekatan: Ziarah Ayah (2003), Bulan Rebah di Meja Diggers (Beranda, Agustus 2004), Dawai Kembali Berdenting (Logung Pustaka, November 2004), dan Perempuan Sunyi (Gama Media, Desember 2004). Pada 2005 ini yang dipastikan terbit: Selembut Angin Setajam Rantinmg (Lingkar Pena Publishing House, April 2005), Seandainya Kau Jadi Ikan (Gramedia, Meil 2005), dan Hanya untuk Satu Nama (Penerbit Bentang Pustaka) ini.
Artinya, cerpen memang benar-benar mendapat perhatian lebih. Ini yang membuat saya sedikit "banting setir" dari puisi ke prosa. Tentu saya tak pernah untuk mengabaikan penulisan puisi. Saya masih menulis puisi, ketika saya benar-benar ingin menulis puisi. Frekuensi keseriusan dalam menulis puisi saat ini benar-benar saya tingkatkan, sehingga saya tak hendak melahirkan puisi yang "sekadar" atau hanya memainkan tipografi namun tidak bermakna. Atau memainkan gambar, tetapi bahasa yang digunakan milik orang atau mencaplok dari yang ada: dasri puisi atau ayat kitab suci. Ditambah lagi, saya tidak punya kemampuan menciptakan sensasi-sensasi di dalam sastra demi popularitas.
Apa yang Anda harapkan dengan menulis cerpen?
Dalam menulis cerpen, saya banyak belajar dari mengamati berbagai karakter (tokoh) orang yang ada di sekitar saya. Saya dapat lebih memasuki setiap karakter tokoh, seting, atau alur cerita. Saya bisa bebas memainkan bahasa—sesungguhnya berperan penting bagi karya sastra—ketika menulis cerpen. Sementara dalam puisi, kewajiban saya ialah memadatkan imajinasi yang berkeliaran-berkelindan ke dalam kalimat-kalimat sebisa mungkin ekonomis sehingga tak kelewahan.
Harapan lain, saya ingin menghidupkan tokoh-tokoh dalam cerpen saya seakan benar-benar hidup. Tokoh-tokoh itu bisa saja saya, teman, orang tua, istri, ibu, atau pun anak. Tokoh-tokoh itulah, setelah cerita itu jadi, kembali berdialog dan berdiskusi dengan saya betapa pentingnya hidup lurus dan bersih. Betapa indahnya menengok hidup yang acap berzigzag. Tokoh-tokoh dalam cerita itu juga seperti membuka mata dan hati saya kembali: "kok ada ya tokoh seperti ini? Memang ada!" bisik tokoh-tokoh itu.
Buku-buku yang sudah terbit? Tolong ceritakan sedikit gambaran buku-buku itu
Saya menunjuk buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit yang sudah punya nama saja. Yaitu Aku Tandai Tahilalatmu adalah kumpulan puisi saya yang telah dimuat di sejumlah media
Kemudian kumpulan puisi Menampar Angin. Judul buku ini saya petik dari puisi saya yang dimuat Koran Tempo. Dalam kumpulan puisi kedua ini, saya banyak bermain pada tataran budaya melayu dan persoalan sosial di daerah pedalaman di Lampung. Meski banyak juga tema lain. Itu sebabnya seorang teman ketika mengupas buku saya itu, menyebutkan tema puisi saya beragam. Akhirnya ia mengambil bidikan ke satu persoalan, yakni soal waktu dalam puisi-puisi saya.
Setelah itu, kumpulan cerpen Ziarah Ayah, Bulan Rebah di Meja Diggers, Dawai Kembali Berdenting, dan Peremapuan Sunyi. Kumpulan Ziarah Ayah saya ambil dua cerpen di dalamnya—“Ziarah” dan “Ayah”—untuk judul buku tersebut. Sedangkan buku kedua, saya tertarik dan sekaligus juga sebenarnya saya hendak memromosikan tempat pariwisata yang di Bandar Lampung: Kafe Diggers. Sedangkan Dawai Kembali Berdenting memuat cerpen-cerpen seputar masalah keluarga dengan perniknya, cinta dan pengkhinatan, sosial, dan seterusnya. Begitu pula pada Perempuan Sunyi. Bertolak dari dua buku cerpen saya itu sampai perkembangan berikut, saya katakan telah terjadi perubahan dalam karya-karya cerpen saya dengan melakukan eksplorasi kisah ataupun
Mana di antara buku itu paling laku? Adakah laporan terus menerus dari penerbit soal ini?
Saya sulit mengecek secara pasti mana buku yang paling laku. Sebab penerbit terlalu abai melaporkan berapa buku yang sudah laku. Padahal, dalam
Tetapi, saya bisa memperkirakan Ziarah Ayah, Aku Tandai Tahilalatmu lumayan laku. Sedangkan kerja sama dengan Beranda yang menerbitkan Bulan Rebah di Meja Diggers sejak Agustus 2004, pada Februari lalu mentransfer royalti dari hasil jual buku selama 6 bulan.
Bagaimana dengan royalti atau honor buku? Cukupkah untuk hidup?
Tidak cukup untuk hidup mengandalkan dari royalti atau honor buku. Setiap penerbit menetapkan besar royalti sama: 10 persen dikalikan harga jual lalu dikurangi 35 persen untuk pembayaran distribusi buku ke pasar. Sebesar itulah yang akan diperoleh penulis. Lalu, kalau buku yang dicetak pada peluncuran pertama hanya 2.500 dengan harga buku Rp25 ribu dan taruhlah terjual habis sebesar itulah yang didapat penulis. Lalu royalti baru dicairkan 6 bulan sekali: biasnaya Januari dan Juli. Wah wah, rasanya tidak akan bisa mengandalkan hidup dari royalti buku. Untungnya, cerpen (puisi) dalam buku itu, sebelumnya sudah dimuat media
Belakangan Anda tidak lagi bekerja di media, apakah benar Anda total hidup dari menulis? Mengapa Anda memilih total menulis?
Saya berhenti bekerja dari media sejak 2001 ketika Trans Sumatera hanya bisa bertahan 2 tahun. Koran ini diawaki oleh jurnalis dan karyawan eks suatu media terbesar di Lampung. Sejak itu saya total hidup dari menulis. Saya "tumpangkan hidup" saya dari hasil menulis, meski ada kalanya kurang mencukupi. Tetapi saya menyukai karena dunia ini adalah pilihan yang mesti saya jalani. Sebab saya sudah memilih jalan hidup ini, maka saya mesti serius, konsisten, dan disiplin. Tidak seperti ketika saya masih punya penghasilan dari luar kepenulisan, saya suka menemui kawan-kawan dan mengobrol menghabiskan berwaktu-waktu. Kini tak. Saya harus punya jadwal "bekerja": dari pukul 07.30 hingga 12.00. Atau dari 19.30 sampai 01.00.
Mungkin saya sudah amat kecewa dengan kehidupan di belantara media. Saya bersama lebih dari 60 jurnalis dan karyawan dipecat dari sebuah media besar di Lampung, karena memrotes kebijakan pemimpin yang waktu itu kami anggap tidak sejalan. Tapi, pemecatan kami itu hingga sekarang tidak mendapat pesangon serupiah pun! Lalu kami bikin media baru, namun pemodalnya menghentikan suntikan dana pada saat tahun pertama terbit berlalu. Saya juga sudah berumur kalau harus bergelut di media
Bisakah hidup dari menulis? Kalau tidak bisa, bagaimana mencukupkan kebutuhan?
Untuk sampai hari ini saya masih bisa hidup dari menulis. Mengingat tulisan saya (cerpen dan puisi) kerap bermunculan di media
Bagaimana Anda melihat tingkat penghargaan kepada para penulis (penyair, pengarang, dll)?
Masih dan masih sangat jauh! Baik itu dari pemerintah, penerbit, media, sampai masayarakat. Berbeda bukan dengan olahragawan, atau bidang seni lain semacam perupa, penari, dan mungkin teater yang agak lumayan? Tetapi tetap saja, seniman masih di bawah bidang lain dalam menerima penghargaan. Politik, ekonomi, militer, dan olahraga masih menjadi panglima di negara ini. Kalau bidang-bidang itu masih disubsidi pemerintah cukup besar, tidaklah bagi kesenian. Meski kita punya data bahwa hasil PAD yang 10 persennya konon untuk membiayai kesenian, tetapi benarkah itu dilakukan oleh pemerintah? Berapa besar sih subsidi dari pemerintah untuk kesenian?
Apakah Anda merasa karya-karya Anda sudah cukup mendapat penghargaan?
Saya tak berani menjawabnya, karena ini sudah urusan penilaian. Dan yang berhak menilai karya kita layak mendapat penghargaan ataukah tidak adalah orang lain. Meskipun tidak setiap hasil penilaian menggembirakan semua pihak. Buktinya penghargaan terhadap buku sastra yang ada, acap kontroversial. Selain itu, tugas saya adalah berkarya dan berkarya. Dan saya akan berhenti setelah saya merasa tak mampu lagi melahirkan karya bermutu—dengan ukuran bahwa redaksi, editor, dan pembaca sudah tak menyukai lagi karya-karya saya.
Selama menulis (puisi dan cerpen), mana karya Anda yang paling berkesan buat Anda? Mengapa?
Semua karya yang saya lahirkan berkesan buat saya. Tetapi memang ada prioritas-prioritasnya. Puisi "Aku Baca Lembaran-Lembaran Koran" dalam antologi Forum Puisi
Sedangkan cerpen, saya menyukai "Meniti Sepi, Menanti yang Pergi" karena cerpen itu mengalir saja hingga rampung. Hal yang sama dengan "Mata Elangmu Nyalang", dimana saya mencoba bermain-main dengan imajinasi yang saya rasa lebih bebas.
Tolong ceritakan bagaimana proses kreatif Anda menulis?
Untuk karya puisi, saya banyak digoda oleh kalimat-kalimat seperti lahirnya puisi "Aku Tandai" meski ada pula yang kelahirannya tanpa sentuhan apa pun. Artinya saya hanya mengandalkan proses kreatif saat berhadapan dengan kyboard komputer. Saya termasuk orang yang sangat mudah tersentuh inspirasi. Karena itulah, seorang teman sastrawan Lampung melontarkan komentar: “Tersandung batu saja, di tangan Isbedy bisa jadi puisi!” Ah yang benar? Saya bertanya balik di dalam hati. Kalau demikian, betapa mudahnya menulis puisi dan menjadi sastrawan? Sungguh, komentar itu seharusnya datang dari kalangan di luar sastrawan. Sebab, semua sastrawan tahu, menulis tidaklah gampang…
Tetapi, saya akui, banyak karya saya yang lahir diawali oleh sentuhan-sentuhan sederhana. Contohnya, “Aku Tandai” yang disentuh oleh kalimat-kalimat yang dapat saat di kenderaan motor. Sesampai di kantor—saat itu saya bekerja di Trans Sumatera—saya “abadikan” di komputer, dan kalimat itu berhari-hari mengusik untuk diselesaikan menjadi puisi. Dalam proses kreatif kemudian, saya giring “tahilalat” itu sebagai penanda bagi manusia. Sementara pengalaman berbangsa menunjukkan bahwa banyak kasus pertikaian di negeri ini hanya ingin mempertahankan identitas suku, memperjuangkan marhwa etnis dan agama. Sehingga mengabaikan bahwa kita sebangsa: bersaudara atas nama
Hal yang hampir sama sebenarnya dengan penulisan cerpen. Misalnya, cerpen “Meniti Sepi, Menanti yang Pergi”, saya hanya mendapatkan kalimat pembuka (paragraf pertama) di kios koran sebelum saya membeli koran edisi Minggu. Paragraf pertama: “Kau tidak juga tersenyum, padahal sudah berulang kubikin lelucon di hadapanmu.
Saya ingat terus kalimat-kalimat yang saya dapatkan begitu saja saat di mana pun, seakan saya khawatir kehilangan nuansa kisahannya. Pada saat itu saya tak mau disibukkan oleh bagaimana alur ceritanya, siapa saja tokoh-tokoh yang akan memainkan peran di dalam cerita saya nanti, dan bagaimana seharusnya saya sudahi cerita itu. Tugas saya ialah menangkap nuansa itu untuk saya tuangkan ke tulisan, dan pada proses kreatiflah sebagai penulis sekaligus dalang menentukan. Bisa saja saya ikut terbawa ke dalam kisah tersebut, saya biarkan.
Oleh karena itu, saya kadang tak begitu memikirkan endingnya bagaimana, sehingga bisa saja malah akhir dari cerpen saya dapati saat proses kreatif. Tetapi, ada juga yang sudah saya pertimbangkan sebelum menulisnya. Salah satunya ialah cerpen "Terompet", saya mesti menutupnya dengan ucapan ini: "Kalau kau masih mencintaiku, dan demi Nina..... aku ikhlas menjadi istri pertamamu." Cukuplah saya mendapat moment-moment cerita, lalu saya garap menjadi cerpen.
Ketika gempa dan tsunami menimpa Aceh dan Sumatera Utara, kiranya turut menyuburkan kreativitas saya. Sekitar 5 cerita dan beberapa puisi lahir untuk menyikapi bencana itu. Setelah sebuah puisi yang saya bacakan pada malam penggalangan dana yang diadakan Pememerintah Provinsi Lampung (29 Desember 2004), saya mendapat ide menulis cerpen “Gelombang Besar di Kota itu”. Untuk menyiasati cerita ini, saya teringat kisah kaum Luth dan Nuh. Pada zaman Luth yang kaumnya banyak durhaka akhirnya Tuhan membalikkan bumi, sedang di zaman Nuh yang berkhinat itu maka Tuhan mengirim bah hingga menengelamkan bumi. Untuk menyampaikan kisah ini saya menciptakan tokoh ibu, dan dari tokoh inilah kisah antara zaman Luth, Nuh, dan apa yang terjadi di Aceh (saat ini). Cerpen “Ibu Berperahu Sajadah” saya teringat dengan pengalaman seorang ibu Aceh yang selamat dari gelombang tsunami dengan tetap memegang alQuran. Ibu itu bercerita, saat kejadian ia baru saja selesai salat dhuha dan tengah membaca alQuran.
Dalam menulis cerpen, saya bisa menyelesaikan satu cerpen hanya dua jam atau kurang, tetapi bisa juga berhari dan berbulan atau tahun. Cerpen “Gelombang Besar di Kota itu” hanya saya selesaikan tak kurang dua jam dan dimuat Jawa Pos dimuat 2 Januari 2005 hanya selisih sehari dari pengiriman saya 30 Desember 2004 malam. Beitu pula “Terompet” yang saya tulis 27 Desember 2004 dan dimuat Kompas 16 Januari 2005.
Kegiatan lain selain menulis?
Tidak ada, kecuali sebagai kepala keluarga, Ketua Program Dewan Kesenian Lampung, dan Sekretaris AJI Lampung. Sesekali diminta jadi narasumber dalam sebuah diskusi, juri baca dan cipta sastra...
*) Mustafa Ismail, lahir 25 Agustus 1971 di Pidie, Aceh. Alumni STIEI Banda Aceh jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan ini menulis puisi, cerpen, dan artikel. Kini menjadi wartawan Koran Tempo
TENTANG PENULIS
Isbedy Stiawan ZS lahir di Tanjungkarang (Lampung) pada 5 Juni 1958 dan hingga kini masih menetap di
Karya-karyanya—puisi, cerpen, dan esai--dipublikasikan di berbagai media massa antara lain Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, Suara Karya, Jwa Pos, Suara Merdeka, Sinar Harapan, Horison, Amanah, Nova, Citra, Annida, Sabili, Tabloid Fikri, Surabaya Post, Kedaulatan Rakyat, Bali Post, Serambi Indonesia (Aceh), Pikiran Rakyat, Riau Pos, Lampung Post, Majalah Budaya Sagang, Jurnal Cerpen, Jurnal Puisi, Majalah Sastra Tepak, dan lain-lain.
Kumpulan puisi tunggalnya antara lain Roman Siti dan Aku Selalu Mengabarkan (LSM Perempuan DAMAR, Bandar Lampung, Juli 2001), Aku Tandai Tahi Lalatmu (Gama Media, Yogyarakta, Januari 2003), Menampar Angin (Bentang Budaya, Jogjakarta, Oktober 2003), kumpulan cerpen Ziarah Ayah (Syaamil Bandung, Mei 2003)., Bulan Rebah di Meja Diggers (Beranda Jakarta, Agustus 2004), Dawai Kembali Berdenting (Logung Pustaka Yogayakrta, November 2004), Perempuan Sunyi (Gama Media Yogyakarta, Desember 2004), kumpulan cerita anak Dongeng Sebelum Tidur (Beranda Jakarta, September 2004), kumpulan cerpen Selembut Angin Setajam Ranting (Lingkar Pena Publishing House, April 2005), dan Seandainya Kau Jadi Ikan (Gramedia, Mei 2005).
Karya-karyanya juga masuk di sejumlah antologi bersama seperti Dari Negeri Poci, Dari Bumi Lada, Resonansi Indonesia, Angkatan 2000, Horison Sastra Indonesia, dari Fansuri ke Handayani, Hijau Kelon dan Puisi 2002 (Penerbit Buku Kompas, 2002), Puisi Tak Pernah Pergi (Penerbit Buku Kompas, Juli 2003), 20 Tahun Cinta (Penerbit Senayan Abadi Jakarta, Juli 2003), Wajah di Balik Jendela (Penerbit Lazuardi Jakarta, Agustus 2003), Anak Sepasang Bintang (FBE Press Jakarta, 2003), Bunga-Bunga Cinta (Senayan Abadi, 2003), Jika Cinta… (Senayan Abadi, 2004), Cerita-cerita Pengantin (Galang Pres, Jogjakarta, Mei 2004), serta sebuah monolognya masuk nominasi 12 besar lomba naskah monolog Anti-budaya Korupsi Nasional dan terhimpun dalam antologi monolog Sphing Triple X (Sinergi Yogyakarta, Agustus 2004).
Pernah diundang Dewan Kesenian Jakarta membacakan puisi di TIM pada Forum Puisi
1) puisi “Perjalanan Pelaut”, Isbedy Stiawan ZS (1986)
2) bait puisi “Air Raya: 27 Ribu Mayat Terhampar”, Isbedy Stiawan ZS; dan puisi ini ditulis pada 29 Januari 2004 untuk dibacakan pada penggalangan dana Pemerintah daerah Provinsi Lampung di Balai Keratun Pemda Lampung, 29 Januari 2004 malam. Waktu itu baru 27 ribu orang yang ditemukan tewas akibat musibah gempa dan tsunami di Aceh dan Nias (Sumut). Tentang “Air Raya” dikutip dari cerpen Azhari (Aceh) yang dimuat Kompas (2004).
1) ucapan Rendra dalam satu puisinya, maaf saya lupa judul puisinya.
2) perempuan (bahasa Aceh).
1) Ebiet G. Ade dalam salah satu lagunya, jika beristri nanti ingin punya rumah di pinggir sawah
1 teringat cerpen “Manusia Kamar” Seno Gumira Ajidarma, namun tidak ada kaitan (pengaruh) dengan lahirnya cerpen saya ini. Kalau persitiwa di dalam cerpen ini ada kemiripan dengan kejadian yang saat ini masih menempati urutan pertama pemberitaan media, boleh jadi sebagai pemicu untuk tulisan ini. Tentu saja cerpen tetaplah karya sastra, sehingga punya banyak kacamata untuk melihatnya.
1) baris puisi Isbedy Stiawan ZS, “Bintang Pergi” (2005)
2) teringat puisi Fikar W. Eda, “Seperti Belanda” yang acap dibacakan oleh penyairnya.


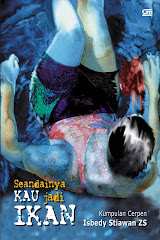



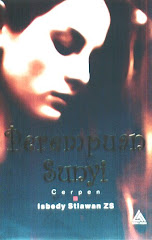







Tidak ada komentar:
Posting Komentar